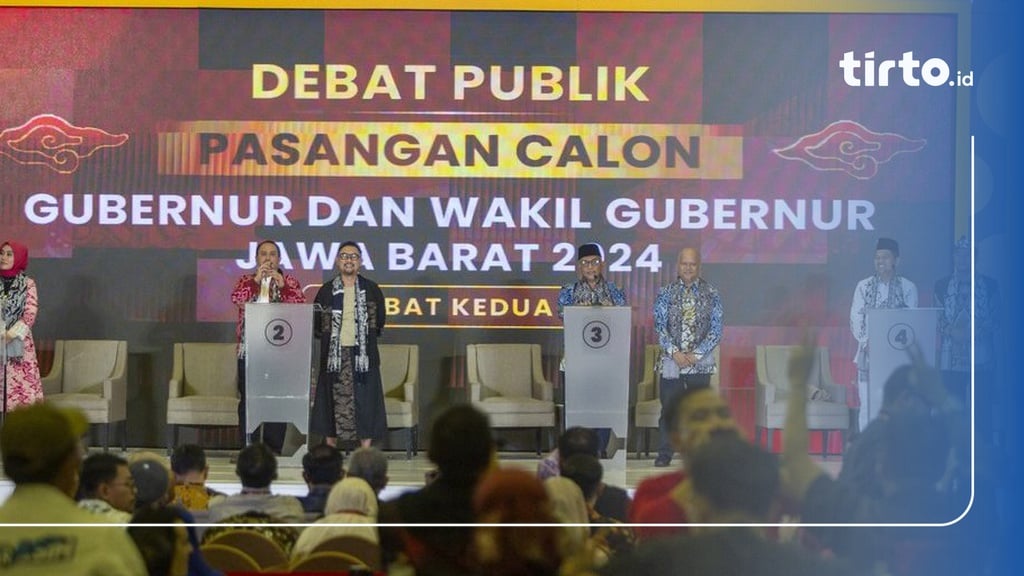tirto.id - Dalam benak Katsuhiro Otomo, Tokyo bakal jadi kota modern yang kacau balau pada 2019. Kekacauan tersebut utamanya berasal dari gerombolan pemuda yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sembari menyerang siapa pun yang ada di sekitar mereka tanpa pandang bulu.
Para berandalan ini benar-benar membuat pening para penegak hukum dan mereka tak henti-hentinya terlibat dalam aksi antipemerintah.
Tokyo yang dipikirkan Otomo pada awal 1980-an itu bukanlah Tokyo yang sesungguhnya, melainkan Neo-Tokyo, sebuah kota ultramodern yang dibangun dari puing-puing Tokyo tua yang hancur secara misterius.
Bak kota-kota cyberpunk lainnya, Neo-Tokyo memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia begitu modern dan menawan, tapi di sisi lain, kota tersebut menyimpan sejuta problematika sosial yang salah satunya terejawantahkan melalui aktivitas meresahkan geng motor.
Kurang lebih, begitulah latar cerita komik dan anime legendaris Akira, sebuah karya yang menahbiskan Otomo menjadi salah satu mangaka terhebat dalam sejarah Jepang. Tentunya, apa yang dibayangkan Otomo itu sangat jauh dari citra Jepang selama ini yang rapi, santun, dan taat aturan. Namun, ide sinting laki-laki 70 tahun itu tidaklah datang dari langit; Otomo menemukan ide tersebut di jalan-jalan Tokyo sendiri yang, ketika itu, memang kerap dijadikan arena berkendara ugal-ugalan anak muda.
Sepeda motor mereka dimodifikasi (Kaizōsha) dengan fairing yang besar dan mancung, setang yang ditarik sedikit ke belakang (shibori), sandaran jok yang tinggi, dan knalpot tinggi nan bising. Pengendaranya anak-anak muda berseragam tempur (tokkōfuku) menyerupai pilot era Perang Dunia II, lengkap dengan logo bendera matahari terbit dan atribut yang menjelaskan nama geng.
Tak lupa, senjata tajam dan tumpul mereka bawa di tangan untuk menyerang atau sekadar mengancam.
Yang disaksikan Otomo ketika itu adalah masa keemasan dari sebuah subkultur bernama bōsōzoku. Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih "geng ngebut ugal-ugalan".
Antara Kamikaze dan Kultur Greaser
Selepas Perang Dunia II, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat usai dibom atom dua kali oleh Amerika Serikat, muncullah sebuah generasi yang betul-betul kebingungan saat harus dihadapkan pada situasi "damai". Mereka umumnya anak-anak muda berusia 16-20 tahun yang sebelumnya direkrut untuk menjadi pilot kamikaze, tapi urung berangkat karena perang uasi lebih buag usai
Di usia semuda itu, mereka sudah dicuci otak dengan berbagai doktrin, salah satunya doktrin yang menyamakan para pilot kamikaze dengan samurai dari era feodal dulu. Di saat perang tiba-tiba usai, para pemuda yang sudah disiapkan untuk perang (dan mungkin mati dalam perang) itu pun kebingungan untuk menyesuaikan diri kembali ke masyarakat beradab.
Akhirnya, mereka pun mencari pelarian. Mayoritas penduduk Jepang ketika itu belum sanggup membeli mobil dan hanya memiliki sepeda motor, termasuk anak-anak muda tersebut. Mereka kemudian memodifikasi sepeda motor itu dan menggunakannya untuk adu cepat di jalanan. Tak lupa, mereka juga mulai melakukan hal-hal melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan akan pacuan adrenalin.
Pasca-Perang Dunia II, tentara Sekutu, khususnya Amerika Serikat, ikut menduduki Jepang dan dari sinilah sebuah transfer budaya terjadi. Para serdadu Amerika saat itu berdandan dengan gaya greaser ala James Dean dengan rambut jambul dan jaket kulit. Penampilan itu kemudian lantas diadopsi oleh anak-anak muda Jepang, khususnya yang terlibat dalam aktivitas balap liar di jalanan tadi.
Lambat laun, anak-anak muda Jepang itu juga menambahkan identitas mereka sendiri, yaitu dengan mengenakan seragam tempur ala pilot kamikaze, lengkap dengan bendera matahari terbit yang, entah dijadikan emblem dan ditempelkan ke seragam tadi atau dikibar-kibarkan saat mereka tengah berkendara. Seragam tempur tadi kerap juga digantikan dengan setelan overall ala pekerja pabrik dengan warna berbeda-beda di setiap gengnya.
Dari Bōsōzoku ke Yakuza
Kendati sudah eksis sejak dekade 1950-an, subkultur bōsōzoku ini baru mengalami ledakan popularitas pada dasawarsa 1970-an. Di era ini pulalah, istilah bōsōzoku pertama kali digunakan. Istilah ini sendiri tidak berasal dari para anggota geng motor, melainkan dari orang lain, khususnya yang merasa terganggu akan kehadiran mereka.
Namun, oleh para anggota geng motor, istilah bōsōzoku kemudian justru diadopsi untuk menamai diri mereka sendiri.
Sebelum muncul istilah bōsōzoku, yang lebih dahulu lahir adalah kaminarizoku alias "geng halilintar". Peralihan dari kaminarizoku menjadi bōsōzoku inilah yang terjadi pada dekade 1970-an. Jika sebelumnya anak-anak geng motor itu hanya doyan kebut-kebutan, setelah itu mereka jadi semakin beringas dan tak jarang terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Tak heran apabila sebutan untuk mereka pun menjadi denotatif.
Memasuki era ledakan ekonomi Jepang pada dekade 1980-an, subkultur bōsōzoku pun mencapai puncaknya. Anggota geng bōsōzoku di seluruh Jepang ketika itu mencapai lebih dari 45.000 orang.
Ini cukup bisa dimengerti karena, meski berawal dari anak muda yang tak punya apa-apa, hobi modifikasi motor bukanlah hobi yang murah. Ini belum termasuk dengan atribut-atribut lain yang juga cukup mahal.
Di tengah ledakan ekonomi itu, bōsōzoku menjadi gerakan kontrakultural tersendiri. Mereka yang terlibat di sana merasa bahwa masyarakat di sekitar mereka sudah semakin modern dan mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional Jepang. Dalam benak mereka, menurut fotografer Yoshinaga Masayuki, para anggota geng motor bōsōzoku melihat diri mereka sebagai samurai yang mewakili daimyō-nya masing-masing.
Sebelum disatukan Tokugawa Ieyashu, pada dasarnya Jepang diperintah oleh raja-raja kecil (daimyō) yang hobi berperang satu sama lain. Para serdadu yang berperang mewakili daimyō inilah yang disebut sebagai samurai. Sebelumnya sudah disebutkan bagaimana rezim fasis Jepang mendoktrin para pilot kamikaze bahwa mereka adalah samurai dan, mengingat muasal dari subkultur bōsōzoku ini sendiri, menjadi masuk akal apabila para anggota geng motor merasa dirinya sebagai samurai.
Pada era keemasan bōsōzoku itu pula banyak dari anggota geng yang sudah dewasa kemudian bergabung dengan Yakuza. Kepercayaan bahwa mereka adalah samurai ini, sedikit banyak, juga berpengaruh pada trajektori hidup para gangster tersebut. Ada kemiripan antara Yakuza dengan sistem pemerintahan feodal Jepang, di mana terdapat klan-klan yang saling berseteru memperebutkan wilayah, pengaruh, serta (tentu saja) mata pencaharian.
Kecenderungan para anggota bōsōzoku untuk bergabung dengan Yakuza ini pulalah yang membuat aparat kepolisian semakin tegas dalam menindak para gangster muda tersebut. Sampai akhirnya, kini sudah nyaris tidak ada lagi anak muda yang "melestarikan" subkultur tersebut.
Selain karena kerasnya respons dari aparat, satu penyebab meredupnya subkultur bōsōzoku ini adalah krisis ekonomi. Perlambatan ekonomi yang dialami oleh Jepang membuat banyak anak muda tak lagi memiliki sumber daya untuk membeli serta memodifikasi sepeda motor.
Jika dahulu bōsōzoku bisa memiliki puluhan ribu anggota, kini yang tersisa tinggal puluhan.
Yang Patut Dilestarikan dari Bōsōzoku
Sudah jelas bahwa bōsōzoku bukanlah subkultur yang nilai-nilainya patut untuk dilestarikan. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada sisi positif dari apa yang selama ini mereka lakukan. Ekspresi seni yang mereka tuangkan lewat sepeda motor serta seragam tentu layak mendapat apresiasi tersendiri.
Biasanya, sepeda motor yang digunakan anggota bōsōzoku adalah sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 s/d 400 cc. Honda CB 400 adalah salah satu sepeda motor yang paling kerap dimodifikasi dengan gaya Kaizōsha. Dalam proses modifikasi ini turut masuk pengaruh modifikasi dari Amerika Serikat dan Inggris.
Jika diperhatikan baik-baik, fairing besar yang digunakan anggota bōsōzoku itu mirip dengan fairing sepeda motor bergaya cafe racer yang berasal dari Inggris. Ini masuk akal karena motor-motor cafe racer awalnya dimodifikasi dengan tujuan utama mendapatkan kecepatan optimal. Sementara itu, bōsōzoku sendiri bermula dari hobi balapan di jalan raya.
Namun, para anggota bōsōzoku memang tidak mau meniru mentah-mentah apa yang dilakukan para anak muda di Inggris. Maka mereka pun memutuskan untuk meninggikan moncong sepeda motor sehingga, sepintas, tampak seperti pesawat yang hendak tinggal landas. Ini, lagi-lagi, bisa dilacak pada bagaimana subkultur ini diciptakan oleh para eks pilot kamikaze.
Sementara itu, pengaruh Amerika terlihat pada bentuk sandaran jok serta knalpot. Sandaran jok yang dibuat tinggi itu memang menyerupai motor-motor gaya chopper ala Amerika. Ini memang agak aneh karena sandaran jok tinggi di motor chopper biasanya difungsikan untuk bersandar karena posisi setang yang tinggi dan lebar. Namun, pada motor-motor Kaizōsha, setang justru ditarik sedikit ke belakang sehingga pengendaranya justru malah mesti duduk lebih tegak.
Adapun, untuk knalpot, sebenarnya tidak semua motor anggota bōsōzoku dibuat meninggi. Ada yang memilih untuk membiarkan knalpotnya berada di bawah layaknya motor-motor chopper. Namun, satu hal yang disepakati, peredam knalpot harus dicopot. Ini, utamanya, berfungsi untuk menggeber-geber motor untuk mengintimidasi pengguna jalan lainnya.
Selain dari sisi otomotif, sisi fesyen anggota bōsōzoku juga bisa dibilang unik. Sebagian besar dari mereka memilih seragam yang mirip seragam tempur atau seragam pekerja pabrik. Namun, ada pula geng yang memilih untuk tidak menggunakan seragam model seperti itu. Ada yang cukup menggunakan jaket bertuliskan kanji dengan tempelan berbagai emblem, termasuk bendera Jepang serta bendera matahari terbit.
Meski demikian, satu hal yang selalu terlihat dari seragam para anggota bōsōzoku itu adalah kemeriahan. Warnanya memang tidak selalu cerah, tetapi tulisan serta ornamen-ornamen yang terpampang di sana sangatlah khas dan sulit disamai subkultur mana pun.
tirto.id - Mild report
Reporter: Yoga Cholandha
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Fadrik Aziz Firdausi

 2 weeks ago
3
2 weeks ago
3