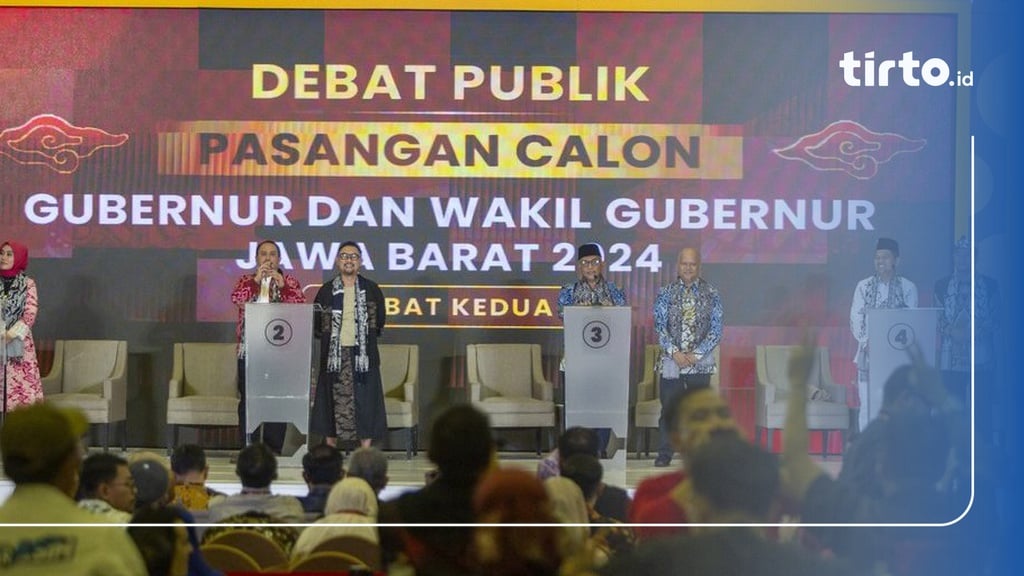tirto.id - Dari 30 April hingga 2 Mei 1926, Wage Rudolf Supratman hadir dalam Kongres Pemuda I di Gedung Vrijmetselaarsloge (kini gedung Kimia Farma) yang berlokasi di Weltevreden, Batavia.
Seturut Bambang Sularto dalam Wage Rudolf Supratman (2012), saat itu Supratman hadir sebagai wartawan Sin Po untuk meliput jalannya kongres. Selain mendengar secara langsung pidato-pidato kebangsaan dari para pemuda, di hari terakhir kongres ia menyaksikan perdebatan antara Ketua Kongres, Mohammad Tabrani, Mohammad Yamin, Djamaludin Adinegoro, dan Sanusi Pane.
Tabrani menentang poin terakhir dalam rumusan persatuan dari Yamin yang berbunyi, “bahasa persatuan, bahasa Melayu.” Ia mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Menanggapi itu, Yamin menyebut Tabrani sebagai “tukang ngelamun”. Sebab, saat itu bahasa Indonesia belum ada. Tak tinggal diam, Tabrani membalasnya dengan tegas, jika bahasa Indonesia belum ada, maka harus dilahirkan dalam kongres.
Di tengah perdebatan, Djamaluddin Adinegoro mendukung pendapat Yamin. Tak berselang lama, Sanusi Pane, yang datang terlambat ke kongres, segera masuk ke dalam perdebatan dan mendukung pendapat Tabrani.
“Ibaratkan pertandingan sepakbola sebelum turun minum 2-1 untuk kemenangan Yamin. Setelah Sanusi Pane muncul stand berobah menjadi 2-2. Sebab Sanusi Pane menyetujui saya,” tulis M. Tabrani dikutip dari Harimurti Kridalaksana dalam Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia (2018).
Mengutip kembali Bambang Sularto (2010), perdebatan itu tak kunjung menemui titik temu. Panitia kongres akhirnya mengambil jalan tengah dengan menangguhkan keputusan akhir kongres dan mengamanatkan untuk merembukkan kembali bahasa persatuan di Kongres Pemuda berikutnya.
Pada 27-28 Oktober 1928, para pemuda kembali berkumpul dalam gelaran Kongres Pemuda II. Hasilnya, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan.
Tak hanya mendukung Tabrani, Sanusi Pane juga menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini setidaknya tergambar dalam keikutsertaannya di Kongres Bahasa Indonesia di Gedung Habiprojo, Solo, yang berlangsung pada 25-28 Juni 1938.
Dalam acara tersebut, selain menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, ia mengusulkan pentingnya pembentukan institut bahasa untuk merawat dan mengembangkan bahasa Indonesia.
"Gagasan besar Sanusi Pane tentang institut bahasa Indonesia itu berkembang menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saat ini,” ujar Ketua Balai Bahasa Sumatra Utara, Maryanto, kepada Moyang Kasih Dewi Merdeka dalam Sanusi Pane: Pujangga Pencetus Badan Bahasa (2022).
Sastra dan Sejarah
Sanusi Pane lahir pada 14 November 1905 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Ia kakak kandung dari Armijn Pane dan Lafran Pane. Ketiganya adalah putra dari Sutan Pangurabaan Pane, penulis cerita daerah Tolbok Haleon.
HB Jassin dalam Pujangga Baru (2013), menempatkan Sanusi Pane sebagai sastrawan angkatan Pujangga Baru. Alasannya, selain terlibat dalam penerbitan majalah Pujangga Baru, karya-karya Sanusi dinilainya mengandung unsur semangat kebangsaan dan romatik.
Sedangkan Ajip Rosidi dalam Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia (1976) menempatkannya sebagai sastrawan sebelum masa Pujangga Baru. Hal ini dilihat dari sajak-sajaknya yang masih berbentuk soneta, khususnya dalam kedua kumpulan sajaknya Pancaran Cinta dan Puspa Mega. Masing-masing terbit pada tahun 1926 dan 1927.
Pada tahun 1931, terbit kumpulan sajak berjudul Madah Kelana. Meski masih terdapat bentuk soneta, karya ini menggambarkan pengalaman Sanusi dalam mencari kebahagian dan ketenangan di negeri India.
“Sanusi Pane menganggap dirinya sebagai seorang kelana yang berjalan ke mana-mana mencari kebahagiaan dan kemudian sadar bahwa kebahagiaan itu didapatinya dalam hatinya sendiri,” tulis Ajip Rosidi (1976).
J.U Nasution dalam Pudjangga Sanusi Pane (1963), menyebut Madah Kelana lekat dengan unsur filsafat India. Sanusi mengakui bahwa dirinya banyak terpengaruh pikiran Rabindranath Tagore.
Ia juga menciptakan empat karya drama dengan unsur romantik, khususnya sejarah Jawa. Airlangga dan Eenzame Garoedavlucht, masing-masing terbit pada tahun 1928 dan 1929 dalam bahasa Belanda. Sedangkan Kertajaya dan Sandhyakala ning Majapahit yang terbit pada tahun 1932 dan 1933 ditulisnya dalam bahasa Indonesia.
“Pada masa itu melukiskan sejarah mungkin disebabkan oleh karena kerinduan akan kebesaran diri sendiri. Jadi semacam usaha untuk mengembalikan kepercayaan diri sendiri yang sedang berada di bawah telapak kaki penjajah,” terang Ajip Rosidi (1976).
Warsa 1940, terbit drama lainnya yang berjudul Manusia Baru. Berbeda dengan drama-drama sebelumnya, drama ini mengangkat tema emansipasi wanita dan kebudayaan baru hasil sintesa budaya Barat dan Timur.
Mengutip Harry Poeze dan Henk Schulte Nordholt dalam Merdeka: Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti (1945-1950) (2023), pada 1943 Sanusi Pane menulis buku Sejarah Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang.
Materi dalam buku sejarah tersebut diawali dengan kejayaan dari kerajaan-kerajaan kuno, penindasan kolonial selama tiga setengah abad, pemberontakan, nasionalisme, dan pembebasan Jepang yang mengakhiri rezim kolonial.
Mengutip kembali Ajip Rosidi (1976), satu tahun setelah kemerdekaan, Sanusi Pane menyusun Bunga Rampai Hikayat Lama. Warsa 1948, ia menerjemahkan Kakawin Arjuna Wiwaha dari bahasa Kawi ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, ia menulis kembali buku sejarah yang berjudul Indonesia Sepanjang Masa pada tahun 1952.
Selain bekerja menciptakan karya sastra, ia memimpin penerbitan majalah Timboel edisi bahasa Indonesia dari tahun 1931-1933, dan surat kabar Kebangoenan pada 1936. Selanjutnya, di penghujung masa kolonial Belanda, bekerja sebagai redaktur di Balai Pustaka.
Mengutip laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atas jasa-jasanya di bidang sastra, Presiden Sukarno hendak memberi penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Namun, ia menolaknya.
"Indonesia telah memberikan segala-galanya bagiku. Akan tetapi, aku merasa belum pernah menyumbangkan sesuatu yang berharga baginya. Aku tidak berhak menerima tanda jasa apa pun untuk apa-apa yang sudah kukerjakan. Karena itu, adalah semata-mata kewajibanku sebagai putera bangsa,” ucap Sanusi.
Pada pada tahun 1969, setahun setelah Sanusi Pane meninggal, pemerintah memberi hadiah sastra sebagai penghormatan atas jasa-jasanya di bidang sastra.
Guru dan Organisasi
Sanusi juga dikenal sebagai seorang guru. Pekerjaan ini diawalinya di Kweekschool Gunung Sari pada tahun 1925, yang kemudian pindah ke Lembang dan berganti nama menjadi HIK (Holland Inlandsche Kweekschool).
Bersamaan dengan itu, ia mengikuti kuliah etnologi di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Kehakiman). Namun, pada “tahun 1934 dipecat sebagai guru karena keanggotaanya dalam PNI,” tulis Jassin (2013).
Setelah itu, ia memimpin sekolah dasar Perguruan Rakyat di Bandung dan mengajar di sekolah menengah Perguruan Rakyat di Jakarta. Menurut Soebagijo I.N dalam S.K. Trimurti: Wanita Pengabdi Bangsa (1982), sekolah dasar tersebut didirikan oleh Partindo.
Selanjutnya, Ia turut berkiprah dalam organisasi pergerakan. Mula-mula, bergabung dalam Jong Sumatranen Bond. Setelah itu, mengutip De Indische Courant edisi 12 Desember 1925, ia tercacat hadir dalam pertemuan pelajar Batak di Hotel Lux Orientalis, Weltevreden, Batavia.
Dalam pertemuan itu, disepakati pembentukan Jong Batak Bond dan akan memulai aktivitasnya pada 1 Januari 1926. Sanusi bersama dua pelajar Batak lainnya terpilih sebagai pembantu ketua organisasi, V.L. Tobing.
Dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), Benny G. Setiono mencatat, pada 1937, Sanusi Pane bersama Mr. Sartono, Amir Sjarifuddin, Muhammad Yamin, Dr. A.K. Gani, dan Wikana, turut mendirikan organisasi Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).
Pada masa pendudukan Jepang, Sanusi Pane memimpin pusat kebudayaan bernama Keimin Bunka Shidoso yang didirikan pada 1 April 1943 untuk kepentingan propaganda Jepang.
“Pusat kebudayaan itu mempunyai beberapa bagian yaitu kesusasteraan, pelukis, musik, film, sandiwara, dan tari-menari,” tulis S. Sumardi dalam Sarijah Bintang Sudibyo (Ibu Sud): Karya dan Pengabdiannya (1995).
Menurut M.C. Ricklef dalam Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008 (2010), upaya propaganda kerap mengalami kegagalan. Sebab, dihadapkan dengan kenyataan hidup yang sulit di masa pendudukan Jepang.
Dalam Polemik
HB Jassin (2013) menyebut Sanusi Pane sebagai antipoda Sutan Takdir Alisjahbana. Sebab, keduanya saling bertentangan dalam memandang sejarah dan arah kemajuan untuk kebudayaan Indonesia.
Merujuk buku Polemik Kebudayaan yang disusun Achdiat K. Mihardja (1952), dalam esainya yang berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru, Indonesia – Prae-Indonesia”, Takdir menjelaskan bahwa Indonesia yang tumbuh di abad ke-20, bukan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Teuku Umar.
“Sesungguhnya menyambung masa yang sudah lampau berarti membangkitkan perselisihan, sebab dalam zaman prae-Indonesia bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara ini tiada pernah mempunyai kemauan, tjita dan pikiran bersatu dan berhubungan dengan itu tiada pernah melahirkan Kebudajaan bersemangat demikian,” tulis Takdir.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan Indonesia harus berjalan dengan semangat baru dengan nilai-nilai dan modernitas Barat, guna menciptakan kehidupan yang dinamis. Bahkan, jika menilik kembali kemunculan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo hingga kata “Indonesia” itu sendiri, tidak terlepas dari pengaruh Barat.
Sanusi Pane menanggapi pandangan Takdir melalui esainya “Persatuan Indonesia” yang dimuat dalam surat kabar Suara Umum. Menurutnya, Indonesia yang lahir pada abad ke-20 merupakan sambungan dari masa silam.
“Tuan S.T.A rupanya tidak cukup mewujudkan dalam pandangan hidupnya akan kenyataan, bahwa sejarah itu ialah rantai. [...] Zaman sekarang adalah terusan jaman jang terdahulu. Manusia tidak sanggup mengadakan dewasa yang baru sama sekali. Hal yang demikian itu sekiranya sama dengan mengadakan barang dari yang tidak ada,” tulisnya.
Lebih lanjut, kata dia, ke-Indonesiaan sudah ada sejak masa Majapahit, Diponegoro, dan Teuku Umar, dalam bentuk adat dan seni. Hanya Indonesia sebagai nation yang belum timbul di masa itu. Sebab, saat itu orang Indonesia belum sadar bahwa mereka sebangsa.
 Infografik mozaik Sanusi Pane. tirto.id/Parkodi
Infografik mozaik Sanusi Pane. tirto.id/Parkodi
Selain itu, tambahnya, kebudayaan Barat berkembang atas dasar materialisme, intelektualisme, dan individualisme. Mereka lebih mengutamakan jasmani dan lupa akan jiwanya. Akalnya dipakai untuk menaklukan alam, seperti tokoh Faust dalam karya Goethe, yang rela mengorbankan jiwanya demi menguasai jasmani.
Hal tersebut, kata Sanusi Pane, bertentangan dengan kebudayaan Timur yang berdiri atas nilai spiritualisme, perasaan, dan kolektivisme. Mereka lebih mementingkan rohani, sehingga lupa akan jasmani. Sedangkan akalnya digunakan untuk menyesuaikan dirinya dengan alam, seperti Arjuna yang bertapa di Indrakala.
“Haluan jang sempurna ialah menjatuhkan Faust dengan Ardjuna memesrakan materialisme, intelektualisme, dan individualisme dengan spiritualisme, perasaan, dan collectivisme,” tulis Sanusi.
Mengutip kembali Ajip Rosidi (1976), melalui roman Layar Terkembang yang terbit pada tahun 1936, secara tidak langsung, Takdir mengkritik drama Sandhyakala ning Majapahit yang ditulis Sanusi pada tahun 1933.
Menurutnya, unsur-unsur filsafat India yang terkandung dalam drama tersebut hanya akan membuat manusia merasa terasingkan dari dunia dan menanamkan kesangsian hidup bagi para pemuda.
Menyadari itu, Sanusi membalasnya dengan menyebut Layar Terkembang sebagai roman bertendensi yang berisi propaganda dan tidak menunjukkan sebuah bentuk kesusastraan yang sejati.
alam perkembangan selanjutnya, keduanya saling berbalik arah dari pendiriannya masing-masing. Takdir dalam tulisannya “Menumbuhkan Pribadi Sendiri”, menyatakan jika secara mutlak berpedoman kepada Eropa dan Amerika dalam mengejar kemajuan modern, maka, bukan tidak mungkin kehidupan kita akan lenyap.
Sedangkan Sanusi melalui Manusia Baru, berupaya menciptakan kebudayaan baru, kombinasi dari Faust (Barat) dan Arjuna (Timur). Namun, J.U Nasution (1963) menyebut upaya tersebut gagal.
Hal ini terlihat dalam satu adegan, saat tokoh Saraswati, seorang gadis yang terikat pertunangan sejak kecil berdasarkan adat lama, pergi dari rumah kedua orang tuanya untuk hidup bersama Surendranath Das, seorang penganjur kaum buruh yang memiliki keinginan untuk mengubah masyarakat dan peradaban.
Adegan itu menggambarkan manusia yang memilih untuk meninggalkan kebudayaan lama menuju kebudayaan baru. Sehingga, tidak sepenuhnya tercapai sintesa dari Faust (Barat) dan Arjuna (Timur).
“Sekaligus pula drama Manusia Baru disadari atau tidak oleh pengarang, menentang pendiriannya sendiri yang menolak sastra bertendensi, karena drama itu berbau propaganda,” pungkas J.U. Nasution (1963).
tirto.id - Humaniora
Kontributor: Andika Yudhistira Pratama
Penulis: Andika Yudhistira Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi

 2 weeks ago
3
2 weeks ago
3