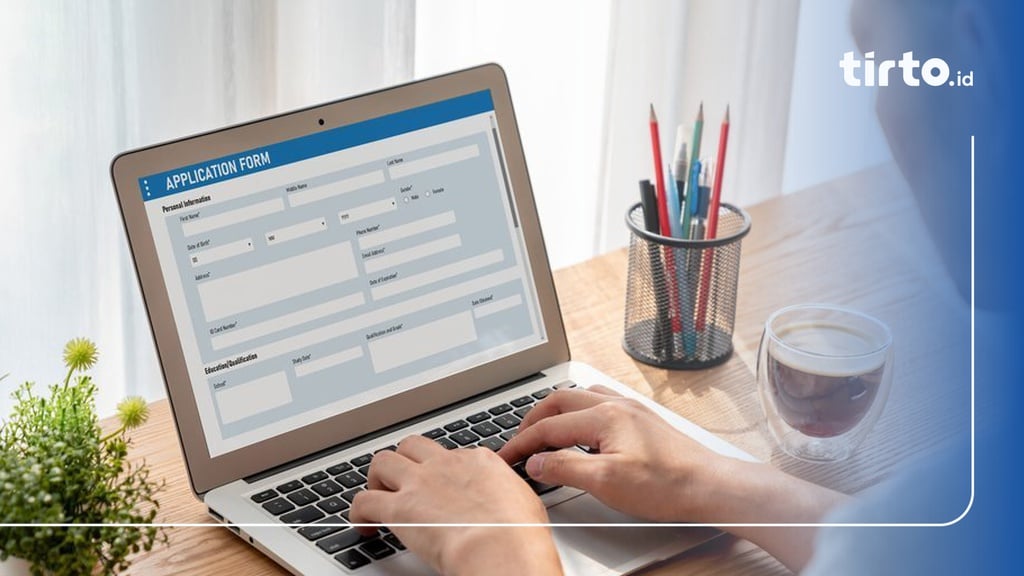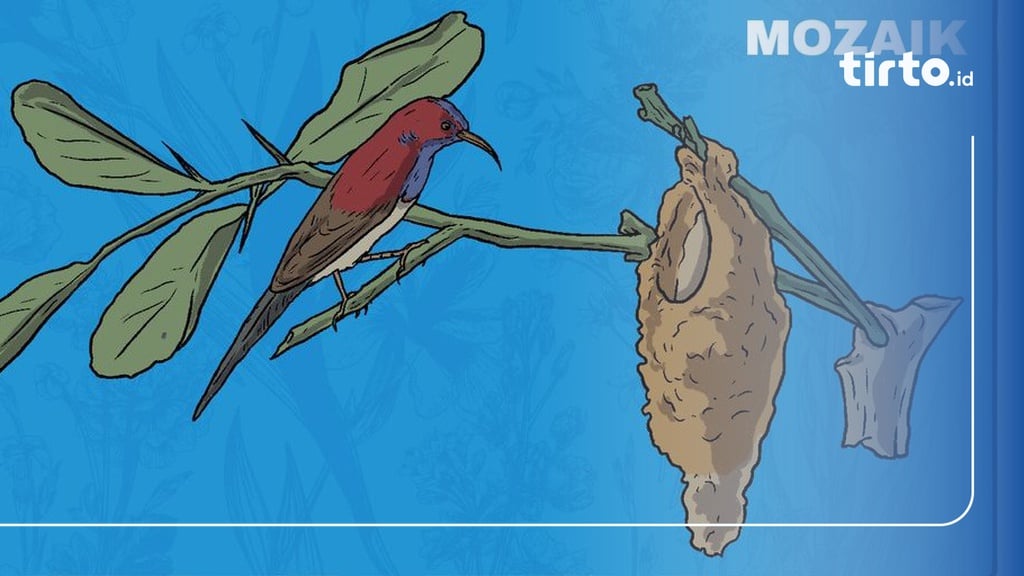tirto.id - Ketika Kompeni atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) bercokol di Nusantara, Madura tak luput dari perhatiannya, lebih-lebih setelah kongsi dagang Belanda itu mengambil alih bagian timur pulau tersebut dari Pangeran Puger atau Pakubuwono I sebagai kompensasi dari penghapusan akumulasi utang Kesultanan Mataram.
Seturut Imam Syafi’i dalam "Persaingan Pengangkutan Garam di Selat Madura Tahun 1924-1957" (2013:86), sebelum Belanda berkuasa produksi garam di Madura dijalankan oleh masyarakat Tionghoa. Karena dianggap kurang menguntungkan, banyak ladang garam dialihfungsikan untuk keperluan lain.
Situasi berubah pada 1861 setelah produksi garam diambil alih pemerintah kolonial dan harganya dinaikkan. Lima tahun berselang, luas ladang garam bertambah. Selain banyak masyarakat yang menggunakan tanahnya untuk membuat garam, juga karena maraknya reklamasi pantai dan konversi kolam ikan menjadi ladang garam. Sejak itu, Madura menjadi pemasok utama garam di Hindia Belanda dan dikenal sebagai Pulau Garam.
Pada abad ke-20, produksi garam di Madura ibarat mesin uang yang memberikan untung berlipat bagi pemerintah kolonial. Selain jumlah garam yang dihasilkan melimpah, kualitasnya juga sangat bagus. Sejak 1916 hingga 1920, laba bersih komoditas tersebut lebih dari 9 juta gulden per tahun, melampaui keuntungan bisnis opium.
Pada 1915, desa-desa di pesisir selatan Sampang, Pamekasan, dan Sumenep menjadi pusat penghasil garam (zoutlanden). Masing-masing memiliki jumlah ladang garam yang bervariasi. Sampang memiliki 1.377 ladang, Pamekasan 1.547 ladang, dan Sumenep 1.648 ladang.
Di Sampang, ladang garam banyak ditemukan di Desa Ragung, Dangpadang, dan Pangarengan. Di Pamekasan terdapat di Desa Mangunan dan Capak. Sedangkan di Sumenep berada di Desa Marengan, Kertosodo, Palabuhan, Mundung-mundung, Pinggirpapas, Nambakor, dan Sarokka.
Dalam laporan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1928, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dianggap sebagai kawasan ideal pembuatan garam karena bertanah kapur dan memiliki musim kemarau yang panjang. Dalam empat bulan, tiga kota itu bisa tidak turun hujan sama sekali. Saat pergantian musim pun kota-kota tersebut kadang masih kering.
Garam Briket Madura
Sejak masa kekuasaan bupati hingga Pemerintah Kolonial Belanda, ladang garam berada dalam kepemilikan penguasa. Itu sebabnya, produksi garam di Madura dilakukan dengan sistem sewa pada pemerintah, dan sebagaimana lazimnya sistem pertanian saat itu, para petani garam hanya memiliki hak untuk memungut hasilnya.
Produksi garam di Hindia Belanda diurusi oleh Departemen Pendidikan, Urusan Agama, dan Industri Kerajinan (Departement van Onderwijs, Eeredients en Nijverheid). Sementara pengawasannya di lapangan dilakukan oleh Dinas Garam atau Zoutregie.
Seturut Wisnu dkk dalam "Salt Briquette: the Form of Salt Monopoly in Madura, 1883 – 1911" (2017:4), salah satu jenis garam yang diproduksi pabrik-pabrik yang didirikan pemerintah kolonial adalah garam briket, yaitu garam yang dicetak dalam bentuk kubus dengan berat yang bervariasi, mulai 1kg, 10kg, 15kg, hingga 25kg.
Garam briket dibuat dengan garam pasir yang bersih dari kotoran dan benar-benar kering. Garam pasir yang masih mengandung air akan membuat garam briket mudah hancur. Untuk memastikannya, garam yang diterima dari produsen disimpan terlebih dulu di gudang-gudang garam selama satu tahun.
Pabrik garam briket yang pertama didirikan oleh pemerintah kolonial berada di Kalianget (Sumenep). Pada masanya, pabrik yang dibangun pada 1889 itu mengoperasikan mesin-mesin dengan teknologi mutakhir. Setelah Kalianget, pemerintah kolonial juga membangun pabrik yang sama di Mangunan (Pamekasan) dan Krampon (Sampang).
Untuk mendukung operasional pabrik, pemerintah mendirikan gudang-gudang garam. Di seluruh Madura sedikitnya terdapat 167 gudang garam. Di Sumenep, yang produk garamnya dinilai lebih baik dibandingkan Sampang dan Pamekasan, ada kurang lebih 85 gudang garam. Lain itu, kantor dan rumah-rumah pegawai juga dibangun di dekat pabrik-pabrik tersebut.
Untuk memudahkan distribusi garam ke luar Pulau Madura, pabrik-pabrik garam mengoperasikan armada laut yang bernama OJZ (Oost-Java Zeetransport). Selain angkutan resmi, ada juga pihak swasta yang menyediakan jasa yang sama, yaitu KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) dan MSM (Madoera-Stoomtram Maatschappij).
Pada 1901, MSM merevolusi pengangkutan garam di Madura dengan mengoperasikan kereta api. Untuk membantu pabrik-pabrik mendistribusikan garam ke luar pulau, pada 1912 perusahaan tersebut mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuka firma pelayaran.
Perlawanan Sarekat Islam Madura
Setahun setelah mengganti nama dari Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI), organisasi yang semula bergerak di bidang perniagaan itu merambah Madura. Pada April 1913, Haji Syadzali mendirikan Sarekat Islam Sampang. Sebulan kemudian, Sarekat Islam juga membuka cabang di Pulau Sapudi yang berlokasi di timur Pulau Madura.
Pada Desember 1913, Sarekat Islam Sumenep resmi berdiri, disusul Sarekat Islam Pamekasan (Februari 1914), dan Sarekat Islam Bangkalan (April 1914). Semua cabang Sarekat Islam di Pulau Madura mendapatkan status hukum dari pemerintah kolonial pada 3 April 1915.
Seturut Iswahyudi dalam "Sarekat Islam Madura: Between Social Religious and Political Movements, 1913 – 1920" (2022:53), keuntungan besar dari bisnis garam membuat pemerintah kolonial memonopolinya. Caranya dengan mewajibkan masyarakat membuat garam, mengawasi proses produksinya, tapi melarang keras penjualannya selain pada mereka.
Karena minimnya lapangan pekerjaan, para petani garam tidak memiliki daya tawar terhadap peraturan itu. Celakanya, jika terjadi gagal panen mereka terpaksa berutang pada rentenir dengan bunga yang mencekik. Pada 1915, petani yang meminjam uang 10 gulden, 17 gulden, atau 60 gulden harus mengembalikannya sebesar 14 gulden, 34 gulden, dan 100 gulden.
Situasi tersebut mendorong Sarekat Islam Madura mengajukan tuntutan agar pemerintah menaikkan harga jual garam. Tuntutan untuk menaikkan harga dinilai masuk akal sebab pemerintah memberlakukan peraturan ketat untuk menjaga kualitasnya, seperti kewajiban memperbaiki tambak dan membersihkan limbahnya.
 Infografik Mozaik Garam Madura. tirto.id/Parkodi
Infografik Mozaik Garam Madura. tirto.id/Parkodi
Namun, tuntutan kenaikan harga ini memicu konflik di tubuh Sarekat Islam Madura. Menurut Haji Syadzali yang ditugaskan pemerintah untuk meneliti produksi garam di Madura, kenaikan harga beli garam yang semula 10 gulden per koyang menjadi 20 gulden per koyang pada produsen laik disetujui dalam sidang Volskraad pada akhir 1918.
Salah satu anggota Sarekat Islam Madura yang bernama R. Sosrodanukusumo menolak keras harga tersebut. Sikap kritisnya berbuah pemecatan dan berbuntut panjang. Putra R. Sosrodanukusumo yakni Kaharkusuman kemudian menginisiasi mogok massal para pekerja garam di desa Krampon, Sampang, pada akhir 1920.
Tak hanya ditolak sesama anggota Sarekat Islam Madura, rekomendasi Haji Syadzali belakangan juga tidak dipercaya oleh pemerintah. Pemerintah bahkan menudingnya hanya mewakili kepentingan pemilik ladang garam tapi melupakan kepentingan para buruh penggarap yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin.
Dalam sidang Volksraad, tuntutan kenaikan harga itu memang disetujui, tapi jumlahnya diperdebatkan di antara dua kubu. Kubu Van Hinloopen Laberton mengusulkan harga dinaikkan menjadi 15 gulden per koyang, sedang kubu Abdul Muis menuntut kenaikan harga hingga 25 gulden per koyang.
Merespons perdebatan di Volksraad, Sarekat Islam Madura mengadakan serangkaian pertemuan di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep pada 5, 6, dan 8 Desember 1918. Ratusan petani garam dari tiga kota tersebut hadir dalam pertemuan-pertemuan itu.
Hasil dari tiga pertemuan tersebut adalah antiklimaks: Sarekat Islam Madura tetap mengajukan tuntutan kenaikan harga, tapi nilainya disesuaikan dengan kesepakatan anggota Volksraad. Celakanya, hingga 1920 tuntutan kenaikan harga yang sudah dibahas di Volksraad tidak ada kelanjutan dan realisasinya.
tirto.id - Politik
Kontributor: Firdaus Agung
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Irfan Teguh Pribadi

 3 weeks ago
6
3 weeks ago
6