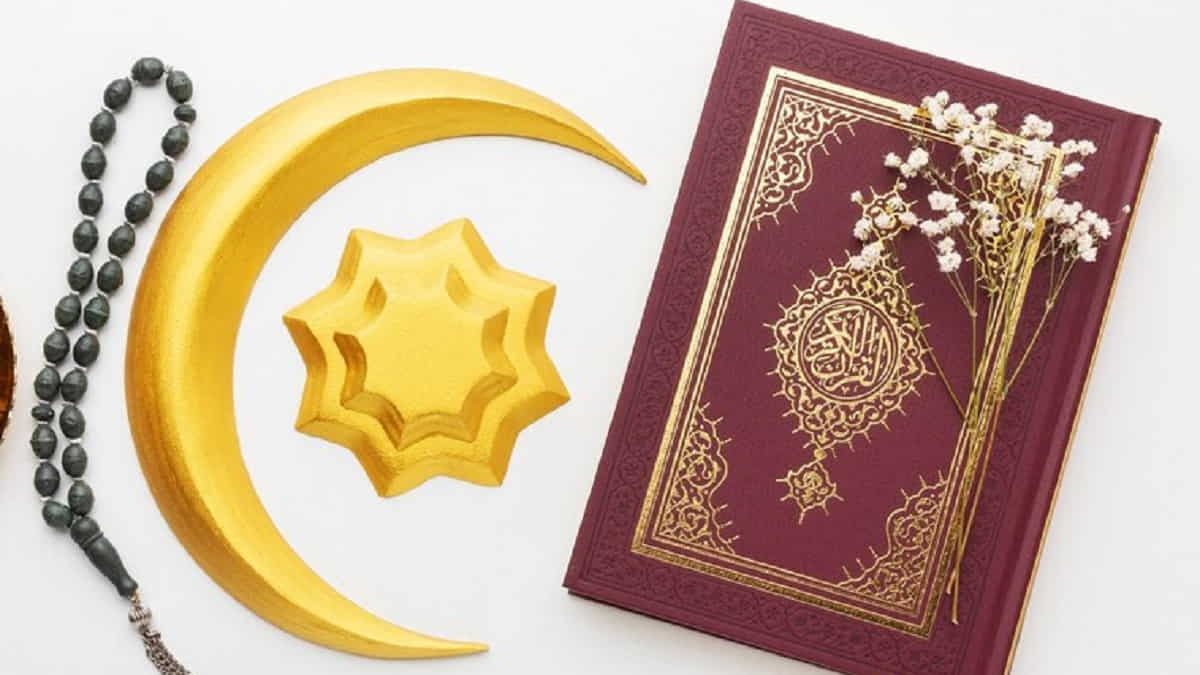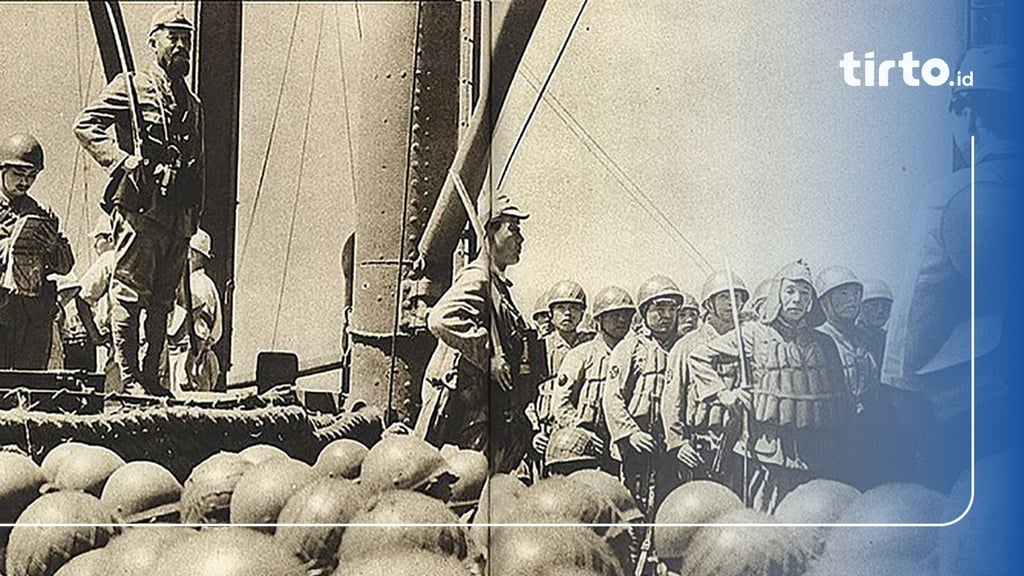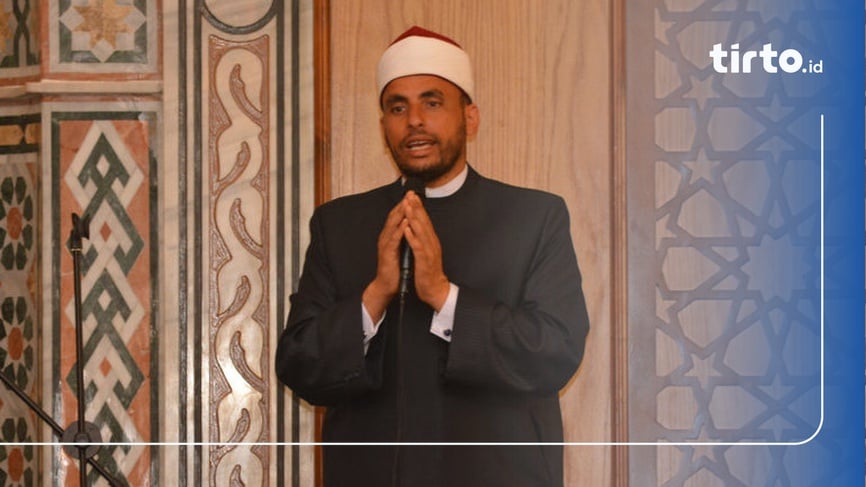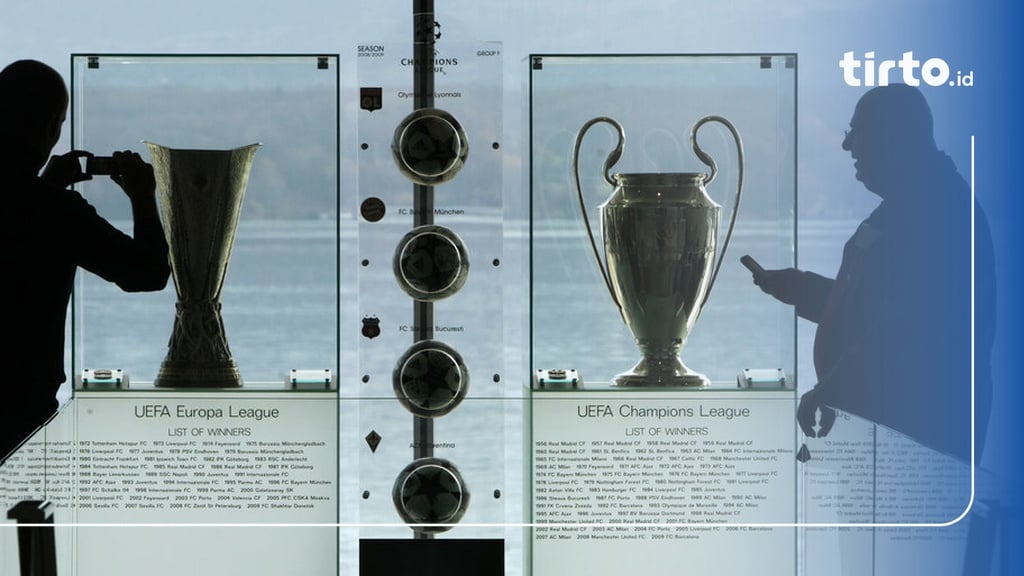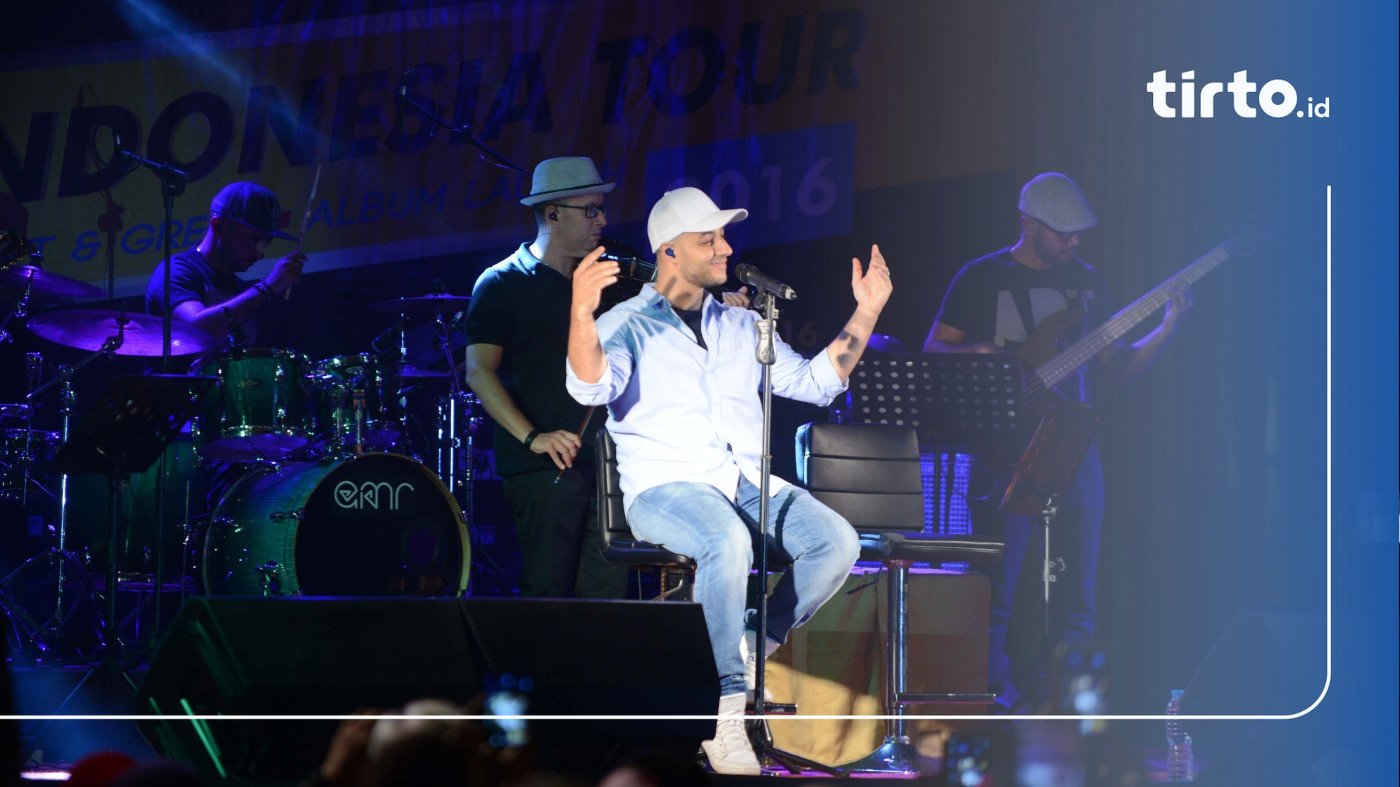Alat musik Tarawangsa merupakan kesenian tradisional khas Sumedang, Jawa Barat, yang memiliki kemiripan dengan kecapi. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek dan sangat populer di daerah Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Keberadaan Tarawangsa erat kaitannya dengan perayaan panen, menjadikannya bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat.
Tarawangsa berfungsi sebagai sarana ungkapan rasa syukur para petani atas hasil panen padi yang melimpah. Biasanya, masyarakat setempat memainkan alat musik ini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, dewi kesuburan dalam kepercayaan masyarakat Sunda.
Baca Juga: Mengulas Sejarah Alat Musik Karinding di Jawa Barat
Oleh karena itu, Tarawangsa tidak hanya sekadar alat musik saja. Akan tetapi juga simbol yang erat terkait dengan kehidupan pertanian dan tradisi agraris masyarakat Sumedang.
Sejarah Alat Musik Tarawangsa dan Maknanya
Kata Tarawangsa memiliki makna mendalam dan beragam interpretasi di kalangan masyarakat. Beberapa orang meyakini bahwa istilah ini merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu Ta, Ra, dan Wangsa.
Ta berarti meta atau pergerakan, Ra bermakna api agung atau matahari, dan Wangsa berarti bangsa. Jika digabungkan, Tarawangsa dapat kita maknai sebagai “kisah pergerakan bangsa matahari,” sebuah konsep yang erat kaitannya dengan dunia pertanian yang sangat bergantung pada sinar matahari untuk keberlangsungan hidup dan hasil panen.
Selain itu, interpretasi lain muncul seiring dengan masuknya pengaruh Islam ke dalam budaya Sunda. Setelah perpaduan antara budaya Sunda dan ajaran Islam, Tarawangsa juga dimaknai sebagai akronim dari Tatabeuhan Rakyat Wali Salapan, yang berarti tetabuhan rakyat sembilan wali.
Makna ini menegaskan bahwa Tarawangsa tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional saja. Akan tetapi juga menjadi simbol perpaduan budaya dan nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat Sunda.
Awal Bermulanya Budaya Sawah Tercipta
Alat musik Tarawangsa memiliki sejarah panjang yang bermula pada masa kejayaan Kerajaan Mataram ketika wilayah Sunda berada di bawah kekuasaannya. Pada masa itu, pejabat Sunda wajib mengunjungi Mataram setahun sekali.
Menariknya, pada periode tersebut, masyarakat Sunda belum mengenal konsep sawah, yakni metode bercocok tanam dengan petakan penuh air dan tanah berlumpur. Sebaliknya, padi yang terkenal di tanah Sunda adalah padi huma, yaitu menanam padi di ladang kering saat musim hujan tiba.
Budaya huma mencerminkan pola hidup berpindah-pindah. Di mana masyarakat Sunda menggunakan satu petak lahan untuk bercocok tanam dan berpindah ke lahan baru setelah tanah yang lama kehabisan unsur hara.
Meski demikian, budaya sawah yang menetap dan produktif rupanya menarik perhatian masyarakat Sunda. Hal ini mendorong beberapa orang Sunda untuk mencoba menyelundupkan benih padi sawah dari Mataram ke wilayah Sunda.
Percobaan pertama mereka lakukan dengan menyelundupkan benih padi di dalam kecapi, namun gagal. Setelah berbagai usaha, benih padi sawah akhirnya berhasil mereka selundupkan menggunakan alat musik Tarawangsa.
Keberhasilan ini menjadi titik penting, karena padi sawah tumbuh subur di tanah Sunda yang kaya akan mineral akibat keberadaan gunung api dan bekas danau purba. Hal ini memungkinkan padi sawah tumbuh lebat dan berisi, memperkaya budaya pertanian masyarakat Sunda serta mempererat hubungan mereka dengan alat musik yang hingga kini masih menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen melimpah.
Wujud Rasya Rasa Syukur Panen
Orang Sunda yang sudah mengenal budaya sawah tersebut kemudian bersyukur saat panen tiba. Wujud rasa syukur mereka adalah dengan membunyikan alat musik Tarawangsa, alasannya karena berhasil membawa padi ke Sunda. Syukur ini juga menjadi simbol penghormatan kepada Nyi Pohaci Dangdayang Sri atau Dewi Sri, selaku dewi kesuburan.
Baca Juga: Sejarah Alat Musik Calung, Warisan Budaya Sunda
Seiring dengan perkembangan zaman, Tarawangsa yang semula hanya nama alat musik sekarang menjadi nama kesenian bermusik. Seni Tarawangsa sangat erat kaitannya dengan ritual, sebab musik ini biasa bermain pada saat syukuran hasil bumi saja. Hingga kini, daerah yang masih melestarikan seni Tarawangsa adalah Desa Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat.
Cara Memainkan Alat Musik
Alat musik Tarawangsa dimainkan dengan cara digesek, mirip dengan cara memainkan rebab. Meskipun tampak serupa, Tarawangsa memiliki dua senar saja, yang membuatnya berbeda dari instrumen gesek lainnya.
Bentuk Tarawangsa terdiri dari sebuah bagian persegi panjang yang berfungsi seperti tabung resonansi. Terdapat sebuah gagang panjang yang memudahkan pemain untuk memegang dan menggesek senar.
Cara memainkan Tarawangsa adalah dengan meletakkannya dalam posisi berdiri, mirip dengan posisi yang kita gunakan saat memainkan selo. Pemain kemudian menggesek senar menggunakan busur untuk menghasilkan bunyi.
Keunikan dari Tarawangsa terletak pada kolaborasinya dengan alat musik lainnya, khususnya dengan paduan petikan kecapi yang bernama Jentreng. Kolaborasi ini menghasilkan harmonisasi yang indah.
Perbedaan dengan Alat Musik Cianjuran
Permainan kacapi dalam alat musik Tarawangsa memiliki keunikan tersendiri jika kita bandingkan dengan seni musik lainnya, seperti Cianjuran. Pada Tarawangsa, senar yang bergetar ketika dimainkan harus ditekan dengan cukup kuat, sehingga menghasilkan suara yang tidak mulus.
Suara ini memberikan kesan yang lebih kasar namun tetap memiliki keindahan tersendiri. Suara tersebut menjadi ciri khas dan memberikan warna tersendiri dalam alunan musik Tarawangsa.
Salah satu perbedaan yang mencolok antara Jentreng dan kecapi Cianjuran terletak pada jumlah senarnya. Kecapi Cianjuran memiliki 20 senar yang terbagi dalam tiga tingkatan nada, yakni “da-mi-na-ti-la”, sementara Jentreng dalam Tarawangsa hanya memiliki 7 senar.
Perbedaan jumlah senar ini memberikan perbedaan dalam teknik permainan serta kekayaan tonalitas yang tercipta dalam setiap alunan musiknya. Jentreng lebih sederhana dan langsung, sedangkan Cianjuran lebih kompleks dalam penataan dan harmonisasi nada.
Saat ini, alat musik tersebut masih berfungsi sebagai ritual dan juga hiburan dalam acara-acara tertentu. Salah satu contoh penggunaannya adalah dalam acara-acara resmi pemerintah di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga: Sejarah Alat Musik Tifa sebagai Melodi Warisan Budaya
Pada momen resmi ini, fungsi alat musik Tarawangsa adalah untuk menyambut pejabat dari pemerintah pusat ke wilayah tersebut. Keberadaan alat musik ini harus senantiasa lestari agar menambah kekayaan budaya di Indonesia. (R10/HR-Online)

 2 months ago
80
2 months ago
80