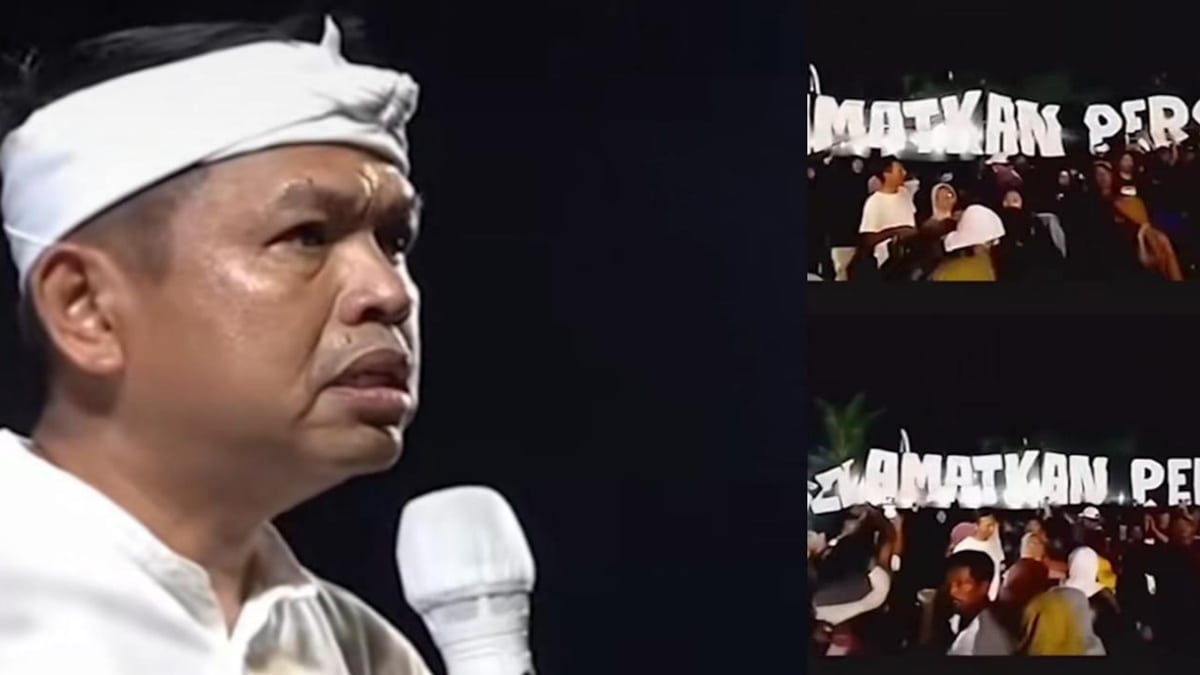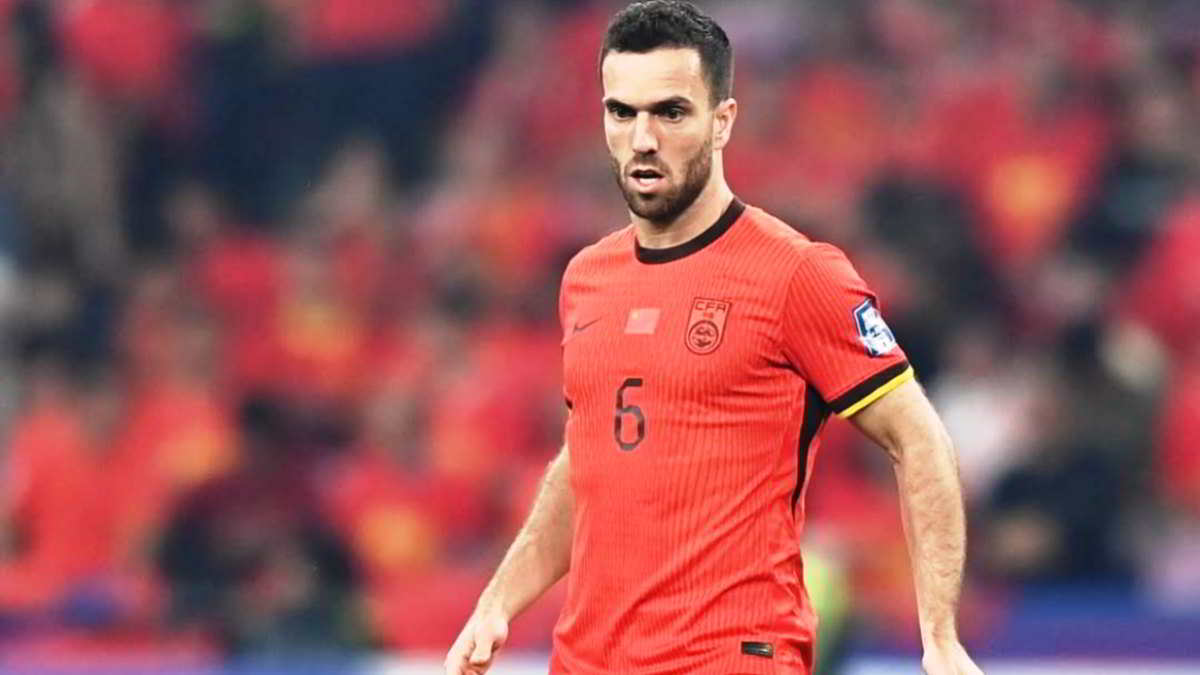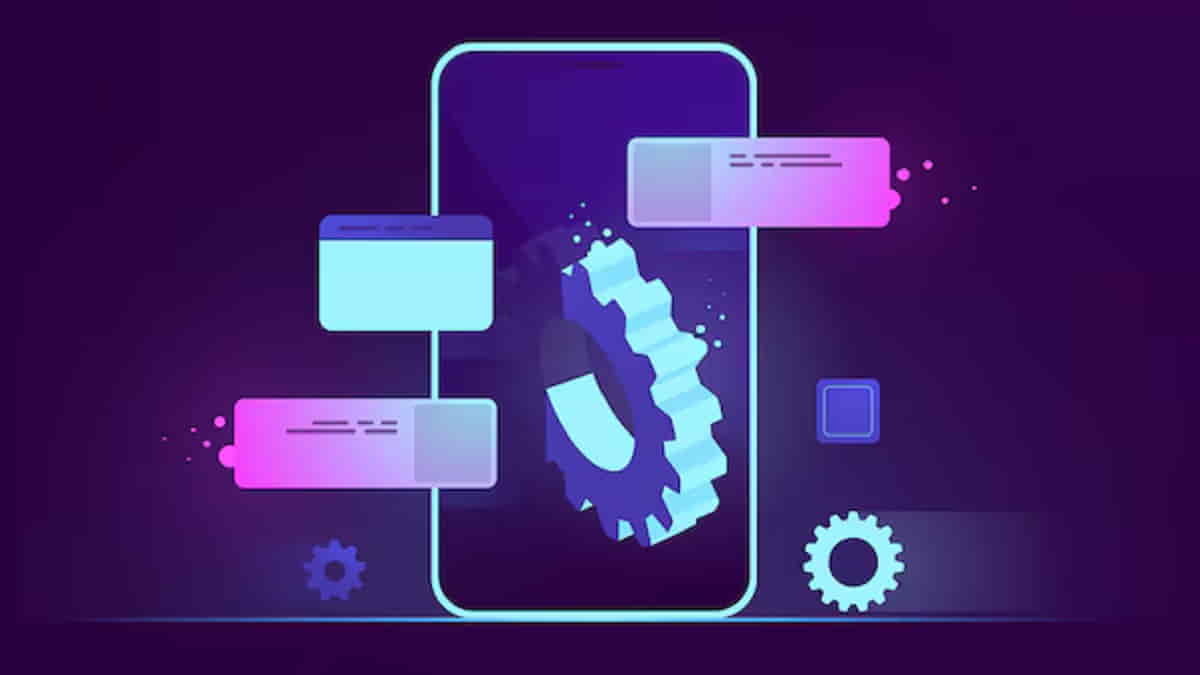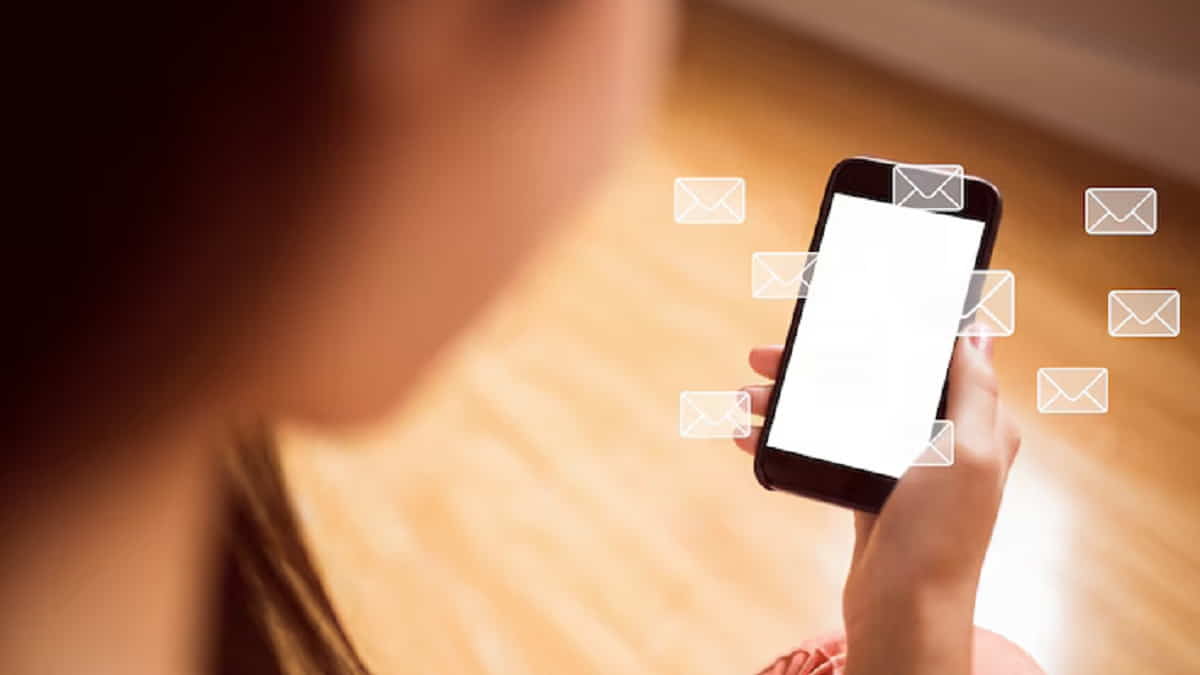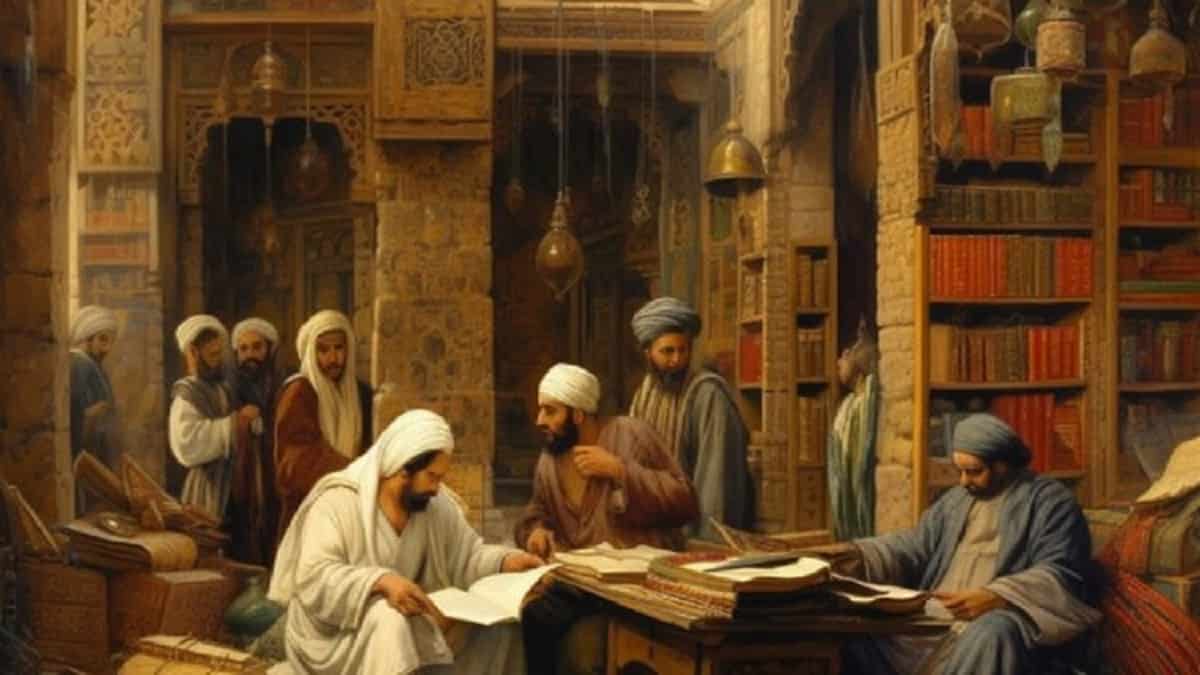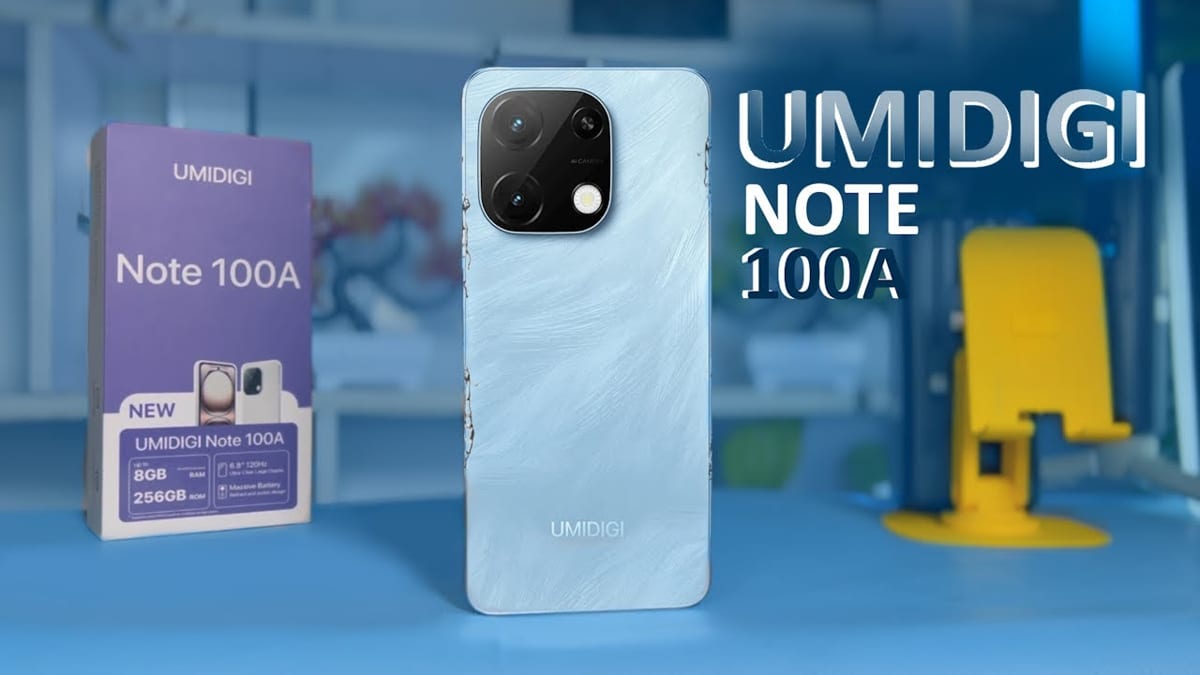Sejarah cultuurstelsel di Sukabumi menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan panjang kolonialisme di Indonesia. Sukabumi, wilayah subur di kaki Gunung Gede Pangrango, pernah menjadi saksi bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda mengubah kehidupan masyarakatnya.
Namun sebagaimana menilik dari catatan sejarah Indonesia, kebijakan ini bukan sekadar soal pertanian, melainkan tentang penderitaan, ketidakadilan, dan ketimpangan yang ditinggalkan untuk tanah Sunda. Setiap jengkal tanah yang dulu ditanami kopi dan teh menyimpan kisah pilu para petani yang terpaksa tunduk kekuasaan penjajah.
Baca Juga: Sejarah Cihapit Bandung, dari Kamp Tahanan hingga Pasar Tradisional Modern
Bayangkan suasana pagi di lereng pegunungan Sukabumi pada abad ke-19, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah dan ladang. Saat dinginnya udara, deretan petani berjalan tergesa membawa cangkul dan keranjang menuju perkebunan kopi milik kolonial. Tidak ada ruang untuk menolak atau bersuara. Rasa lelah dan lapar menjadi teman setia, sementara harapan tentang kehidupan lebih baik perlahan memudar di tengah kebijakan yang menindas.
Mengenal Sejarah Cultuurstelsel di Sukabumi
Cultuurstelsel yang berarti “sistem budaya” dalam bahasa Belanda, terkenal sebagai Sistem Tanam Paksa. Kebijakan ini mewajibkan petani pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula.
Hasil panen tersebut harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk diekspor ke Eropa. Sistem ini muncul pada tahun 1830 melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang memperkenalkannya. Katanya, sistem ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial dari Hindia Belanda.
Nah, sejarah cultuurstelsel Sukabumi juga bermula pada awal abad ke-19 tersebut. Sukabumi, sebagai bagian dari Residentie Preanger, menjadi salah satu wilayah untuk perkebunan kopi. Petani pribumi terpaksa menyerahkan sebagian lahannya untuk tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula. Hasil panen wajib setor kepada pemerintah kolonial tanpa memperhatikan hak dasar para petani.
Penerapan kebijakan ini yakni sistem kerja paksa dengan pengawasan ketat. Rakyat tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah, meskipun harus mengorbankan lahan pangan dan kebutuhan hidup keluarga. Bayangkan bagaimana keteguhan hati masyarakat waktu itu, bertahan dengan penindasan hanya demi bertahan hidup.
Perkembangan Perkebunan di Sukabumi
Sukabumi mengalami perubahan besar ketika pemerintah Belanda memfokuskan wilayah ini sebagai pusat perkebunan. Perkebunan kopi menjadi komoditas unggulan karena kualitasnya yang terkenal baik. Selain kopi, teh dan kina juga mulai ditanam di lereng-lereng pegunungan Sukabumi.
Pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, hingga rel kereta api untuk mempermudah pendistribusian hasil perkebunan ke pelabuhan. Meski secara ekonomi produksi kopi meningkat, situasi berbeda justru terjadi kalangan masyarakat lokal. Banyak petani yang kehilangan lahan pangan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk mengurus kebutuhan pribadi.
Dari gemerlapnya perdagangan kopi pasar Eropa, masyarakat Sukabumi kala itu hidup dalam tekanan. Rasa lelah, lapar, dan cemas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari sistem ini.
Dampak Sosial dan Ekonomi Cultuurstelsel
Sejarah cultuurstelsel di Sukabumi juga meninggalkan dampak sosial yang berat. Banyak keluarga petani jatuh miskin karena tidak lagi bisa menanam padi atau tanaman pangan lain di lahannya sendiri. Kelaparan pun kerap terjadi, terutama saat panen kopi atau teh tidak sesuai harapan.
Baca Juga: Regenschap Meester Cornelis, Jejak Administratif yang Menjadi Sejarah Jakarta Timur
Tidak sedikit pemberontakan lokal muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan tanam paksa ini. Meski seringkali terbungkam, semangat perlawanan tetap menyala dalam hati masyarakat. Derita panjang ini akhirnya mulai berakhir pada akhir abad ke-19 saat sistem tanam paksa terhapus menyusul desakan kritik dari berbagai pihak. Ini termasuk dari kaum intelektual Belanda sendiri.
Rasa perih masih tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat Sukabumi. Setiap kebun kopi peninggalan zaman itu seolah menyimpan cerita tentang darah dan keringat yang tercurah demi memenuhi ambisi penjajah.
Perubahan Status Sukabumi di Masa Kolonial
Selain sebagai pusat perkebunan, Sukabumi juga mengalami perkembangan administratif yang signifikan. Wilayah ini awalnya merupakan sebuah distrik kecil, kemudian naik status menjadi gemeente atau kota administratif pada 1921. Perubahan ini menunjukkan pentingnya peran Sukabumi dalam perekonomian Hindia Belanda kala itu.
Fasilitas publik, kantor pemerintahan, serta jalur transportasi terus berkembang demi mendukung aktivitas perkebunan dan pendistribusian hasil panen. Sukabumi pun perlahan berubah menjadi kota strategis untuk wilayah Priangan Barat, meskipun kesejahteraan masyarakatnya tetap terpinggirkan.
Baca Juga: Sejarah Cornelis Chastelein, Sosok di Balik Lahirnya Depok
Sejarah cultuurstelsel di Sukabumi menjadi pengingat betapa beratnya penderitaan masyarakat atas penjajahan Belanda. Sistem tanam paksa ini tidak hanya merampas hak atas tanah, tetapi juga menyisakan luka sosial yang sulit terhapus hingga kini. Dari keindahan alam Sukabumi yang sekarang terkenal sebagai destinasi wisata, tersimpan kisah getir tentang perjuangan petani lokal yang bertahan hidup karena tekanan kolonial. Warisan sejarah ini patut kita kenang, agar generasi mendatang tak pernah lupa bahwa tanah yang kini damai, pernah tercurah air mata dan keringat demi mempertahankan martabat. (R10/HR-Online)

 2 months ago
58
2 months ago
58