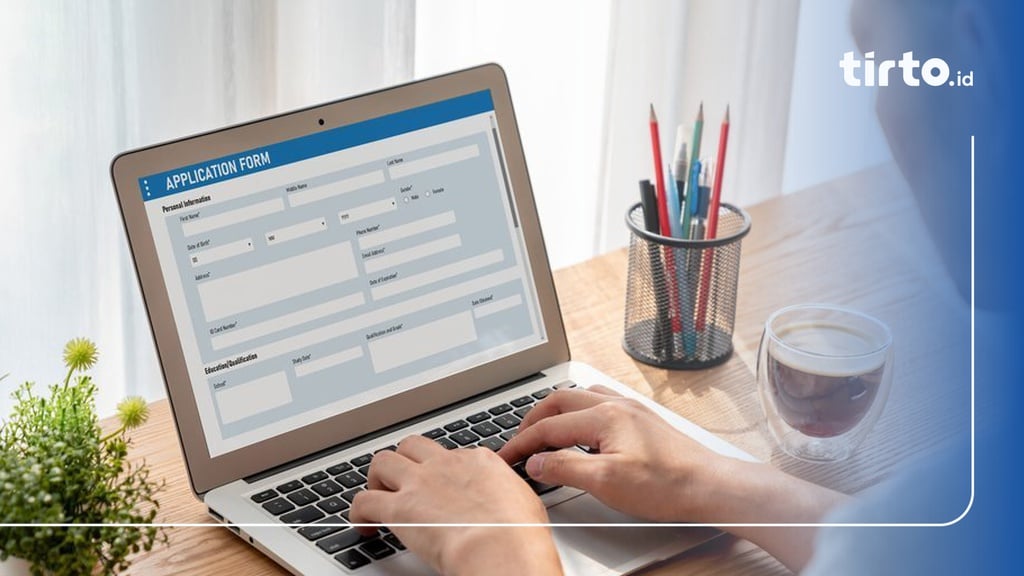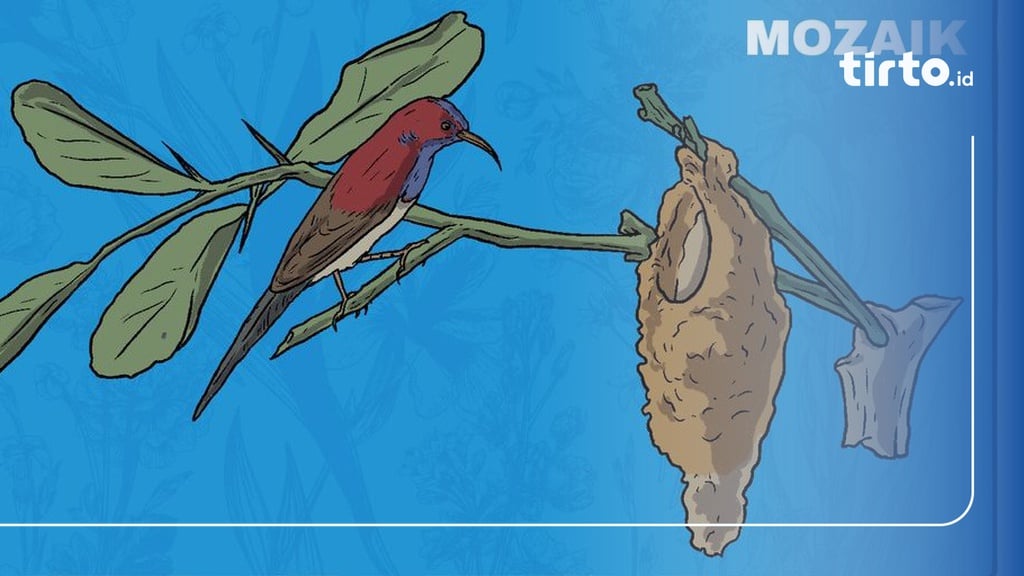tirto.id - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan mampu dicapai dalam empat tahun ke depan. Target swasembada pangan tentu bukan perkara mudah dan mesti ditopang kebijakan yang tepat. Seiring tantangan itu, Komisi IV DPR RI mengutarakan saran kepada pemerintah agar mencontek metode swasembada pangan yang dilakukan Presiden Soeharto di era Orde Baru.
Ide tersebut diusulkan oleh anak dari Soeharto yang juga Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Menurut Titiek, pemerintah dapat menyesuaikan skema swasembada era Soeharto dengan kondisi yang dihadapi hari ini. Dia menilai pemerintah tidak perlu malu jika harus mencontek program presiden terdahulu.
“Bukan karena Pak Harto ya. Zamannya Pak Harto dulu, kita bisa swasembada beras,” ucap Titiek di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Titiek menilai program presiden terdahulu yang tak berhasil dapat diperbaiki atau ditinggal sekalian. Dia menekankan bahwa program swasembada era Soeharto berhasil bukan hanya karena sosok ayahnya itu, melainkan didukung sumber daya manusia yang unggul pula.
“Kenapa kita enggak tinggal nyontek saja, lihat, dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang,” tutur Titiek.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, memandang maksud Titiek kemungkinan besar mengacu pada momen keberhasilan pemerintahan Orde Baru mencapai swasembada beras pada 1984 silam. Menurutnya, Titiek tidak serta-merta mengajak pemerintah mencontek bulat-bulat kebijakan Soeharto.
Pasalnya, di era Orde Baru, selain diwarnai kegemilangan capaian swasembada beras, ternyata diikuti kekecewaan yang berkepanjangan. Terlebih, Khudori menilai konteks sosio-politik hari ini sudah jauh berbeda dengan era Orde Baru yang sentralistik dan monolitik.
Sejak munculnya otonomi daerah setelah Soeharto tumbang, persoalan pangan dan pertanian tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.
“Saya sih menafsirkan mencontek itu bukan meniru mentah-mentah, tapi melihat, memilah, dan memilih mana yang baik dan bisa diteruskan dan meninggalkan yang tidak seharusnya,” kata Khudori kepada reporter Tirto, Kamis (7/11/2024).
Resep Swasembada Orde Baru
Khudori menjelaskan bahwa target swasembada beras zaman Soeharto digenjot lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang disokong jargon Revolusi Hijau. Lewat program Bimbingan Masal (BIMAS), pemerintah mendorong peningkatan hasil produksi beras.
Dengan adopsi paket usaha tani, produksi beras dilipatgandakan menggunakan bantuan teknologi, seperti bibit varietas unggul, pemberatasan hama dan penyakit dengan pupuk kimia atau anorganik, sistem pengairan yang baik, teknologi pengolahan, termasuk penguatan penyuluhan.
Jika melihat sisi hasilnya semata, Revolusi Hijau ala Soeharto memang sukses menggenjot produksi beras gila-gilaan. Pada 1984, produksi beras nasional mampu mencapai angka sekitar 27 juta ton, sementara konsumsi beras dalam negeri saat itu sedikit di bawah 25 juta ton.
Jadi, masih ada sekitar 2 juta ton stok beras cadangan. Pemerintah pun tetap membuka sedikit keran impor demi menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Capaian swasembada beras ini mengantar Soeharto mendapatkan penghargaan medali emas bertulis “From Rice Importer to Self Sufficiency”dari Food and Agriculture Organization (FAO). Soeharto juga menjadi pembicara khusus pada Konferensi ke-23 FAO di Roma, Italia, pada 14 November 1985. Indonesia bahkan mampu menyumbang 100.000 ton beras untuk rakyat Afrika yang kelaparan.
“Bahkan Indonesia saat itu relatif produktivitasnya lebih tinggi dan lebih pendek waktunya mencapai peningkatan berlipat ganda dibandingkan negara-negara lain, seperti Jepang, Taiwan, dan Thailand,” kata Khudori.
Menurut Khudori, salah satu resep keberhasilan swasembada beras era Soeharto adalah koordinasi visi-misi pemerintah pusat dan daerah untuk menggenjot produksi. Hal itu tentu didukung dengan kebijakan “tangan besi” Soeharto. Namun, hal positifnya terjadi suatu keseriusan di tingkat daerah untuk menggenjot target swasembada yang dikontrol pusat.
Saat itu, program yang menurut Khudori bagus adalah kehadiran Catur Sarana Unit Desa di desa-desa. Program ini terdiri atas empat kompenen: kios sarana produksi, BRI Unit Desa, Penyuluhan Unit Desa (PPL), Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa.
Sayangnya, kata Khudori, upaya semacam ini tidak hadir sejak otonomi daerah menjadikan sektor pertanian sebagai agenda pilihan prioritas pemerintah daerah.
“Kita bisa cek sebetulnya. Dari 500-an lebih kabupaten dan kota itu, mana sih sebetulnya yang serius mengurus pertanian? Mana sih yang serius mengurus penyuluhan? Mana sih yang serius mengurus pengairan? Tidak banyak,” ucap Khudori.
Ekses Revolusi Hijau
Namun, Revolusi Hijau ala Soeharto bukan tanpa catatan. Kekecewaan akan dampak sosial ekologis dari program yang digenjot untuk mencapai swasembada beras ini justru jauh lebih besar. Swasembada beras pun hanya bertahan hingga 1989. Seterlah itu hingga sekarang, impor beras jadi pilihan andalan ketika produksi dalam negeri turun.
Khudori menjelaskan bahwa paket teknologi Revolusi Hijau yang mendorong penggunaan pupuk anorganik dan pestisida terbukti merusak tanah dan lingkungan. Target mengejar produksi beras sebesar-besarnya pun tidak diiringi dengan upaya menjaga kontinuitas produksi.
Maka tak mengherankan capaian swasembada beras Soeharto cepat redupnya. Pasalnya, adopsi inovasi dan teknologi seharusnya memikirkan aspek keberlanjutan produksi.
Mimpi besar mengejar produksi gila-gilaan ternyata abai prinsip pertanian yang ramah lingkungan. Kualitas tanah terdegradasi dan bahkan sampai digolongkan sebagai “tanah sakit” dan produktivitasnya pun menurun.
Sayangnya, Revolusi Hijau membuat adopsi teknologi dan industrialisasi sektor pertanian jadi habitus yang terpatri hingga kini. Pemerintah masih memakai kacamata mengerek produksi padi sebesar-besarnya tanpa memikirkan kontinuitas produksi. Hal ini, menurut Khudori, tercermin dari sikap pemerintah yang mendorong Indeks Pertanaman (IP) semakin rapat tanpa memberikan kesempatan lahan untuk beristirahat.
“Itu pasti melawan kodrat alam. Apa? Hama dan penyakit kalau terus menerus dalam satu siklus, satu tahun itu ditanami padi terus [tanpa istirahat] kalau ada wereng, tikus, ini enggak terputus. Jadi, akan terus ada [hama dan penyakit],” terang Khudori.
Jangan Terulang Kembali
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa kebijakan semacam Revolusi Hijau ala Soeharto sebaiknya tidak lagi digunakan. Pasalnya, ekstensifikasi pertanian berimbas terhadap pembukaan lahan baru secara besar-besaran.
Hal ini bukan hanya mengganggu dari sisi lingkungan, tapi juga membutuhkan modal yang sangat besar. Tak heran ketika Orde Baru, kata Bhima, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Soeharto mendapat banyak jatah konsesi pembukaan lahan yang besar atas nama proyek swasembada pangan.
Selain itu, varietas unggul yang selalu dimunculkan menggeser varietas-varietas lokal yang tidak rakus hara dan nonrekayasa genetik. Hal ini berlawanan dengan prinsip bio-ekonomi yang diluncurkan forum G20 di mana Indonesia berpartisipasi di dalamnya. Dijelaskan bahwa pengembangan bio-ekonomi – termasuk sektor pangan – harus menghargai kekayaan dari sumber bibit lokal.
“Banyak sekali pengembangan teknologi [era Revolusi Hijau] tidak menghargai local wisdomatau kekayaan intelektual masyarakat adat di daerah yang juga petani kecil,” kata Bhima kepada reporter Tirto, Kamis.
Swasembada pangan Orde Baru juga berpusat pada agenda penyeragaman pangan berupa beras. Beras-isasi terjadi di banyak daerah dengan komando dari pemerintah. Padahal, kata Bhima, setiap daerah di Indonesia pasti memiliki sumber pangan lokal yang beragam dan tidak harus bertumpu pada produksi padi.
“Semua daerah itu disuruh mengkonsumsi beras, padahal masing-masing daerah punya potensi pangan lokal. Papua, misalnya. Padahal, punya sagu di sana, tapi masyarakatnya disuruh mengonsumsi beras,” lanjut Bhima.
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa swasembada pangan yang dikejar pemerintah ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada target jumlah produksi. Namun, ia seharusnya memperhatikan aspek yang lebih luas, seperti kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
Menurut Andri, kalau yang dikejar adalah target produksi beras, tidak usah sampai ke era Soeharto. Era Joko Widodo pada 2017 hingga 2020 saja hitungannya sudah swasembada beras, meskipun di tahun-tahun setelahnya kembali banyak mengimpor beras. Sebab, berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.
“Yang belum diperhatikan dalam swasembada pangan, jika ingin meniru keadaan di zaman Soeharto, yang pertama sekali adalah mengenai kedaulatan pangan,” ucap Andri kepada reporter Tirto, Kamis.
Kedaulatan pangan, kata Andri, diukur dari seberapa besar harga pangan sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu, ia mengacu kesejahteraan petani yang memproduksi pangan.
Pasalnya, swasembada pangan era Soeharto melalui Revolusi Hijau justru telah membuat petani kehilangan kedaulatannya. Sebab, para petani harus bergantung pada modal produksi yang jauh lebih mahal. Ketika harga jual semakin turun, yang bertahan adalah petani dan korporasi yang memiliki tanah dan modal besar.
Akhirnya, kebanyakan petani gurem atau petani skala kecil menjadi buruh tani yang penghasilannya sangat terbatas.
Dampak Revolusi Hijau di atas sesuai analisis Sajogyo (1973) dalam ”Modernization Without Development ini Rural Java”. Sajogyo memandang bahwa kebijakan Revolusi Hijau itu tidak lain adalah modernisasi pertanian yang melahirkan dampak kesenjangan. Namun, di sisi koin yang lain, keuntungan justru mengguyur lapisan atas desa. Hal ini pun mempercepat proletarianisasi petani gurem.
“Ketahanan pangan juga seberapa besar hasil produksi pangan ini dikendalikan oleh negara atau masyarakat secara langsung. Bukan kendali korporasi seperti yang kita lihat pada implementasi food estatesaat ini,” kata Andri.
tirto.id - News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi

 1 week ago
3
1 week ago
3