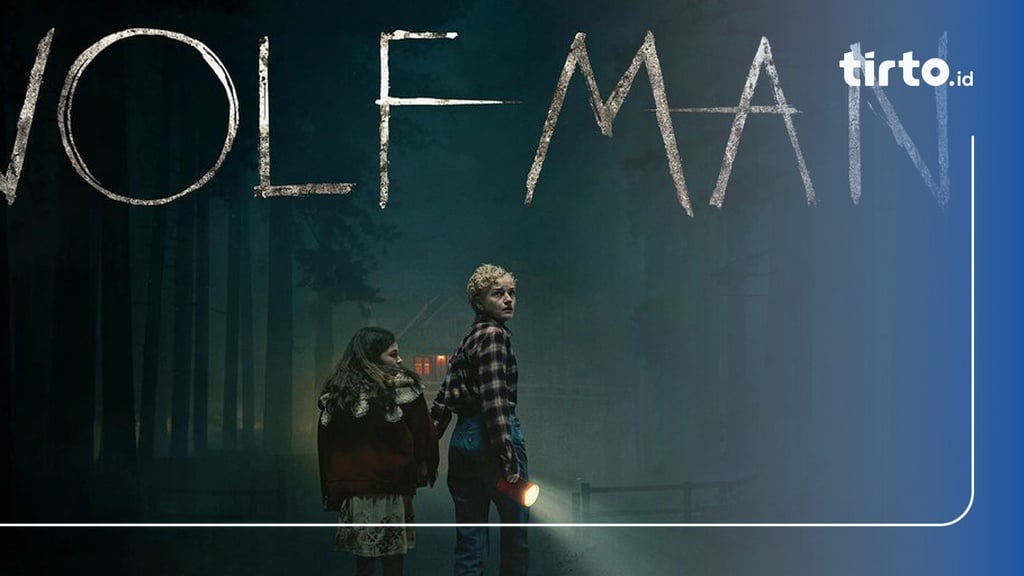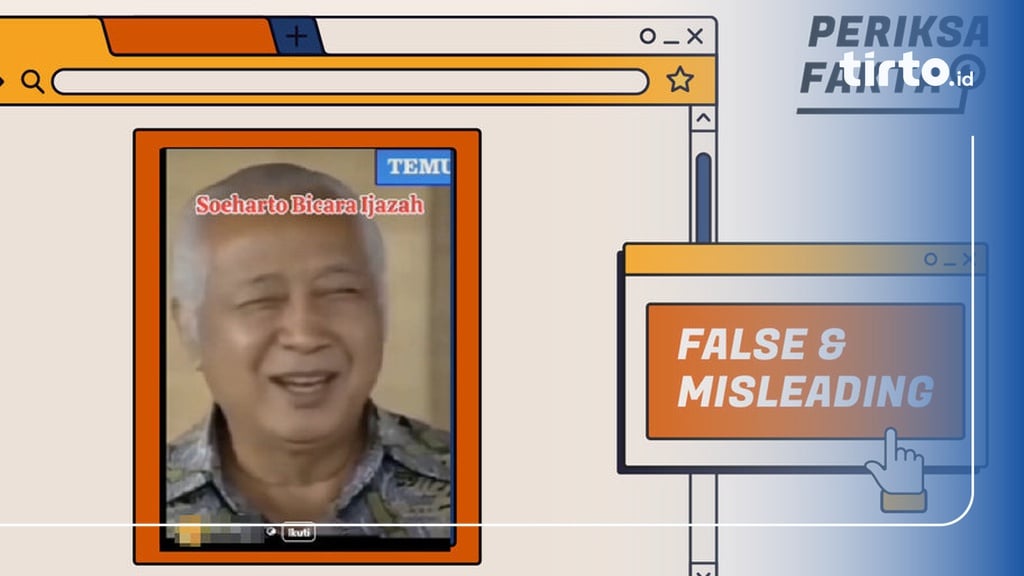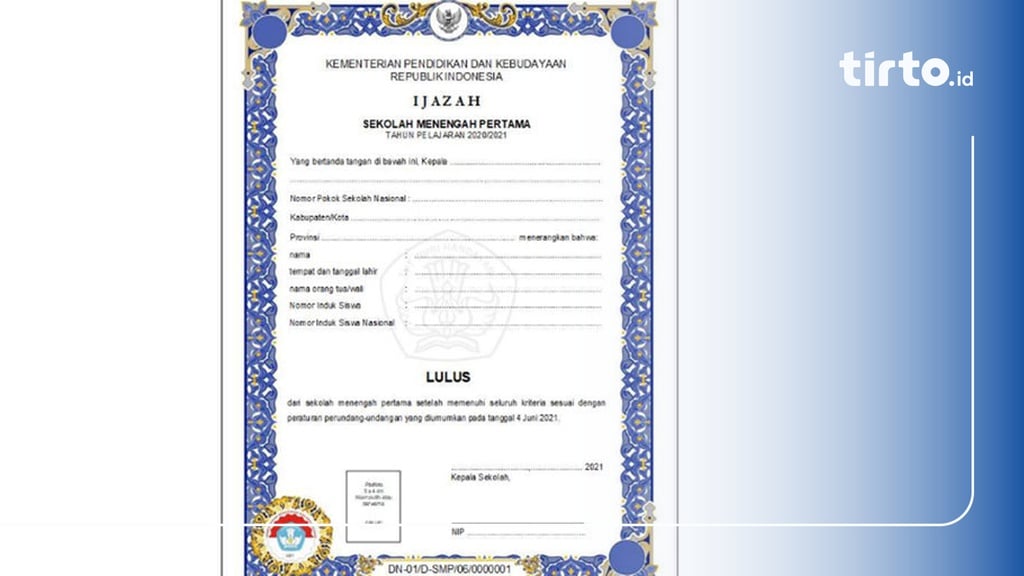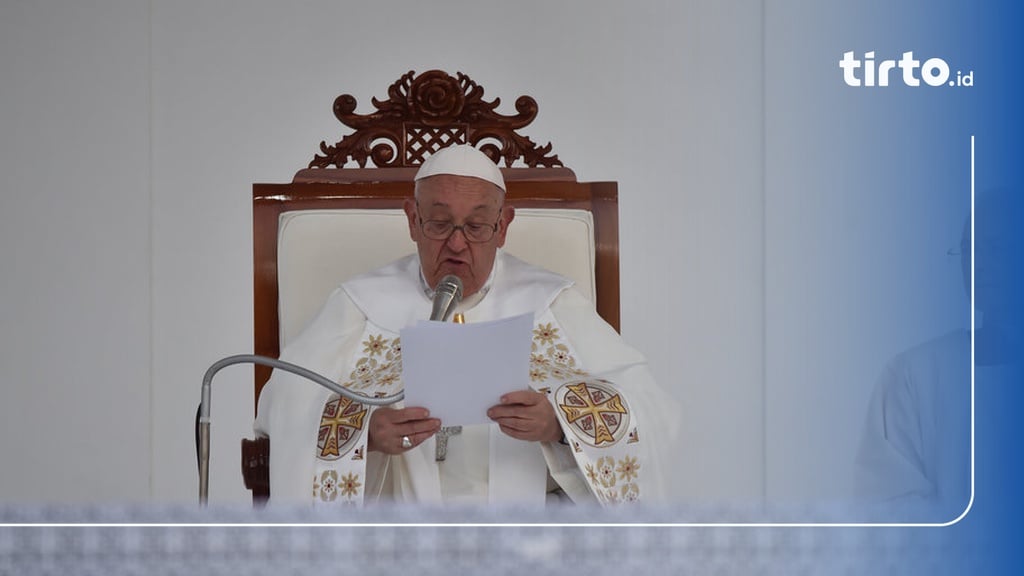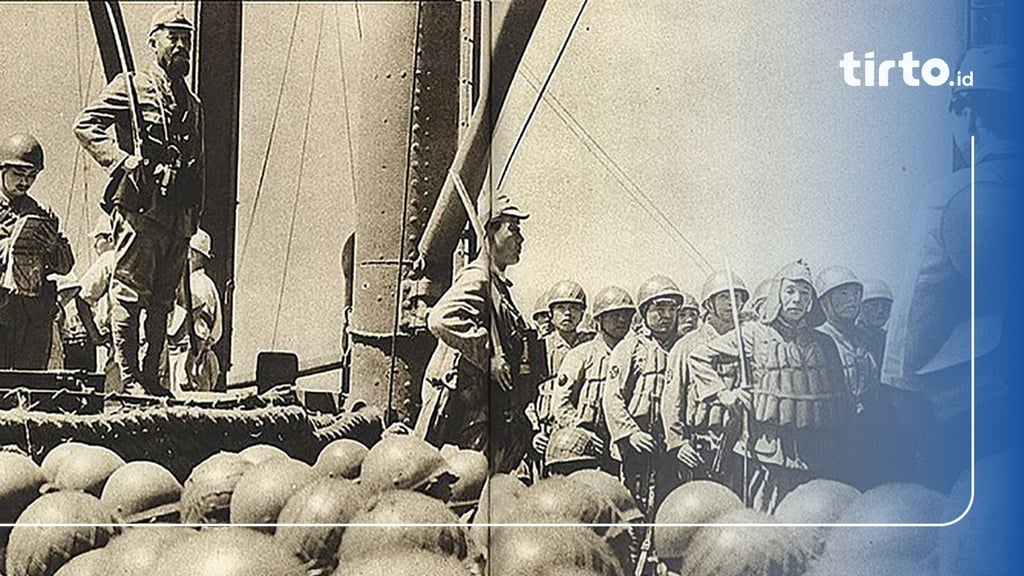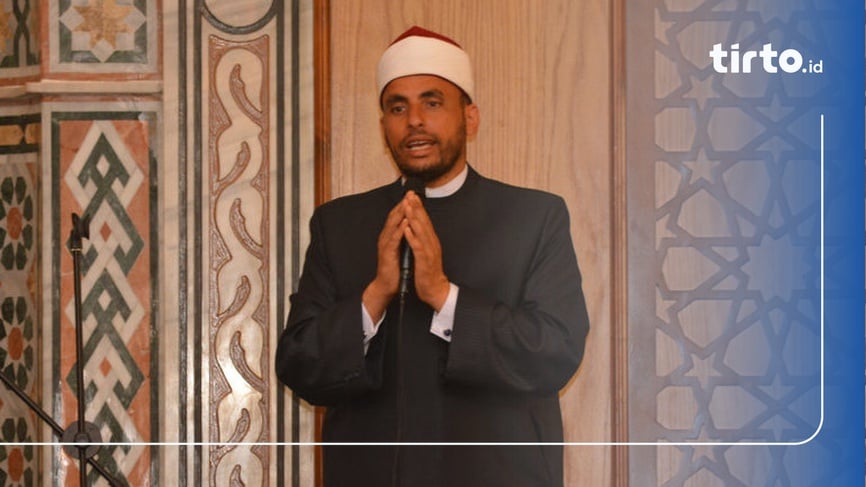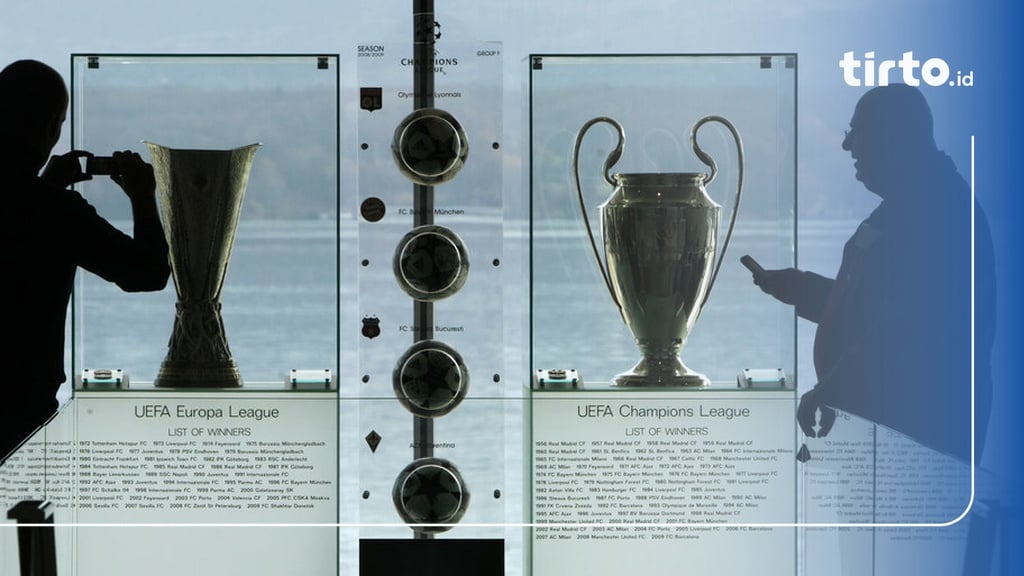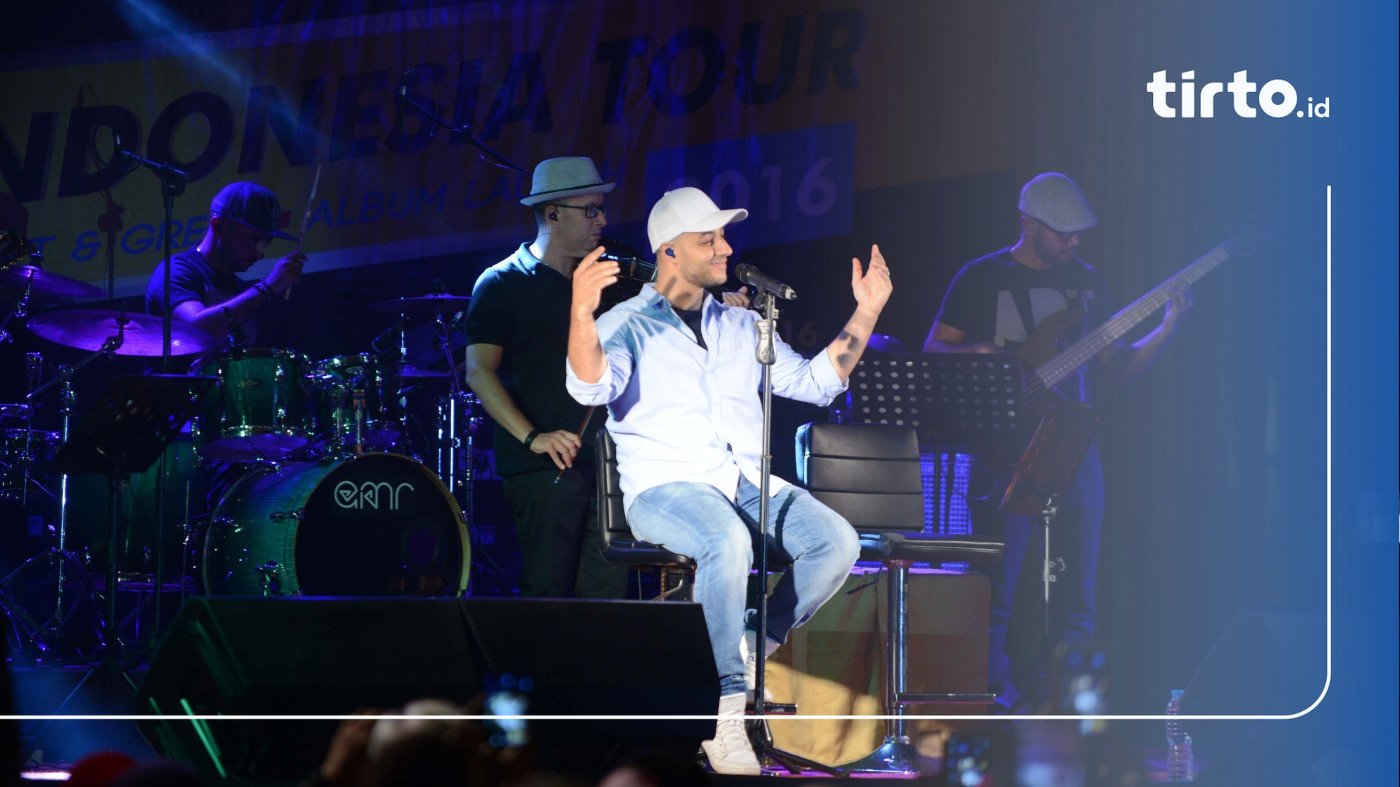tirto.id - Pemerintah kembali mengejar target swasembada pangan yang ditargetkan dicapai pada 2027. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto setidaknya punya dua program yang sudah dilempar ke publik. Pertama, cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 3 juta hektar di luar pulau Jawa yang dikomandoi Kementerian Pertanian. Kedua, program Kementerian Kehutanan memanfaatkan 20,6 juta hektar kawasan hutan menjadi lahan pertanian pangan untuk mempercepat swasembada pangan pada 2027.
Kendati sejarah panjang mimpi swasembada pangan kerap memunculkan dampak buruk, kali ini pemerintahan Presiden Prabowo hakulyakin tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan rezim pemerintahan sebelumnya. Rencana proyek lumbung pangan Pemerintah Prabowo diyakini tak membuat lingkungan dan masyarakat kembali terbebani angan ambisius Istana.
Dari cuplikan dokumen rencana lokasi pelaksanaan program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang diterima Tirto dari Kementan, terdapat tiga provinsi utama di 2025 yang menjadi sasaran program cetak sawah atau ekstensifikasi lahan pangan. Masing-masing wilayah rencananya dicetak 150 ribu hektar sawah, meliputi Kalteng, Kalsel, dan Sumatra Selatan. Provinsi lain akan dicetak seluas 50 ribu hektar untuk sawah.
Adapun optimalisasi lahan tahun ini bakal menyasar total seluas 500 ribu lahan. Proyek ini akan dilaksanakan di 14 provinsi dengan rincian 48 kabupaten/kota. Ditotal, ada 1 juta hektar lahan serta sawah yang digarap pemerintah tahun ini untuk program pangan.
Kendati begitu, sejumlah pengamat lingkungan tidak begitu optimistis dengan klaim dan janji manis pemerintah. Pasalnya, proyek-proyek lumbung pangan terdahulu memperlihatkan bahwa mimpi untuk mencapai swasembada pangan selalu mengorbankan alam dan masyarakat lokal. Ancaman tersebut tampaknya kembali terkerek dalam ambisi swasembada pangan Prabowo.
Ketua Task Force Cetak Sawah Kementan, Husnain, menjelaskan bahwa rencana mengejar target swasembada pangan pemerintahan Prabowo ini memang akan menyasar lokasi yang bisa dioptimalkan untuk pertanian pangan, seperti lahan-lahan rawa. Namun, Uut –sapaan akrabnya-- memastikan program lumbung pangan era pemerintahan Prabowo tak akan mengulang kegagalan masa lalu.
“Termasuk lahan eks PLG atau FE [food estate]. Cetak sawah dilakukan di lahan baru atau lahan sawah yang ditinggalkan lebih dari 15 tahun karena rusaknya saluran irigasi,” kata Uut kepada wartawan Tirto lewat keterangan tertulis, Jumat pekan lalu.
Menurutnya, program cetak sawah dan optimalisasi lahan melibatkan petani lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Selain itu, program ini didukung penggunaan teknologi yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
Husnain percaya optimalisasi lahan yang sudah eksisting meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas. Dengan begitu, swasembada pangan diyakini bisa tercapai pada 2027. Ia juga memberi sinyal program ini akan lebih berhasil dibandingkan proyek food estate rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Istilah food estate lebih sentralistik hanya di beberapa tempat, tapi lebih komprehensif. Sementara oplah [optimalisasi] lahan tersebar di semua provinsi yang ada LBS rawa, melalui perbaikan infrastruktur khususnya pengairan dan bantuan olah tanah dan alsin,” jelas Uut.
Setali tiga uang, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menampik bahwa rencana mengubah kawasan hutan 20,6 juta hektar sebagai areal cadangan pangan menyebabkan deforestasi. Menurut pandangan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut, Ade Tri Ajikusumah, yang terjadi adalah sebaliknya. Program ini berpeluang melakukan reforestasi secara tidak langsung karena akan dijalankan dengan sistem agroforestri.
“Bukan diubah menjadi lokasi pertanian tapi kawasan hutan yang digunakan, dioptimalisasi melalui sistem agroforestri atau sylvo forestry,” kata Ade kepada wartawan Tirto lewat pesan singkat, Kamis pekan lalu.
Ade mengeklaim agenda ketahanan pangan ini tidak bakal menghasilkan deforestasi karena melakukan optimalisasi kawasan hutan. Namun ketika ditanya detail, Ade tidak membeberkan secara rinci di mana saja lokasi hutan yang digunakan untuk rencana ambisius ini.
“Lokasinya menyebar, ada Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan seterusnya seluruh Indonesia,” jelas Ade.
Dalam dokumen rencana program Kemenhut yang diperoleh Tirto, rincian luasan hutan 20,6 juta hektar tersebut didapat dari kawasan hutan belum berizin sebesar 15,53 juta hektar dan kawasan hutan berizin 5,07 hektar. Detail kawasan hutan belum berizin yang bisa digunakan yakni: hutan lindung dialokasikan 2,29 juta hektar serta hutan produksi dialokasikan 13,24 juta hektar untuk cadangan pangan dan energi.
Sementara hutan berizin, dialokasikan dari wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak aktif yang berpotensi dicabut seluas 3,17 juta hektar. Ditambah dengan potensi pangan lewat skema persetujuan perhutanan sosial seluas 1,9 juta hektar. Luas persetujuan untuk skema perhutanan sosial hingga Agustus 2024, tercatat sekitar 8 juta hektar.
Menurut dokumen Kemenhut, dari total 1,9 juta hektar area perhutanan sosial (SK definitive) yang dicadangkan untuk lahan pangan, terdapat sekitar 389.406 hektar cocok untuk padi gogo. Adapun untuk cadangan energi, Kemenhut berencana menanam 1 juta hektar pohon aren untuk menghasilkan bioetanol. Target agar Indonesia menutup kebutuhan impor BBM.
“Bahasanya bukan pembukaan kawasan hutan tapi optimalisasi kawasan hutan yang tidak terpakai,” ungkap Ade.
Lumbung pangan selalu menjadi rencana di mana hutan dikerat-kerat dan dihabisi untuk ambisi politik pangan yang berujung kegagalan. Dampak ekologis dan sosial dari ambisi swasembada pangan Prabowo kali ini juga terbuka lebar.
Mengingatkan bencana ekologis yang menimpa masyarakat adat, petani, dan rakyat luas imbas proyek lumbung pangan yang mendegradasi kawasan hutan. Pasalnya, sulit tidak menduga pemerintah Prabowo-Gibran akan berpihak pada kelestarian alam dan hutan.
Desember tahun lalu, dalam gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Bappenas, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia perlu menambah perluasan penanaman kelapa sawit tanpa takut disebut menyebabkan deforestasi. Ia beranggapan, sawit merusak hutan itu tidak benar, sebab sawit juga menyerap karbon dioksida seperti pohon lainnya.
Sehari berselang, giliran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan pemerintah bakal memanfaatkan sekitar 20,6 juta hektar kawasan hutan untuk cadangan ketahanan pangan dan energi. Termasuk untuk mendukung proyek food estate hingga tingkat desa.
Ekstensifikasi lahan secara masif demi proyek lumbung pangan yang mengorbankan jutaan hektar hutan, adalah pengulangan dari proyek-proyek besar sebelumnya yang gagal. Proyek serupa pernah dijalankan sebelumnya, dan hasilnya adalah kehancuran lingkungan yang masih bisa dirasakan hingga hari ini. Lihat bekas proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) era Soeharto. Dirancang untuk mengubah lahan gambut Kalimantan Tengah menjadi sawah produktif, proyek ini malah melahirkan salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Lahan gambut yang dikeringkan kehilangan daya serapnya, berubah menjadi ladang api setiap kali kemarau. Di era Jokowi, kesalahan yang sama diulang lagi dengan proyek Food Estate di Kalimantan, Sumatra, hingga Nusa Tenggara. Pemerintah membuka hutan untuk sawah dan tanaman pangan, namun yang dituai justru degradasi lahan besar-besaran. Di Kalimantan Tengah misalnya, food estate di lahan eks-PLG memperparah degradasi gambut dan menciptakan titik-titik kebakaran baru.
Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Sayangnya, deforestasi dan kebakaran masih mengancam keberadaan hutan. Mengutip data dari Global Forest Watch, pada 2001, Indonesia memiliki 93,8 juta hektar hutan primer yang mencakup lebih dari 50 persen dari luas wilayahnya. Namun di 2023, Indonesia kehilangan 292 ribu hektar hutan primer yang setara dengan emisi karbon dioksida sebesar 221 juta ton.
Padahal, penghentian deforestasi penting untuk menyerap emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Penelitian terbaru yang diterbitkan di Nature Climate Change yang dikutip World Resources Institute menemukan bahwa hutan dunia menyerap sekitar dua kali lebih banyak karbon dioksida daripada yang dikeluarkan antara tahun 2001 dan 2019. Dengan kata lain, hutan menyediakan penyerap karbon yang bisa menyerap sekitar 7,6 miliar metrik ton karbon dioksida setiap tahunnya.
Jika menilik data pemerintah lewat Badan Pusat Statistik (BPS), tren deforestasi netto, yakni luas deforestasi dikurangi dengan luas reforestasi memang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, angka deforestasi netto tertinggi pada 2014-2015 dengan total deforestasi seluas 1,09 juta hektar.
Setelah itu, angka deforestasi versi pemerintah cenderung menurun, pada 2021-2022 deforestasi netto tercatat di angka 104.032 hektar terendah dalam 10 tahun terakhir. Meski begitu, angka deforestasi ini bisa dikatakan masih relatif besar. Sebagai perbandingan, luas deforestasi sekitar 115,46 ribu hektar sepanjang 2019 dan 2020 ini hampir sebesar negara bagian Los Angeles di Amerika Serikat (AS) dan sedikit lebih besar daripada Hong Kong.
Ahli hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, I Gusti Agung Made Wardana, meyakini konteks proyek lumbung pangan pemerintahan Prabowo sebenarnya melakukan pengulangan terhadap potensi bencana ekologis yang terjadi di era Soeharto. Terlebih, kata Agung, asumsi yang dibangun sekaligus lokasi yang disasar, masih serupa di wilayah bekas PLG. Sekaligus tak ada bedanya dengan food estate era Jokowi yang menyasar lokasi yang sama.
Agung menyebut langkah pemerintah selalu melakukan ‘teknikalisasi’ persoalan pangan. Ini selalu berangkat dari asumsi teknis bahwa sawah di Jawa sudah tidak tersedia. Maka jalan yang diambil adalah ekstensifikasi lahan atau cetak sawah baru di pulau-pulau lain. Agung menilai ini merupakan sebuah langkah yang keliru.
“Solusi yang ditawarkan adalah mencetak sawah baru dan hal ini kemudian memakan kawasan-kawasan habitat asli, misalkan satwa liar dan lain sebagainya atau bahkan ekosistem yang esensial,” kata Agung ketika dihubungi wartawan Tirto, Rabu (19/2/2025).
Ia mencontohkan dampak dari proyek lumbung pangan di areal gambut Kalimantan Tengah. Di sana, dibangun kanal-kanal yang justru merusak kemampuan gambut menampung air. Ini menyebabkan gambut menjadi semakin kering dan rentan terbakar.
Ketika kebakaran melanda, emisi gas rumah kaca atau metan yang disimpan oleh gambut terbawa ke atmosfer, memperburuk perubahan iklim. Pemerintah seharusnya belajar bahwa kontribusi Indonesia terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim sebenarnya juga disebabkan oleh ulah pemerintah lewat ambisi proyek lumbung pangan.
“Dan dampaknya masih kita rasakan hari ini, ekosistem gambut itu membutuhkan ribuan tahun untuk bisa dipulihkan karena itu melalui proses yang alamiah,” lanjut Agung.
Bencana Ekologis Berulang: Mulai PLG hingga Food Estate
Di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, kondisi kawasan hutan Indonesia bisa dibilang tidak baik-baik saja. Proyek lumbung pangan pemerintah ikut berperan atas fenomena deforestasi yang terus terjadi. Menurut studi terbaru yang dirilis Yayasan Auriga Nusantara, Deforestasi Indonesia pada 2024 teridentifikasi seluas 261.575 hektar, atau meningkat 4.191 hektar dari deforestasi tahun sebelumnya yang tercatat seluas 257.384 hektar.
Deforestasi terjadi di seluruh pulau besar di Indonesia. Peningkatan luasan deforestasi terjadi di Kalimantan dan Sumatra, sementara deforestasi di Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menurun.
Catatan Auriga, di 2024, deforestasi terjadi pada 428 kabupaten/kota, alias 83 persen kabupaten/kota di Indonesia yang seluruhnya berjumlah 514. Terdapat 68 kabupaten yang memiliki deforestasi lebih dari 1.000 hektar. Deforestasi ini terjadi di seluruh provinsi, kecuali Jakarta. Dilihat dari status penguasaan lahan, 57 persen deforestasi terjadi di lahan yang dikuasai negara atau kawasan hutan.
Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara, Hilman Afif, menyampaikan, temuan tim mereka di lapangan terdapat seluas 1.515 hektar deforestasi pada tahun lalu disumbang kegiatan proyek food estate Merauke yang kini menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran. Hilman menilai, mimpi swasembada pangan yang pasti kembali melakukan ekstensifikasi ini tentu mengancam keberadaan kawasan hutan Indonesia.
“Kasus deforestasi food and energy estate di Merauke setidaknya menghancurkan hutan seluas 1.515 hektare. Kehancuran ini tidak hanya menghilangkan tutupan hutan alam namun turut menghancurkan gambut yang ada di dalamnya,” kata Hilman lewat keterangan tertulis kepada wartawan Tirto, Kamis (20/2/2025).
Berdasarkan analisis yang dilakukan, paling tidak hingga saat ini terdapat seluas 5,3 hektar gambut terdampak dari kegiatan pembukaan lahan di sana. Ke depan, ancaman terhadap hutan alam dan keberlanjutan lingkungan akan terus menghantui. Dari total 2,3 juta hektar lahan food estate di Merauke saat ini, 50 persen wilayahnya (1,1 juta hektare) masih berupa tutupan hutan alam.
Bahkan, terdapat kawasan hidrologis gambut seluas 132.931 hektar yang setengahnya atau sekitar 60 ribu hektar, masih berupa tutupan hutan. Jika ini terus dilanjutkan, Hilman menilai akan memperburuk krisis iklim sebab pelepasan emisi tidak hanya dihasilkan dari kegiatan deforestasi namun juga dari proses subsidensi gambut.
“Sehingga tidak mengagetkan jika ke depan, kita masih akan dihadapkan oleh potensi deforestasi terutama oleh pengembangan proyek pangan dan energi dari bioetanol,” jelas Hilman.
Berikut ini rekam jejak dampak ekologis proyek lumbung pangan dari masa ke masa:
Proyek Lahan Gambut (PLG) era Soeharto
Proyek ambisius lumbung pangan atau food estate bukan merupakan barang baru di negeri ini. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 sebuah proyek ambisius Pemerintah Indonesia untuk mengkonversi hutan rawa gambut menjadi sawah guna mempertahankan swasembada pangan diluncurkan dengan nama Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar.
Melalui proyek yang membentang di empat wilayah di Kalteng yakni Kapuas (629.827 ha), Pulang Pisau (618.543 ha), Barito Selatan (197.601 ha) dan Kota Palangkaraya (16.324 ha) ini pemerintah awalnya menargetkan produksi beras tahunan hingga 2,7 juta ton.
Namun, kenyataan jauh dari harapan, berdasarkan catatan Pantau Gambut dari target pencetakan sawah seluas 1,45 juta hektare, hanya sekitar 110 ribu hektare lahan yang terealisasi. Tentu, bukan capaian yang diinginkan dari proyek yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah ini.
Tak hanya gagal menggapai target yang dicita-citakan, lebih parah proyek ini turut memicu adanya bencana ekologis di wilayah sekitar. WALHI bahkan menyebut proyek ini sebagai tonggak sejarah kerusakan gambut yang tidak terpulihkan dan menjadi sumber bencana lingkungan dan sumber utama kebakaran hutan lahan gambut hampir dua dekade terakhir.
Berdasarkan studi yang diterbitkan IPB Press, kawasan eks PLG menjadi wilayah yang sangat rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun. Kawasan eks PLG bahkan menjadi tempat yang paling rawan kebakaran dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan bahkan Indonesia, dengan minimal 5.000 hotspot per tahun.
Kombinasi dari perusakan hutan, pembukaan lahan, dampak pembangunan kanal dan peristiwa iklim El Niño yang sangat parah pada 1997 atau setahun setelah proyek ini diluncurkan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut yang paling parah di area PLG ini.
Berdasarkan catatan Pantau Gambut, api dari kebakaran hutan ini diperkirakan turut membakar 730.000 hektar area hutan Indonesia pada tahun 1997–1998. Jika digambarkan, luasan ini sama dengan 11 kali luas Provinsi Jakarta.
Polusi udara yang ditimbulkan karena kabut dari kebakaran pada 1997 itu bahkan diklaim menjadi yang terparah dalam sejarah asia tenggara selama beberapa dekade terakhir. Studi yang dilakukan Page dkk (2002) memperkirakan bahwa 810 – 2570 Mt karbon dipancarkan selama insiden kebakaran pada tahun 1997 tersebut.
Sementara, penelitian yang dilakukan Goldstein (2016) dalam jurnal berjudul “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project” memperkirakan bahwa jumlah karbon dioksida yang dimuntahkan kebakaran Indonesia ke atmosfer pada akhir 1997 setara dengan sekitar 13-40% emisi karbon tahunan global dari bahan bakar fosil.
Pakar hukum lingkungan UGM, I Gusti Agung Made Wardana, menilai dampak bencana ekologis yang ditimbulkan dari proyek PLG masih dirasakan hingga saat ini. Hal ini disebabkan, ekosistem gambut membutuhkan proses alamiah selama ribuan tahun untuk bisa pulih.
“Dampaknya juga sangat masif tidak hanya terhadap ekosistem, biodiversity, tapi juga terhadap masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar situ yang kemudian kehilangan kehidupan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kacamata green criminology atau kriminologi hijau, sebuah kejahatan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang melahirkan marabahaya baik oleh tindakan legal maupun yang tidak legal. Dalam kasus ini, ia menilai bahwa proyek PLG ini telah masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
“Sepanjang kemudian ada kerusakan lingkungan dan bahaya ekosistem, bahaya ekologi yang ditimbulkan oleh sebuah kejahatan, maka itu harus dipandang sebagai sebuah kejahatan lingkungan,” ujarnya.
Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) era SBY
Pada awal dekade 2000-an, pola produksi pangan nasional mulai beralih ke timur Indonesia. Lanskap Merauke yang berupa dataran rata menarik para petinggi negeri membuka peluang investasi di bidang pertanian skala besar.
Anton Apriyantono, Menteri Pertanian kala itu, menargetkan pembukaan lebih dari 2 juta hektare lahan di Merauke untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Macam komoditasnya berupa tebu, jagung, dan tentunya, padi—meski pada perjalanannya proyek ini lebih banyak diisi tanaman industri.
Bak gayung bersambut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui peluang tersebut dan lahirlah program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Pemerintah pada saat itu merencanakan lahan seluas 2,5 juta hektar untuk proyek MIFEE. Namun, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional merekomendasikan area potensial yang efektif seluas 1,2 juta hektar.
Diproyeksikan MIFEE akan menghasilkan 2 juta ton beras dan jagung, 0,2 juta ton kedelai, 2,5 juta ton gula, 1 juta ton CPO dan 64 ribut ton daging sapi per tahun. Alih-alih berhasil mencapai target, WALHI menyebut program ini malah melahirkan banyak persoalan dibanding manfaat bagi Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua.
Temuan Ahmad Arif dari HarianKompas, seperti yang dikutip dari hasil temuan Komnas HAM, proyek MIFEE telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan kemandiriannnya atas pangan lokal, karena dipaksa mengkonsumsi makanan instan yang bukan menjadi kebiasaannya. Hal ini bisa disebut sebagai gastro kolonialisme.
Sementara itu, temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut proyek MIFEE ini telah melakukan deforestasi dan merampas tanah Masyarakat Adat. Suku Malind adalah salah satu komunitas adat yang menjadi korbannya.
Hasil penelusuran Tirto di 2022 menemukan masifnya pembongkaran hutan untuk program lumbung pangan nasional – yang akhirnya malah diisi tanaman industri – ini menyebabkan berbagai dampak. Selain hancurnya sumber-sumber penghidupan, pangan, dan keragaman hayati, bencana ekologis pun datang.
“Kehadiran perusahaan (pada proyek MIFEE) berdampak pada lingkungan, yang akhirnya membuat air tercemar, banjir, dan longsor,” tutur Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Masyarakat Adat (Pusaka), Franky Samperante, (7/12/2022)
Salah satu warga yang tinggal di Kampung Sinegi, Distrik Animha, salah satu wilayah yang masuk konservasi kawasan hutan untuk MIFEE, menyebut proyek tersebut memicu pencemaran limbah di kampungnya.
“Setelah pabrik masuk ke sini, air limbahnya mencemari sungai, membuat air jadi merah, tidak macam dulu lagi. Ikan mati. Sagu mati, kalau hidup pun tepungnya sedikit,” keluh salah satu warga bernama Vitalis (7/12/2022).
Berdasarkan penelusuran Tirto di laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu 2024 saja telah terjadi tiga bencana alam di Kabupaten Merauke yang berdampak pada 3.557 warga, 849 rumah, satu fasilitas pendidikan dan peribadatan.
Food Estate era Jokowi
Pemerintahan Jokowi menjadikan proyek lumbung pangan atau food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan dalih mencapai ketahanan pangan. Namun, ambisi besar ini justru melahirkan bencana ekologis di berbagai daerah. Alih-alih menghasilkan surplus pangan, proyek lumbung pangan ini merusak lingkungan, menggusur masyarakat lokal, dan membebani anggaran negara.
Food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, hingga Papua, dan sejumlah wilayah lain awalnya digadang-gadang sebagai solusi mengatasi ketergantungan impor pangan. Namun, proyek ini mengulang kegagalan Mega Rice Project Orde Baru di Kalimantan yang berakhir menjadi lahan terlantar. Lahan-lahan yang dialihfungsikan tanpa kajian mendalam itu justru mengundang bencana ekologi.
Dalam studi bertajuk Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu (2024) yang dibuat Pantau Gambut, menemukan bahwa peninggalan eks-PLG pada umumnya ditumbuhi semak belukar setinggi orang dewasa (1–2 meter). Meski cukup tinggi, semak ini cuma menyerupai rerumputan, bukan pohon. Semak belukar ini tumbuh subur karena pohon yang sebelumnya menutupi lahan ini telah dibabat habis.
Namun, kawasan bekas PLG ini tetap menjadi sasaran ekstensifikasi food estate Jokowi. Meliputi daerah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Meski begitu, lahan yang dibuka tidak lantas menjadi sawah. Dari 18 titik sampel yang telah dibuka, 15 titik dibiarkan terbuka dan terbengkalai hingga kembali ditutupi oleh semak belukar. Bahkan, tutupan lahan pada 3 titik sampel berubah menjadi perkebunan sawit karena diakuisisi oleh perusahaan perkebunan sawit swasta.
Kondisi lahan pada desa-desa yang menjadi lokasi proyek Food Estate memprihatinkan. Perubahan vegetasi ini berdampak serius terhadap lingkungan di sekitar lokasi pembukaan hutan dan kanalisasi yang dilakukan secara masif pasca-program PLG. Karhutla yang terus menerus, pencemaran air, pelepasan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), hingga yang paling menakutkan hilangnya lapisan gambut sebagai pertanda kehilangan fungsi ekologis gambut.
Juru Kampanye Pantau Gambut, Abil Salsabila, menyatakan PLG dan food estate dilakukan dalam skala yang masif dan tidak mempertimbangan karakter ekosistem gambut yang tidak cocok ditanami padi dengan pola tanam seperti di Jawa. Kegagalan PLG meninggalkan degradasi ekosistem gambut yang parah dan menjadi penyebab kebakaran hutan berulang. Seharusnya area yang telah terdegradasi direstorasi dengan mengacu pada PermenLHK No. P.16/2017, namun hal tersebut tidak terjadi dan justru dijadikan proyek food estate.
“Keduanya sama-sama melakukan pengeringan ekosistem gambut lewat kanalisasi yang berpengaruh terhadap perubahan tata hidrologis ekosistem gambut,” jelas Abi kepada Tirto lewat keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).
Pantau gambut menemukan ekstensifikasi food estate Kalimantan Tengah itu menimbulkan degradasi terhadap ekosistem gambut. Terjadi kebakaran berulang sepanjang 2015–2023 di area bekas PLG yang termasuk di wilayah ekstensifikasi food estate. Pada 2015–2020, seluas 434.227 hektar area bekas PLG turut terbakar karhutla. Sementara, pada 2023 terjadi kebakaran kembali seluas 91.352 hektar di area eks-PLG.
Banjir juga menjadi momok menakutkan imbas food estate Kalimantan Tengah. Di daerah Gunung Mas, sebelum ada program lumbung pangan, ketinggian banjir berkisar 10-40 cm. Namun, kini ketinggian banjir berkisar 1-1,5 meter. Banjir besar memang dialami masyarakat Kalteng secara umum pada 2022. Sejumlah daerah bahkan menerapkan tanggap darurat.
Potensi kebakaran hutan dan banjir juga semakin rawan di proyek food estate lain seperti Humbang Hasundutan dan Merauke. Masyarakat adat semakin rentan terhadap ancaman bencana ekologis dan sosial. Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, deforestasi di Papua Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 190.000 hektar pada 2022-2023 akibat proyek ini. Deforestasi ini juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida hingga 782,45 juta ton, yang bertolak belakang dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050.
Darmawardana (2024) dalam jurnal bertajuk “Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau” menilai Food Estate di tiga lokasi dengan keragaman ekosistemnya menunjukkan dampak kerusakan ekologis yang luar biasa seperti deforestasi besar-besaran, kebakaran lahan skala luas, serta degradasi lingkungan.
Menanggapi bencana ekologi yang kerap terjadi di proyek pangan pemerintah, Direktur Sosio-Bioekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Fiorentina Refani, menilai hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki peta kebijakan (road map) yang jelas dalam hal perencanaan pengadaan pangan. Fio juga menilai proyek pangan yang dilakukan pemerintah selama ini acapkali abai dengan aspek bio-region.
“Jadi bio-region itu harus bisa membaca secara spesifik apa potensi yang bisa dikembangkan untuk pangan di suatu wilayah berdasarkan karakteristik ekologisnya, faktor makro klimatik, dan lain sebagainya,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (20/2/2025).
Fiorentina menilai selama ini ada kecenderungan pemerintah seolah memaksakan proyek pengadaan pangan dalam skala yang besar dalam suatu wilayah atau disebut rakus lahan. Hal ini menurutnya menimbulkan pola monokultur yang menambah kerentanan terhadap kondisi ekologis suatu wilayah.
Ia mencontohkan, pemerintah selama ini hanya melihat lahan gambut dan hutan itu sebagai lahan kosong, alih-alih melihat bahwa di dalam hutan dan gambut itu ada fungsi ekologis misalnya untuk daur hidrologi, daur karbon daur nutrisi dan sebagainya.
“Nah itu semua tersimplifikasi karena akhirnya ada konversi terhadap proyek lumbung pangan,” ujarnya.
Solusi Bagi Pemerintah
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menyatakan, kebijakan pangan yang bisa diambil pemerintah mestinya berada dalam bingkai hak, bukan sekadar bisnis. Dengan bingkai hak, politik pangan pemerintah dapat mengedepankan pihak yang memproduksi pangan alias petani serta cara mereka memproduksinya sesuai kearifan pertanian lokal.
Ambisi swasembada pangan pemerintah saban rezim masih terfokus hanya mengamankan kecukupan kuantitas pangan, tanpa mempertimbangkan kondisi petani yang menjadi garda depan target tersebut.
Alhasil, diversifikasi pangan daerah tersisihkan, karena orientasinya adalah dalam tanaman pangan versi pemerintah dalam jumlah besar. Langkah semacam diharapkan tidak diulang kembali di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Nah, sebenarnya mau dimanapun lokasi ditunjukkan, ketika caranya sama, enggak punya kajian, enggak basisnya saintifik, tidak menghormati keberagaman pangan, dia akan rentan gagal secara besar-besaran juga,” kata Uli saat ditemui Tirto di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu.
Sementara itu, Fiorentina dari Celios, meminta pemerintah berhenti merumuskan kebijakan pangan dengan logika top down dan meletakan beban pengadaan pangan di satu daerah. Ia meminta pemerintah bisa melihat secara spesifik apa kebutuhan dan pola pangan di tiap daerah.
Ia mencontohkan, di NTT misalnya, komoditas jagung bisa didorong dengan skala kecil tapi masif. Bukan dengan ekstensifikasi lahan besar-besaran dalam satu wilayah seperti yang terjadi di Merauke yang melakukan konversi lahan, simplifikasi ekologis dan sebagainya.
“Lebih ke penekanan terhadap penghargaan pola pangan yang sudah ada yang dilakukan masyarakat gitu,” tutupnya.
Jika Prabowo tetap menjalankan proyek lumbung pangan dengan metode serupa, yang kita tuai bukan swasembada pangan, melainkan krisis lingkungan yang lebih parah. Bencana yang selama ini terpusat di beberapa wilayah akan meluas ke seluruh Indonesia. Ketahanan pangan tidak bisa dicapai dengan membabat masa depan, tetapi dengan memperbaiki cara mengelola lahan yang sudah ada dan pertanian pangan berkelanjutan.
Jika tidak, maka yang terjadi bukanlah ketahanan pangan, melainkan kelaparan akibat tanah yang tak lagi bisa ditanami dan lingkungan yang semakin tidak bersahabat. Kedaulatan pangan – yang berfokus pada kearifan pangan lokal daerah – seharusnya menjadi langkah yang bisa dipilih pemerintah.
***
Catatan:Tulisan ini merupakan bagian dari Beasiswa Liputan AJI Indonesia dengan topik 100 Hari Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumig Raka.
tirto.id - News
Reporter: Mochammad Fajar Nur & Alfitra Akbar
Penulis: Mochammad Fajar Nur & Alfitra Akbar
Editor: Abdul Aziz

 1 month ago
113
1 month ago
113