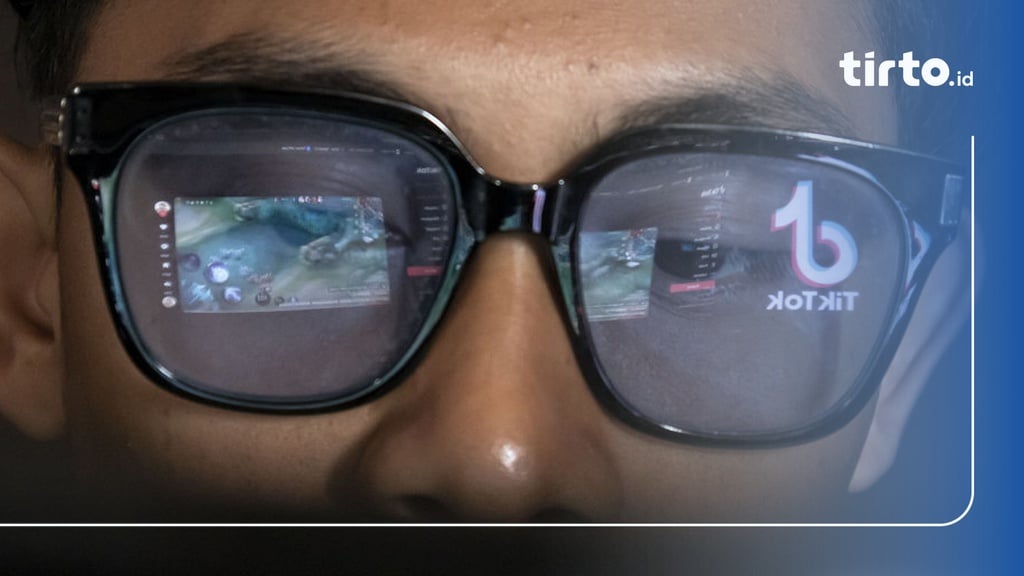tirto.id - Di era Orde Lama, ada sebutan khusus untuk memanggil pejabat dan kepala negara, yakni Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, dan Paduka Tuan.
Mantan Kapolri periode 1978-1982, Awaloeddin Djamin, mengatakan bahwa panggilan-panggilan tersebut kerap dipergunakan saat rapat di lingkungan pemerintahan.
Saat dia masih jadi Kepala Seksi Umum dari 1955-1959, Kapolri Said Soekanto waktu itu meminta anak buahnya memanggilnya dengan sebutan "Paduka Tuan" di depan namanya. Sementara Soekanto memanggil koleganya dengan sebutan "tuan-tuan".
Seturut penuturan Peter Kasenda, sejarawan yang menulis beberapa buku tentang Sukarno, presiden pertama RI itu ingin dipanggil sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR) setelah Demokrasi Terpimpin dikenalkan. Hal ini bahkan termaktub dalam TAP MPRS No. II/MPRS/Mei 1963 yang sekaligus mengukuhkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup.
Dalam beberapa pidatonya, Sukarno menjuluki dirinya sebagai "penyambung lidah rakyat", seperti judul autobiografi yang ditulis oleh Cindy Adams.
Sebutan Paduka Yang Mulia untuk Sukarno kiranya bersumber dari kalangan istana, yang kemudian terdengar lebih familier.
Pengultusan kepala negara kiranya dapat memicu kontroversi, apalagi jika digeser dalam skala moralitas hari ini. Sukarno dan pejabat lain era Orde Lama boleh jadi dikutuk sebagai si gila hormat lantaran terlalu mendewakan julukan.
Namun, berbagai pengultusan untuk kepala negara mengalami animo yang berbeda di setiap masanya. Bagi Sukarno, dia harus dianggap setara raja yang mulia, tetapi panggilan untuk kepala negara setelahnya justru seperti kiasan pujian.
Pengultusan dan Propaganda
Komponis Mus K. Wirya sempat menulis lagu berjudul "Bung Karno Djaya" yang dinyanyikan oleh Onny Surjono. Lagu ini diiringi oleh grup musik sang penulis, yakni Orkes Mus K. Wirya yang direkam dan dicetak oleh PT. Republic Manufacturing Company Ltd. (Remaco).
Lagu yang termuat dalam album Siapa? ini laku keras di pasaran sejak awal peluncurannya. Faktor utamanya, lagu berdurasi 2 menit 38 detik itu mampu memadukan irama tari lenso dengan lirik populis yang mudah dicerna dan dihafal. Mirip pantun kilat dengan nada penuh sukacita. Siapa pun bisa memanggut-manggutkan kepala sembari berdansa, seakan tersihir oleh melodi gitar, flute, dan perkusi yang bertalu-talu.
"Siapa yang tak tahu, awas jangan keliru
Penggali Pancasila, pedoman negara
Bung Karno jaya! Bung Karno jaya!
Bung Karno jaya, sentosa!"
 Presiden Indonesia Sukarno, kiri, menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Jenderal Suharto dalam foto 22 Februari 1967 di Jakarta ini. FOTO/AP
Presiden Indonesia Sukarno, kiri, menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Jenderal Suharto dalam foto 22 Februari 1967 di Jakarta ini. FOTO/AP
Lagu ini kerap diputar dalam siaran Radio Republik Indonesia (RRI). Maklum, itulah satu-satunya radio yang dimiliki negara. Satu segmen yang paling ditunggu-tunggu pemirsa RRI adalah "Pilihan Pendengar". Siapa pun bisa memesan lagu layaknya makanan. Memang kebanyakan pemirsa memesan lagu pop lantaran liriknya terlampau akrab di telinga.
Beberapa musikus hit makers seperti Soetedjo, Mus K. Wirya, Wedhasmara, dan beberapa penyanyi pop pada periode ini cukup berkontribusi meramaikan lagu pop dengan embel-embel Sukarno.
Soetedjo menulis lagu "Untuk PJM Presiden Soekarno" yang dirilis label Irama pada 1965. PJM merupakan singkatan dalam ejaan lama Paduka Jang Mulia.
Lagu ini termuat dalam koleksi pertama dari dua piringan hitam album ....Ia Tetap Diatas!! (1965). Diiringi oleh Orkes Baju pimpinan F. Pareira yang memiliki ciri pembawaan biola dengan teknik gesekan cukup lihai.
Sama seperti lagu "Bung Karno Djaya", lagu ini juga segera mendapat tempat di hati pendengar RRI. Mungkin faktor utamanya berkat kemolekan suara Lilis Suryani yang sudah menjadi penyanyi top Indonesia sejak 1963 berkat lagu "Gang Kelinci", "Jali-Jali", "Selamat Ulang Tahun, dll.
Lilis Suryani dapat mendongkrak popularitas lagu ini sebab dia sudah melanglang buana seantero nusantara. Suaranya elok, ditunjang artikulasi yang jelas serta cengkok yang cenderung stabil. Tak ayal bilamana beberapa tahun kemudian dia dipanggil PJM untuk menyanyi di Istana Negara bersama Titiek Puspa, Nien Lesmana, dll.
"Untuk PJM Presiden Soekarno" adalah salah satu lagu penokohan yang sekaligus merekam situasi politik negara pada waktu itu:
"Manipol USDEK haluan negara kita
Karya Paduka Yang Agung serta mulia"
Menurut Daniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003), Manipol-USDEK adalah akronim dari Manifestoi Politik/Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Haluan ini dianggap sejalan dengan cita-cita bangsa, yang berarti meneladani selain paham tersebut bisa dianggap makar dari ideologi Pancasila.
Sebagai komposer, Soetedjo menerima bayaran sebesar Rp1.200.000 hanya untuk satu lagu ini. Namun sebelum dia dapat menarik bayarannya, rupiah mengalami redenominasi yang menghilangkan tiga angka nol di belakang. Tetapi uang lama dapat ditukar dengan pecahan baru Rp1.200 yang bernilai sama.
Pengaburan Situasi Politik
Sang Diva Tiga Masa, Titiek Puspa merupakan penyanyi kebanggaan Sukarno. Tetapi di masa Soeharto, dia masih melanjutkan karier sebagai penyanyi istana. Hubungannya dengan kedua rezim terlihat baik, terutama makin akrab dengan ibu negara, Suhartini (Tien Soeharto).
Titiek tak mau hanya dikenang sebagai penyanyi. Dia memberikan kado spesial untuk Soeharto dan Golkar. Saat pawai Pemilu 1971, berbarengan dengan HUT Golkar, lagu "Bapak Pembangunan" dinyanyikan untuk pertama kalinya. Pada Pemilu 1987, lagu ini dinyanyikan kembali olehnya di Stadion Utama Senayan bersama grup artis Safari Golkar.
Menurut pengakuannya dalam biografi yang ditulis Alberthiene Endah, Titiek Puspa: A Legendary Diva (2008), lagu itu ditulis Titiek sesaat setelah muncul tayangan Soeharto di TVRI yang tengah menyumbang beras kepada penduduk Ethiopia yang dilanda kelaparan. Bagi Titiek, Soeharto adalah anugerah Tuhan yang diberikan untuk bangsa dan negara Indonesia.
"Sujud kami bagi-Mu yang Esa
Terima kasih atas karunia
Sandang pangan, pembangunan
Kau limpahkan bagi negeri Indonesia!
...
Kepadamu Bapak kami Soeharto
Terima kasih dari rakyat semua
Di dadamu kami sematkan
Bapak Pembangunan Indonesia!"
Dalam buku Power and Political Culture in Soeharto’s Indonesia karya Stefan Eklof (2003), seni disebut sebagai salah satu medium propaganda yang dapat merepresentasikan kekuasaan. Di era Orde Baru, musik dan sandiwara pertunjukan merupakan peranti simbolik komunikasi antara pemimpin dan rakyat.
Pengultusan lewat tokoh politik dapat menjadi simbol "penenang konflik" di antara pemimpin dan rakyat. Semacam sebuah propaganda, dengan sengaja dibuat untuk mengaburkan situasi politik yang sebenarnya.
Fenomena ini termuat dalam "Lagu untuk Pak Soeharto" yang dinyanyikan Edy Sofyan Subing sebagai obituarium pada 2018.
"Tiga puluh dua tahun sudah
Kau menjadi pemimpin kami
Banyak sudah yang telah kau buat
Untuk kami bangsa ini
...
Tak banyak bicara tapi banyak kerja
Tak banyak huru-hara tapi rakyat cukup sejahtera"
Berbeda dengan deretan lagu lain tentang kepala negara. Lagu Edy Sofyan Subing cenderung menampilkan sisi romantisisme pemerintahan Soeharto. Penilaiannya didasarkan nuansa kepositifan ode yang mendayu-dayu, tanpa mencatut analisis gonjang-ganjing politik dan ekonomi semasa Orde Baru bertakhta.
 Presiden Soeharto. FOTO/AP Photo
Presiden Soeharto. FOTO/AP Photo
Romantisisme
Pola romantisisme dalam ode untuk kepala negara jadi semakin kental di era Reformasi. Penjabaran situasi politik kian menipis dan tak lagi menggaungkan pengultusan serta propaganda.
Misalnya dalam "Lagu untuk BJ Habibie" yang dipublikasikan Sapna Music Record pada 2019. Lagu ini dinyanyikan Narti Lestari, sebagai kenangan terhadap Presiden RI ke-3.
"Teriris hati menangis sedih
Menetes air mata di pipi
Mendengar berita kepergianmu
Telah menghadap Sang Ilahi
Baharuddin Jusuf Habibie
Presiden Ketiga Indonesia
Lahir di Tanah Bugis Kota Pare-Pare
Menangislah hati mengenangnya"
Lalu ada lagu yang dibawakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang juga kader PDIP.
Dia menciptakan lagu "Putri Sang Fajar", sebuah karya yang dipersembahkan untuk Megawati Soekarnoputri pada 2012.
Lagu itu menonjolkan ungkapan kagum dan takjub Rano Karno dalam menilai kegigihan semasa Presiden RI ke-5 itu memimpin. "Walau semua ragu, namun tetap engkau jalani," begitu salah satu penggalan liriknya.
Cukup mafhum kemudian apabila lagu yang ditulis untuk Jokowi rata-rata mengisahkan ungkapan syukur dan terima kasih. Dia menjabat dua periode (batas maksimal jabatan presiden setelah Reformasi) dari 2014-2024. Tentu banyak kenangan romantisisme yang cenderung dipilih daripada kritik.
Lagu untuk Jokowi di antaranya "Terima Kasih Presidenku" ciptaan Walden Nadeak yang dinyanyikan Rifega Trio, dan "Terima Kasih Jokowi, Selamat Bekerja Prabowo" yang ditulis Cak Sodiq pentolan grup dangdut kenamaan. Keduanya sama-sama dipublikasikan di penghujung kepemimpinan Jokowi, yakni pada Oktober 2024.
Polanya sudah bergeser jika dibandingkan dengan masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di era Reformasi, ode untuk kepala negara jadi simbolisasi romantisisme antara rakyat dengan penguasanya.
Serupa dengan lagu untuk Prabowo yang berjudul "Pernah di Sana" gubahan Ifan Seventeen bersama Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dalam unggahan musik video di kanal Youtubenya, Ifan Seventeen TV menampilkan thumbnail wajah Prabowo yang mengenakan kemeja cokelat. Ungkapannya masih sama, sajak mendayu-dayu.
tirto.id - News
Kontributor: Abi Mu'ammar Dzikri
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Irfan Teguh Pribadi

 1 month ago
113
1 month ago
113