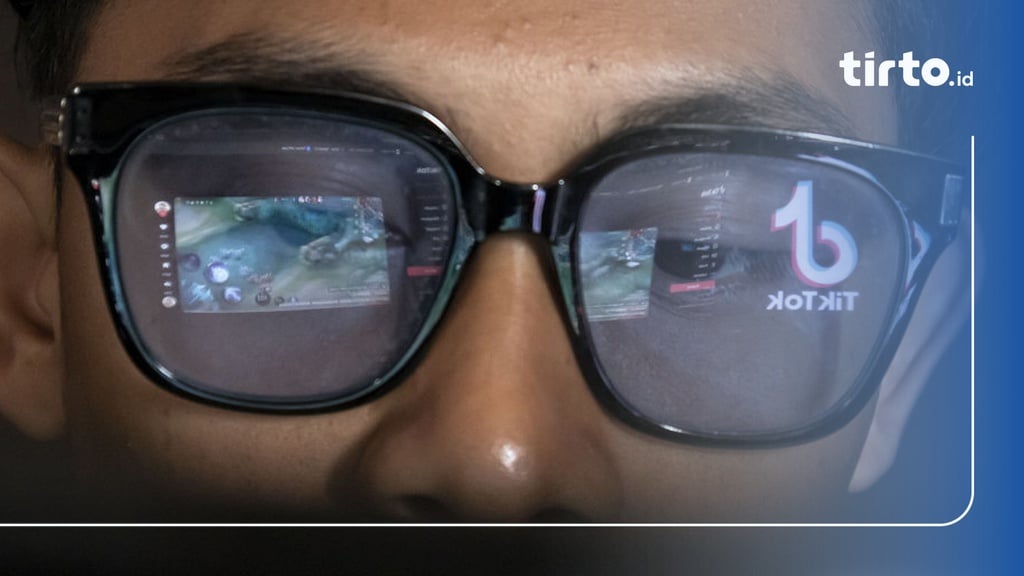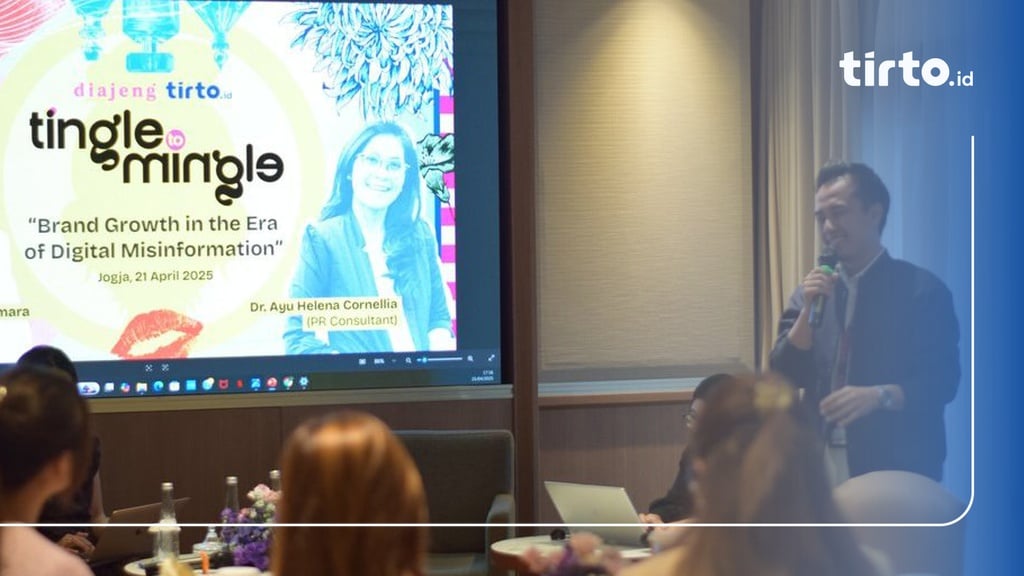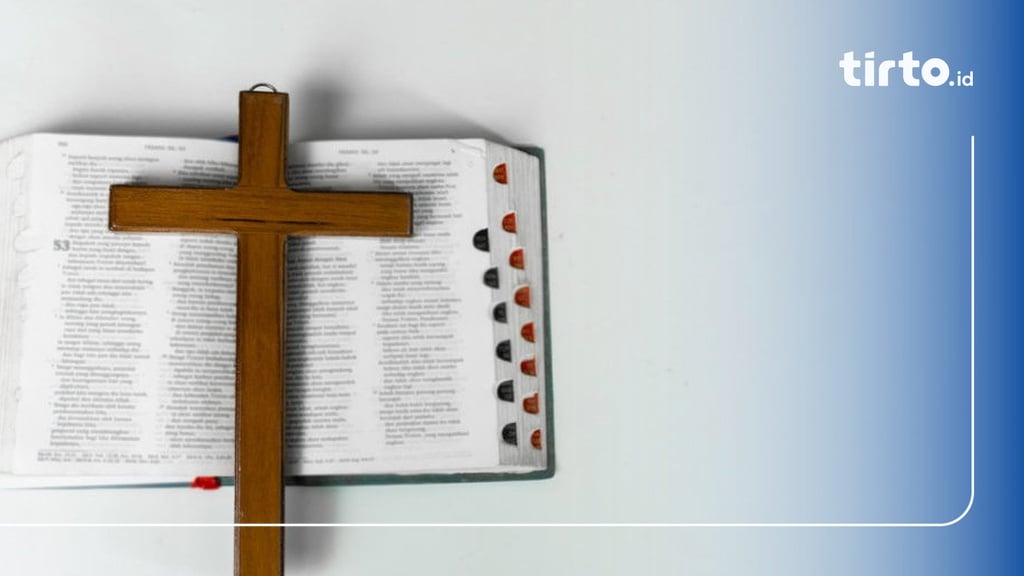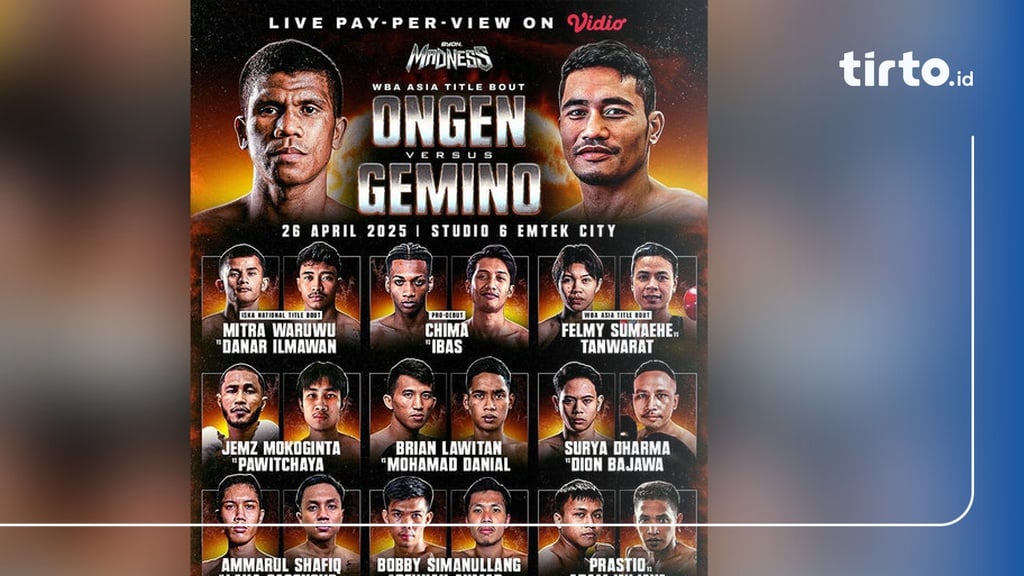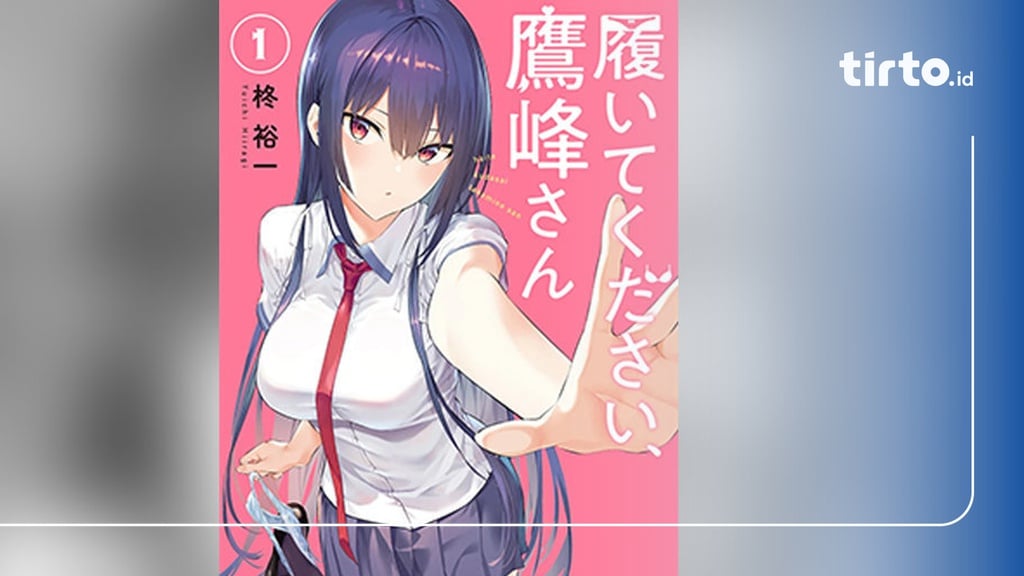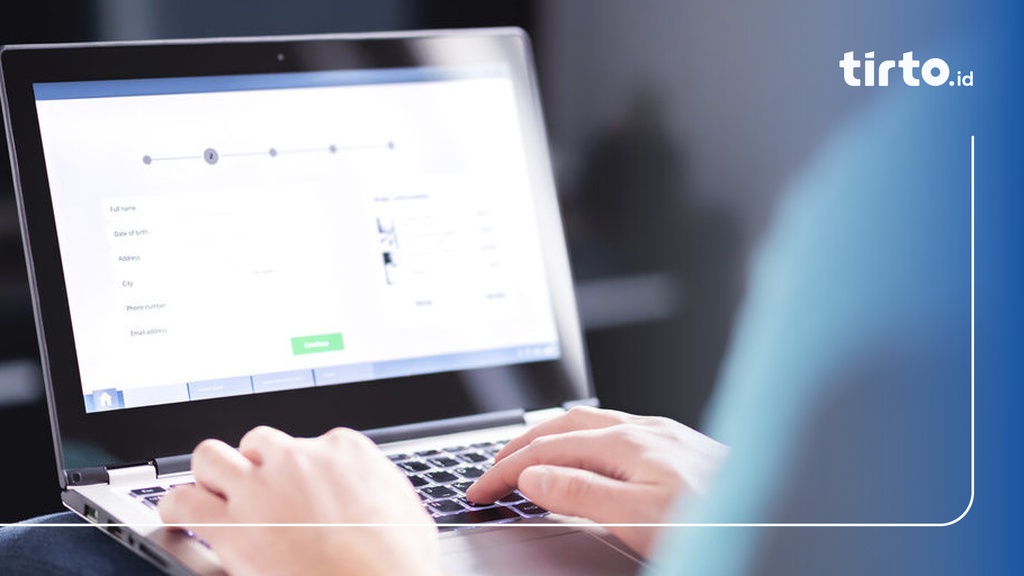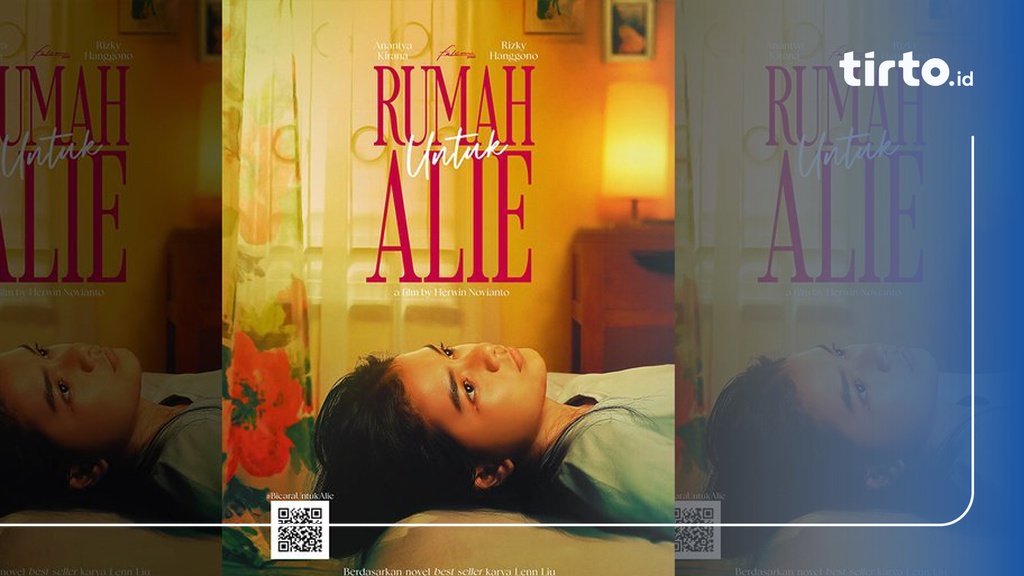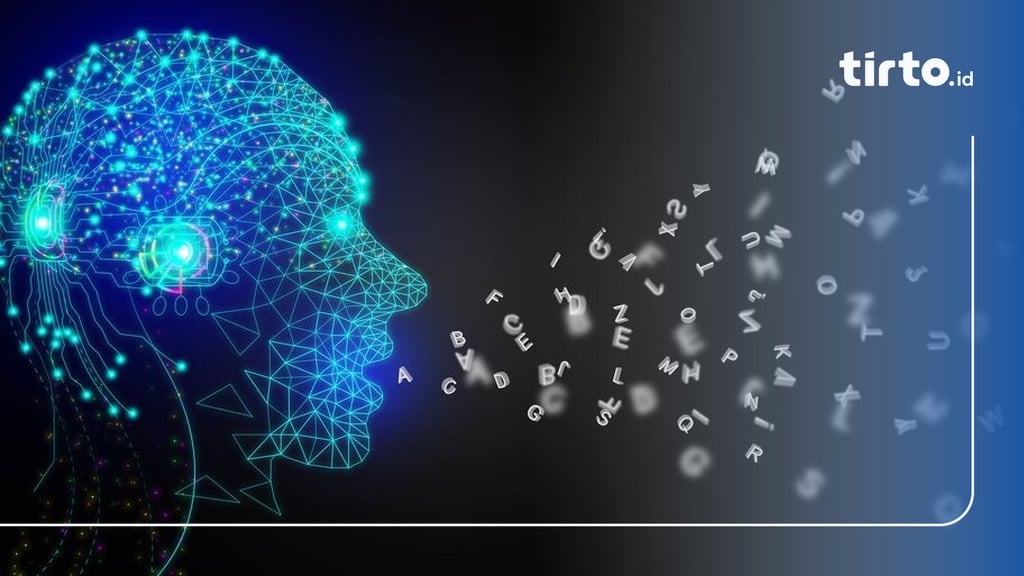tirto.id - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, kata "pengemis" memiliki arti "orang yang mengemis". Kata dasarnya "kemis", yang berasal dari -cak mis. Sebuah cakapan untuk merujuk hari Kamis.
"Kemis" memiliki dua definisi. Tertulis kemis sebagai nomina, yang berarti "minta". Praktik minta ini berasal dari tradisi yang dilakukan pada hari Kamis.
Sejumlah riwayat mengidentifikasi diksi "pengemis" berakar dari kisahan lokal. Ia semacam warisan budaya yang dimuseumkan ke dalam bentuk kata.
Tradisi Kemisan: Cikal Bakal Kemis
Bentuk kisahan lokal yang merunut kata "kemis" dapat ditelusuri sejak masa Sunan Pakubuwono X memimpin Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Pada tanggal 25 Januari 1855, sebuah surat kabar berbahasa Jawa pertama di Hindia Belanda pertama kali memublikasikan wartanya. Namanya Bromartani, surat kabar mingguan yang terbit saban hari Kamis (seminggu sekali).
Surat kabar ini cukup khas dan unik. Di setiap penulisan wartanya, kromo inggil digunakan sebagai bahasa utama. Bahasa ini merupakan tingkatan tertinggi dalam strata bahasa di kebudayaan Jawa.
Salah satu penulis yang rajin mengirim naskahnya ke Bromartini ialah pujangga kesunanan, yakni Ronggowarsito.
Skripsi Resianita Carlina yang berjudul "Berpangku pada Raja: Pengemis dalam Narasi Sedekah Paku Buwono X Tahun 1893-1939" (2020) menyebut bahwa kata "kemis" pertama kali muncul di koran Bromartani pada 1895. Istilah ini digunakan oleh Raden Samingoen Nitiprodjo, wartawan Bromartani yang gemar meliput kebiasaan-kebiasaan Sunan Pakubuwono X.
Dalam laporannya, sunan disebut kerap keluar dari Sasana Sewaka waktu Kamis sore untuk bersiap mengaji. Maklum, di masa tersebut, pengajian pada Kamis malam Jumat selalu menjadi agenda rutinan yang acap kali dilakukan oleh umat Islam.
Sunan terbiasa mengaji Kamis malam Jumat di Masjid Gede Solo. Ia sering terlihat berjalan kaki dari keraton menuju masjid. Tak pernah sendiri, bersamanya mengiringi para penggawa kesunanan seperti abdi dalem dan para pejabat bupati.
Tetapi yang unik, Raden Samingoen Nitiprodjo melaporkan bahwa rakyat sering mengerubungi sunan yang sedang berjalan kaki. Mereka berjongkok, membentuk barisan dan mengantre mendapat ciuman "salam" dari tangan Sang Sunan.
Untuk membalasnya, sunan memerintahkan para penggawa membagikan uang kepengan kepada mereka. Selain bersedekah, hal ini juga dimaknai sebagai wujud terima kasih.
Sedekah pembagian uang kepengan ini disebut sebagai sinuwun. Namun Raden Samingoen Nitiprodjo justru menyebutnya sebagai kemisan. Sebabnya, sinuwun telah bermetamorfosis menjadi kebiasaan yang selalu ditunggu-tunggu rakyat saban hari Kamis, khususnya sewaktu sunan berjalan kaki menuju Masjid Gede Solo tempat melangsungkan pengajian.
 Ilustrasi Pengemis. foto/istockphoto
Ilustrasi Pengemis. foto/istockphoto
Orang-orang yang mendapat pembagian uang kepengan disebut pengemis, sementara yang dilakukannya ialah ngemis.
Tujuan mulanya sebenarnya bukan untuk mencari harta atau derma. Tetapi semata-mata untuk ngalap (mencari) berkah dari sunan. Sosok yang dianggap mulia, diagungkan, dan berkarisma tinggi.
Sejak pemberitaan itu, kemisan menjadi semakin populer. Ia menjadi tradisi rutinan yang dilakukan oleh sunan untuk menyalurkan wujud terima kasihnya kepada pengabdian rakyat.
Selain dari pewartaan surat kabar, kemisan juga turut termuat dalam kitab pujangga kesunanan.
Serat Karangron jilid 3, halaman 24, pupuh ke-32 Asmarandana, tembang ke 18-19 adalah rujukan selanjutnya. Serat itu mengisahkan kebiasaan sunan saban hari Kamis siang. Biasanya, sunan akan keluar dari Sasana Sewaka, lalu berkeliling kompleks keraton. Tak hanya berkeliling, sunan juga menyebarkan uang sen, yang disebut udhik-udhik di sepanjang jalan.
Semua warga berebut derma. Tak hanya warga di sekitar keraton, tetapi turut pula orang-orang yang tinggal di perkampungan atau yang bermukim di pinggir jalan raya.
Setiap mendengar derap bunyi kereta datang, warga senang mengira sunan juga turut di dalamnya. Orang-orang akan keluar dari rumahnya lantas berjongkok di pinggir jalan. Mereka membawa obor yang diacung-acungkan, menantikan uang disebar.
Pergeseran Makna
Lambat laun, kemisan berubah seiring kebiasaan sunan berderma. Bentuk pembagian uang kepengan sinuwun juga mengalami perkembangan.
Tidak hanya saban Kamis, kemisan—yang dimaknai sebagai sedekah sunan—juga berlangsung saat upacara besar macam grebeg, kirab budaya, dan acara lainnya. Dari sinilah kebiasaan sunan yang gemar bersedekah disebut sebagai kemisan. Sementara orang-orang yang mendapat sinuwun dan udhik-udhik disebut pengemis.
Saat Sunan Pakubuwono X memimpin Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pengemis dipelihara oleh negara. Ia adalah simbol filantropis kebudayaan yang diberdayakan lewat tradisi dan upacara adat kesunanan.
Praktik kemis saat masa Pakubuwono X tentu berbeda dengan masa sekarang. Sebabnya, diksi yang berarti meminta itu mengalami pergeseran makna dari pengertian mulanya. Ia tak bisa dimaknai tunggal sebagaimana KBBI merumuskan.
Orang-orang tak lagi tulus ngalap berkah sebagaimana makna awal kemisan. Tetapi sebaliknya, kini justru seolah dengan sadar meminta-minta kepada orang lain. Bahkan, beberapa orang menganggap mengemis sebagai profesi.
 Ilustrasi Pengemis. foto/istockphoto
Ilustrasi Pengemis. foto/istockphoto
Resianita Carlina dalam "Berpangku pada Raja: Pengemis dalam Narasi Sedekah Paku Buwono X Tahun 1893-1939" (2020) kembali menjelaskan bahwa udhik-udhik sampai kini masih dijalankan, tetapi telah mengalami perubahan. Bukan lagi setiap hari Kamis, tetapi sewaktu perayaan jumenengan (penobatan raja) atau kirab budaya ketika sunan mengitari Solo.
Berbeda dengan zaman Pakubuwono X, kini rakyat tak harus berjejer rapi maupun membawa obor sebagai pengganti menengadahkan tangan. Kiwari, motivasi sinuwun sudah berbeda. Semua orang seakan dibebaskan untuk mengemis. Asal ada yang memberi santunan, para pengemis akan berbondong-bondong mengerumuni.
Pengemis di Kota-Kota
Menurut Hasim As’ari dan Moh. Mudzakir dalam "Pengemis dan Makam: Fenomena Pengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik" (2015), pengemis bisa jadi sebuah komunitas yang memang diorganisasikan untuk mendapatkan penghasilan dari meminta-minta.
Salah satu ruang yang paling umum ialah publik. Karena publik selalu menghadirkan pluralitas dan macam-macam latar belakang kehidupan, memungkinkan cara dan alasan yang digunakan oleh pengemis dapat diterima.
Dalam hal ini, pengemis dianggap sebagai komunitas lantaran motivasinya turun ke jalan didasari atas tujuan mencari nafkah dan memperoleh penghasilan dari hibah orang lain.
Mereka menjadi bagian dari komunitas kota, membaur bersama kehidupan jalanan di kota, tempat sekian juta manusia lainnya menggantungkan hidup. Keberadaannya menjadi salah satu ciri utama kehidupan kota. Karena itu, hampir tidak ada kota tanpa pengemis.
Menurut Halim Purnomo dalam "Spiritualitas dan Perilaku Pengemis di Kota Cirebon" (2017), kebiasaan pengemis dapat dengan mudah dikenali. Mereka cenderung mengemis di sejumlah sudut kota, terutama perempatan jalan raya yang dianggap strategis untuk mengharap pemberian dari para pengendara yang melintas.
Pengemis akan menunjukkan berbagai macam cara agar dapat menarik simpati para calon penghibahnya. Ada yang betul-betul sakit, sakit akut, atau hanya berpura-pura. Di antara yang betul-betul sakit akan cenderung memperlihatkan sakitnya, seperti cacat fisik kaki: putus, mengalami kecelakaan, atau terjangkit penyakit bawaan sedari lahir.
Di Cirebon, pengemis yang berpura-pura sakit sering kali mangkal dan mengemis di perempatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Jalan Kesambi. Mereka kedapatan melipat salah satu kakinya dengan cara ditutupi celana, sehingga membuat kesan cacat sungguhan.
Sementara itu, menurut laporan Choirul Amin dkk. dalam "Analisis Karakteristik dan Mobilitas Pengemis di Kota Salatiga" (2017), terdapat beberapa macam indikator yang dapat menjustifikasi seseorang sebagai pengemis. Di Salatiga, usia tidak menjadi patokan lantaran anak-anak sampai lansia kerap ditemukan mengemis di jalan. Biasanya, mereka akan meminta-minta dari rumah ke rumah (door to door), menyebar di persimpangan jalan (lampu lalu lintas), di pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
Selain berpura-pura sakit, di Salatiga sering ditemukan para pengemis menggunakan strategi mendoakan para penghibahnya dengan lantunan bacaan ayat suci. Biasanya, mereka juga menggunakan kedok sumbangan organisasi tertentu yang mengatasnamakan keagamaan.
Di Palu, Sulawesi Tengah, lain lagi. Terdapat istilah pengemis musiman lantaran mereka hanya beraksi ketika waktu-waktu tertentu. Waktu paling ramai dipilih adalah menjelang Idulfitri. Padatnya lalu lintas mudik menjadi sarana potensial mereka untuk meminta-minta.
Di luar waktu itu, mereka kebanyakan berprofesi sebagai kijang (tukang pikul) di beberapa lokasi tambang emas rakyat. Misalnya di Desa Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
tirto.id - News
Kontributor: Abi Mu'ammar Dzikri
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Irfan Teguh Pribadi

 3 months ago
98
3 months ago
98