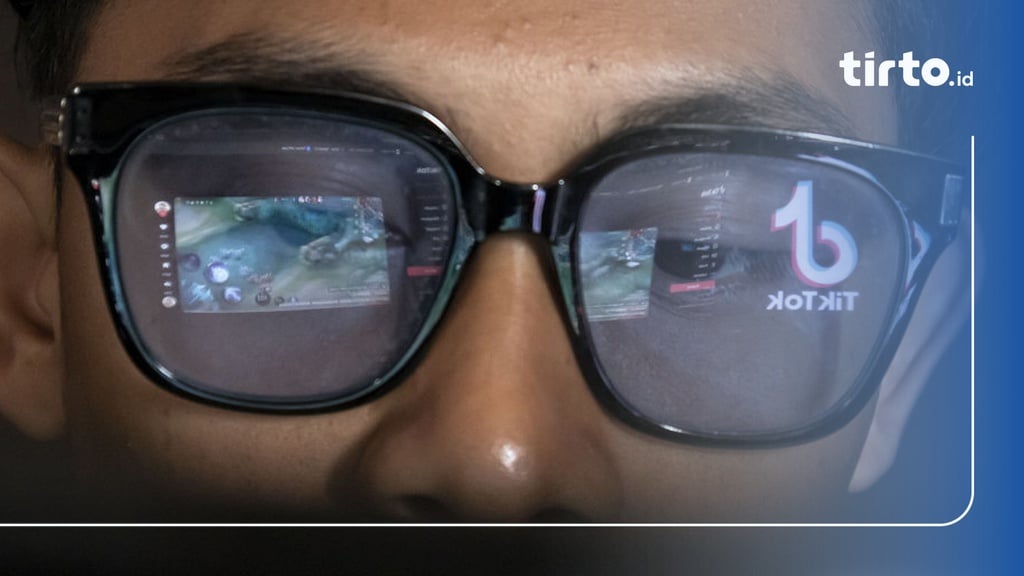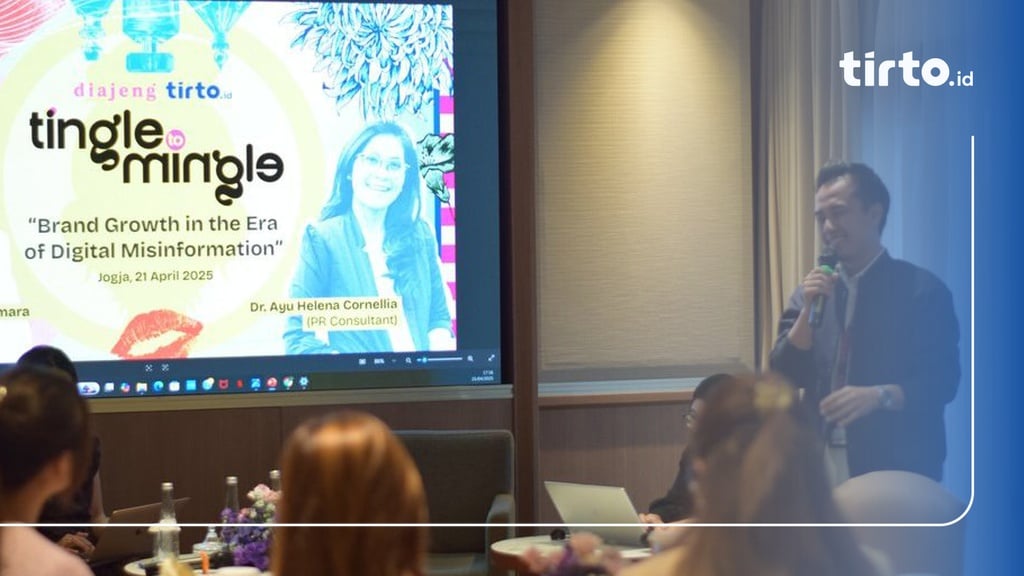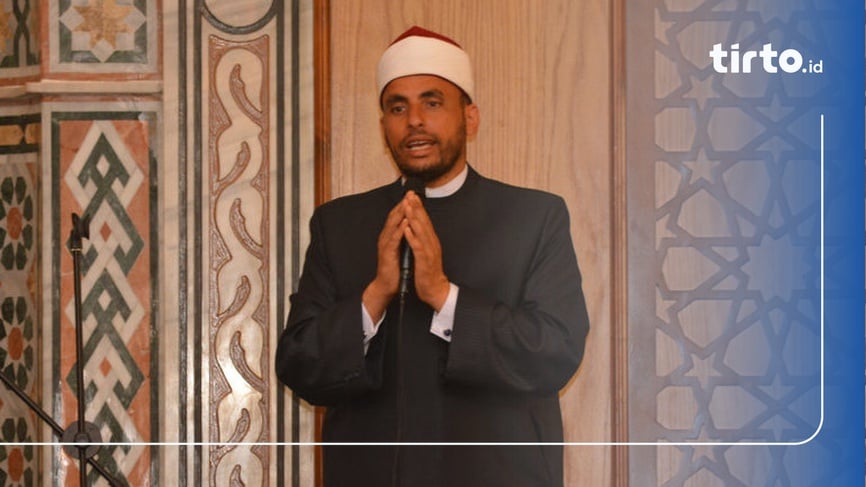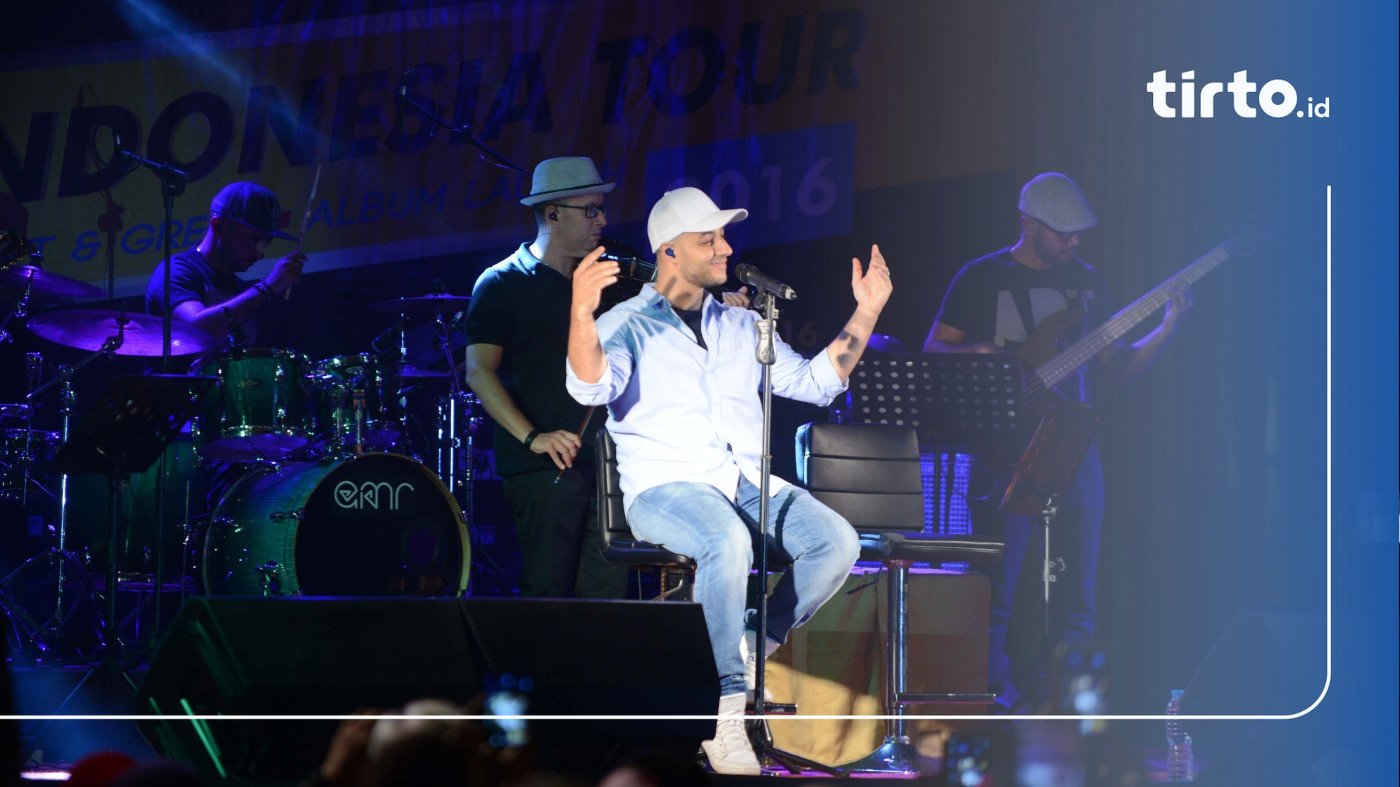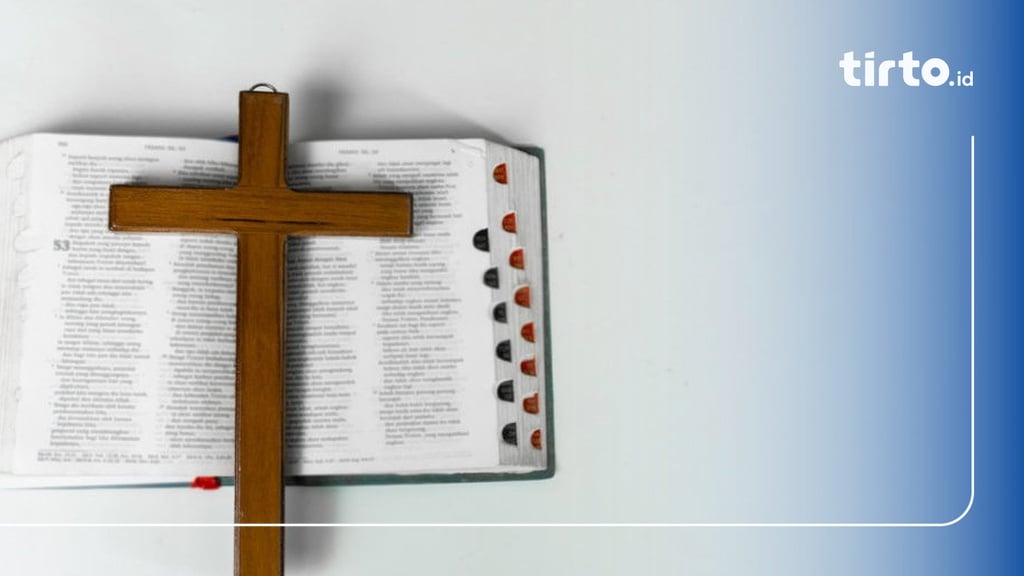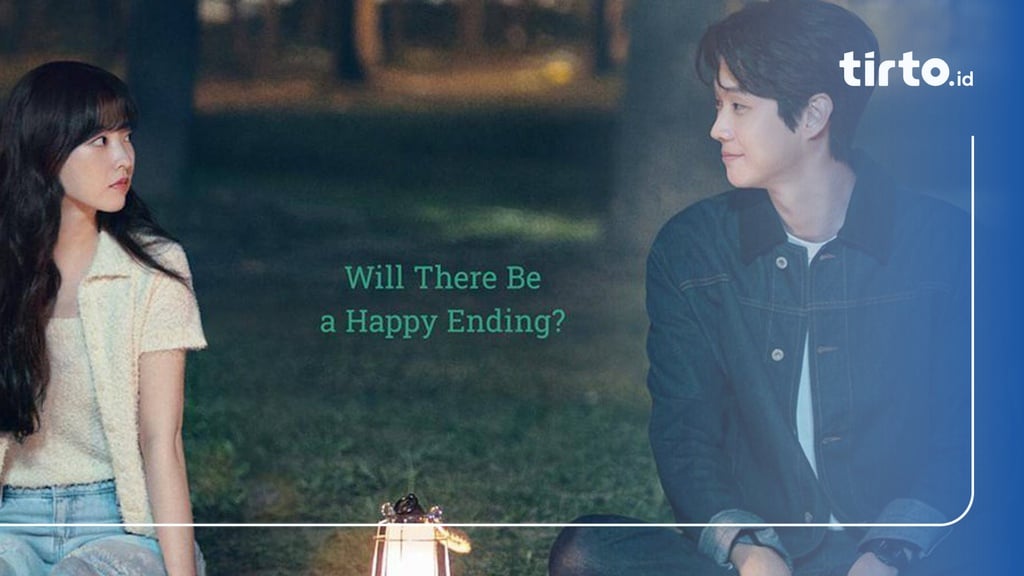tirto.id - DPR RI bakal menyusun formulasi mekanisme baru pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Sekilas, rencana itu memang terdengar menjanjikan. Formulasi mekanisme baru itu akan dibahas pada pertengahan April 2025 ini. Ia pun digadang-gadang mampu memperkuat partisipasi publik dalam proses pembahasan undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ketika dikonfirmasi, menyebut bahwa wacana tersebut memang sedang digodok dan segera dibahas secara detail setelah masa reses.
“Tunggu saja setelah masuk reses,” kata Dasco kepada wartawan Tirto, Senin (7/4/2025).
Dasco belum dapat membeberkan lebih jauh terkait formulasi baru pembahasan RUU itu. Namun, kata dia, formulasi baru itu pasti akan lebih menekankan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU.
“Antara lain penguatan partisipasi publik, selebihnya nanti setelah reses akan diformulasikan secara lengkap,” terang Ketua Harian Partai Gerindra itu.
DPR beberapa kali memang dihujani kritik sebab kurang transparan dan kejar tayang dalam membahas sejumlah RUU. Masih hangat di ingatan bagaimana pembahasan revisi UU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup di sebuah hotel mewah di Jakarta. Maka tak mengherankan masyarakat dari berbagai elemen dan daerah mendesak pencabutan UU TNI yang baru.
Bukan Masalah Aturan, tapi Political Will
Tabiat DPR tersebut menafikan peran partisipasi publik bermakna yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).
Namun, bila ditilik secara kritis, upaya tersebut bagai menabur janji di atas pasir. Janji untuk memperkuat partisipasi publik yang bermakna sering berujung sekadar jadi retorika politik belaka. Catatan sejarah menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang–DPR dan Pemerintah Indonesia–sering kali menjalankan proses legislasi yang minim partisipasi publik, tidak transparan, dan kejar tayang.
Dalam negara demokrasi, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam pembentukan regulasi. Perannya krusial agar undang-undang yang terbit tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik, tetapi juga datang dari aspirasi masyarakat luas.
Proses legislasi di Indonesia sejak lama terinternalisasi dalam budaya politik yang bersifat top-down, keputusan-keputusan penting banyak diambil di balik pintu tertutup dan tanpa melibatkan masyarakat secara maksimal.
Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, memandang bahwa proses partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia memang belum ideal. Masalah ini pun bukan semata-mata disebabkan aturan yang kurang tegas atau belum memadai. Pasal 96 UU P3 sebenarnya sudah mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam setiap tahap pembentukan UU.
Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan UU. Jadi, kata Arif, kerangka hukum yang menegaskan partisipasi publik sebetulnya sudah ada. Namun, implementasinya lebih sering meleset.
“Sering kali, proses konsultasi publik hanya jadi formalitas—dilaksanakan sekadar untuk memenuhi syarat, bukan benar-benar mendengar aspirasi,” kata Arif kepada wartawan Tirto, Selasa (8/4/2025).
Proses partisipasi publik yang ideal semestinya berjalan inklusif, transparan, dan substantif. Arif menjelaskan bahwa masyarakat dari berbagai elemen, seperti kelompok marginal, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal, perlu dilibatkan sejak awal.
Mereka mestinya tak cuma diundang berunding saat pembahasan rancangan UU hampir rampung. Selanjutnya, mekanisme partisipasi publik harus jelas dan terbuka. Misalnya, melalui forum publik, seminar, atau platform digital yang mudah diakses, dan dengan undangan dan jadwal yang diumumkan jauh-jauh hari.
Terpenting, masukan dari masyarakat harus benar-benar dipertimbangkan dan direfleksikan dalam draf UU. Masalnya, selama ini, masukan dari masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) cenderung hanya digubris sambil lalu dan dilupakan.
Menurut Arif, partisipasi bermakna dapat dimulai dengan memastikan DPR dan Pemerintah Indonesia tidak hanya mengundang masyarakat datang berunding, tapi juga menjelaskan bagaimana masukan publik dapat memengaruhi keputusan akhir dalam pembahasan UU.
“Jadi, ini lebih ke soal tabiat dan political will ketimbang kekurangan aturan,” terang Arif.
Sementara itu, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, berpendapat bahwa usulan formulasi baru proses pembahasan RUU yang diwacanakan DPR amat membingungkan sekaligus mengkhawatirkan.
Kalau gagasan itu muncul sebagai respons atas kritik publik terkait proses pembahasan UU TNI, DPR seolah mengatakan bahwa persoalan minimnya partisipasi publik adalah kesalahan aturan yang sudah ada. Dengan kata lain, hal itu dibuat seakan-akan bukan salah DPR dan Pemerintah Indonesia sebagai pembentuk undang-undang.
“Dasco tampak mengambinghitamkan aturan [atas] kesalahan yang sesungguhnya disebabkan DPR dan pemerintah yang cenderung mengabaikan aturan terkait mekanisme legislasi,” ucap Lucius kepada wartawan Tirto, Senin.
Faktanya, kata Lucius, aturan terkait proses legislasi sesungguhnya sudah dua kali diubah, yakni dari UU Nomor 12/2011 hingga menjadi UU Nomor 13/2022.
Dalam regulasi tata cara pembentukan peraturan perundangan-undangan, sudah ada beberapa aturan terkait mekanisme pelibatan publik. Mulai dari ketersediaan informasi, ketersediaan draf, sosialisasi draf, naskah akademik, RDP, hingga RDPU. Dengan demikian, kata Lucius, DPR salah paham atau tak paham masalah saat mengusulkan perubahan mekanisme legislasi untuk menjawab kritikan publik.
Alih-alih membenahi persoalan partisipasi publik dalam proses legislasi, ide formulasi baru pembahasan RUU itu justru dikhawatirkan akan menghasilkan mekanisme yang semakin membatasi ruang partisipasi publik.
“Kalau pembentukan legislasi dikritik karena minim partisipasi, jelas bukan karena aturannya tak tersedia. Masalahnya ada pada DPR yang memilih untuk mengangkangi aturan-aturan itu demi memuluskan niat atau kepentingan politik,” tegas Lucius.
Formulasi Anyar Tetap Perlu Pendapat Publik
Partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia kerap kali cuma bersifat formalitas. Konsultasi publik sering kali diadakan pada tahap-tahap awal tanpa jaminan bahwa masukan publik akan ditindaklanjuti atau dipertimbangkan secara serius.
Jika dibandingkan dengan negara dengan tradisi demokrasi yang lebih mumpuni, Indonesia masih kekurangan portal partisipasi publik yang terintegrasi—baik secara luring melalui forum tatap muka maupun secara daring melalui portal semacam e-governance. Tanpa portal dan akses memadai, partisipasi publik juga cenderung terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja.
Di Inggris, misalnya, pemangku kebijakan memodernisasi proses pembentukan UU melalui mekanisme konsultasi pralegislatif yang melibatkan masyarakat. Mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh UK Cabinet Office, sebelum rancangan UU diintroduksi secara resmi, drafnya didiskusikan melalui konsultasi terbuka.
Konsultasi tersebut sering kali dilakukan dalam bentuk publikasi draf undang-undang yang disertai dengan kesempatan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan masukan melalui platform daring.
Di Finlandia, sejak Maret 2012, pemerintahnya telah mengimplementasikan mekanisme citizens’ initiative (kansalaisaloite). Dengan kebijakan itu, warga negara yang memenuhi syarat dapat mengajukan inisiatif secara langsung kepada parlemen. Inisiatif tersebut mesti mendapatkan 50.000 tanda tangan dalam waktu enam bulan agar dipertimbangkan oleh parlemen. Sistem ini pun dikawal oleh menteri bidang peradilan.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) turut mengembangkan mekanisme partisipasi daring melalui portal seperti Regulations.gov. Melalui portal tersebut, setiap warga dapat mengakses, mengomentari, dan memberikan saran terkait peraturan yang akan diundangkan.
Sistem ini memberikan bukti bahwa partisipasi publik dapat berjalan lebih bermakna bila didukung oleh infrastruktur digital yang memadai dan komitmen untuk transparansi di setiap tahap proses legislasi.
Permasalahan utama di Indonesia terletak pada kesiapan legislator melepaskan kekuasaan penuhnya terhadap partisipasi publik. Birokrasi yang rumit dan politisasi di legislatif berimbas pada sempitnya ruang keterbukaan. Kemudian, hal itu menjadikan langkah reformasi pembahasan undang-undang sering kali terhambat.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, menilai bahwa formulasi baru yang diwacanakan DPR tetap harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Idealnya, tak ada dalih DPR dan Pemerintah RI untuk tidak melakukan partisipasi publik karena hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU P3.
Meskipun prosedur pelibatan publik dalam pembahasan RUU itu ada dalam Tata Tertib DPR, Fajri menilai ketentuannya belum rinci dan belum memiliki konsekuensi bagi pelanggaran syarat dan prosedur. Malah, yang terjadi adalah ruang partisipasi selalu dikorbankan dengan alasan keterbatasan dan efisiensi waktu pembahasan RUU.
“Bahkan Putusan MK 91/2020 terkait dengan uji formil UU Cipta Kerja yang secara tegas menyatakan bahwa pembahasannya tidak melaksanakan partisipasi yang bermakna, seolah tidak berdampak apa-apa kepada penguatan partisipasi publik,” ujar Fajri kepada wartawan Tirto, Selasa (8/4/2025).
Dalam Putusan MK Nomor 91/2020, sudah diberikan tiga prasyarat sebuah partisipasi yang bermakna, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) mestinya diterapkan dalam bentuk akses atas informasi yang seluas-luasnya terhadap pembahasan suatu RUU. Dalam hal ini, transparansi harus dilakukan dengan menyebarluaskan draf RUU dan naskah akademik (NA) secara resmi.
Rapat pembahasan RUU pun harus diselenggarakan secara terbuka dan dapat diakses publik. Setelah syarat transparansi dipenuhi, publik diharapkan dapat memberikan masukan melalui beragam sarana, termasuk secara konvensional dengan menghubungi anggota DPR secara langsung atau bersurat kepada DPR melalui website DPR, melalui media sosial, atau melalui berbagai kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPR.
Sementara itu, hak dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang sudah masuk harus secara sistematis dalam suatu forum resmi, tidak sekadar dicatat dan kabur nasibnya.
Hingga saat ini, ungkap Fajri, DPR dan Presiden RI belum pernah memublikasikan catatan masukan-masukan publik yang sudah masuk saat proses pembahasan RUU.
Selanjutnya, hak mendapatkan penjelasan atau jawaban dari pendapat yang diberikan (right to be explained) haruslah dibuat dialogis. Sehingga, publik bisa mengetahui apa yang sudah diterima atau tidak diterima dari pendapatnya. Prasyarat inilah yang mampu membuat ruang partisipasi, bukan hanya sekadar mengundang masyarakat dalam suatu forum rapat terbuka.
Justru, forum pertemuan baru langkah awal dari serangkaian upaya melibatkan publik dalam pembahasan suatu UU.
“Dalam praktiknya, masing-masing prasyarat itu tidak pernah dijalankan secara maksimal sampai hari ini,” tandas Fajri.
tirto.id - News
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi

 2 months ago
59
2 months ago
59