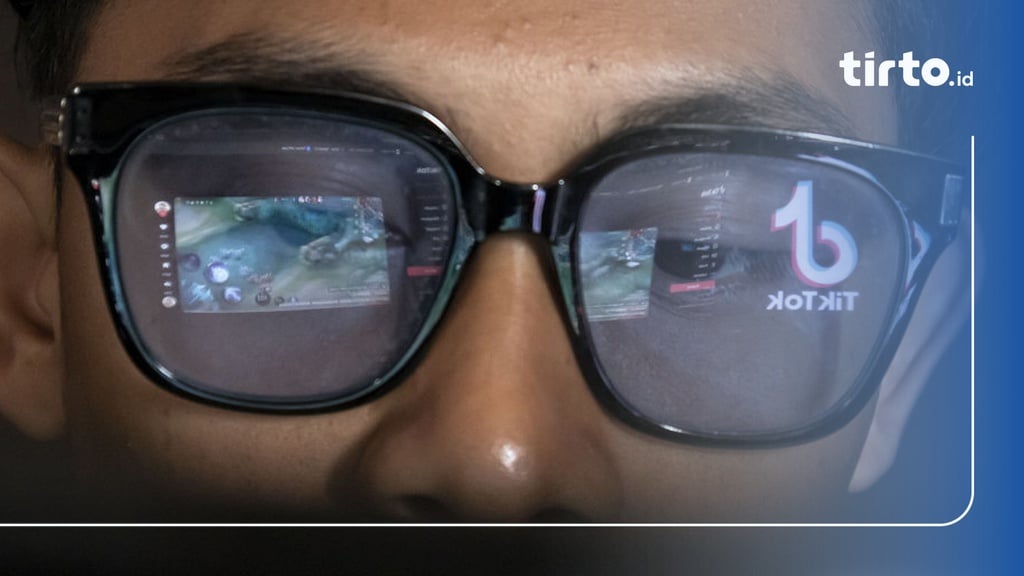tirto.id - Kendati tidak sepopuler di beberapa negara lain, minuman beralkohol bukanlah sesuatu yang asing di Indonesia. Beberapa budaya lokal pun melibatkan minuman beralkohol. Sebut saja tuak di antara masyarakat Batak dan arak yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan di Bali. Meski begitu, ini tidak serta-merta menghilangkan stigma terhadap minuman beralkohol yang, sayangnya, turut melanggengkan stereotip negatif terhadap orang yang mengalami alkoholisme.
Alkoholisme kerap dianggap sebagai bentuk kelemahan moral atau kurangnya kendali diri. Kecanduan alkohol dianggap hanya dialami orang yang "nakal", tidak bertanggung jawab, kurang berpendidikan, atau kerap melakukan kejahatan. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa kecanduan alkohol dapat disembuhkan hanya dengan kemauan untuk berhenti minum.
Faktanya, alkoholisme bukan sekadar akibat dari terlalu banyak minum alkohol. Ini adalah masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor genetik, psikologis, hingga sosial dan lingkungan. Sayangnya, stigma masih menjadi dinding yang menghalangi mereka dari bantuan.
Untuk memahami alkoholisme dengan lebih adil, kita perlu membongkar stigma yang telah lama mengaburkan fakta medis dan realitas sosial di balik kondisi ini.
Alkoholisme dari Perspektif Medis
Alkoholisme adalah istilah awam untuk gangguan penggunaan alkohol (alcohol use disorder/AUD). National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) mendefinisikan gangguan penggunaan alkohol sebagai suatu kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk berhenti atau mengendalikan konsumsi alkohol meskipun berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, pekerjaan, atau kesehatan. Kondisi ini juga dikenal sebagai kecanduan alkohol.
Mengacu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), seseorang bisa dikatakan mengalami alkoholisme jika mengalami sejumlah gejala selama setahun terakhir.
Jika seseorang mengonsumsi alkohol lebih banyak dari biasanya, gagal menguranginya meski sudah mencoba, serta telah beroleh efek samping, ia tergolong alkoholisme ringan.
Namun, apabila kecanduannya sudah lebih parah hingga tidak bisa memikirkan hal lain dan dampaknya sudah merembet ke kehidupan sehari-hari, alkoholisme seseorang tersebut sudah mencapai taraf sedang.
Indikatornya telah sampai pada level parah jika seseorang keukeuh minum alkohol meski kesehariannya terdampak, lebih mementingkan alkohol dibanding hal lain, berkali-kali cedera akibat mabuk, konsumsinya meningkat kendati dampaknya sudah merambah ke aspek psikologis, serta sudah mengalami gejala mirip sakau (withdrawal syndrome).
Masalahnya, orang-orang sekitar kerap kali melabelinya sebagai sampah masyarakat yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Padahal, sejak 1956, American Medical Association (AMA) telah menyatakan bahwa alkoholisme merupakan penyakit medis yang kompleks, dan sukar diatasi hanya dengan bermodal kemauan untuk berhenti. Ini didukung oleh American Society of Addiction Medicine (ASAM), yang bergabung dengan AMA pada 2011 dan mendefinisikan adiksi atau kecanduan sebagai masalah otak kronis alih-alih masalah perilaku.
Kesimpulan itu berlandaskan pada sifat dasar alkohol sebagai depresan yang dapat mengganggu keseimbangan neurotransmiter di dalam otak. Zat ini merangsang pelepasan dopamin yang menimbulkan rasa bahagia dan menumpulkan emosi negatif. Ia juga memengaruhi area otak yang berperan dalam kendali diri. Inilah alasan kita merasa tenang, percaya diri, dan seolah lebih kreatif, setelah meminum alkohol. Padahal, faktanya tidak demikian dan efeknya pun sementara.
NIAAA pun menyebutkan, ketika efek alkohol di dalam tubuh sudah hilang dan seseorang tak lagi mengonsumsinya, dampak yang timbul adalah emosi negatif yang makin kuat. Oleh karena itu, ia akan termotivasi untuk mengonsumsi alkohol lagi untuk mendapatkan efek serupa walaupun telah mengetahui dampak negatifnya.
Makin banyak dan lama seseorang mengonsumsi alkohol, makin buruk dampaknya pada otak. Konsumsi alkohol dalam jangka panjang akan mengubah fungsi dan struktur otak, memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Begitu terjadi ketergantungan terhadap alkohol, orang yang tadinya bisa mengontrol kapan harus berhenti minum, kini kesulitan atau tidak mampu lagi melakukannya. Hal inilah yang akhirnya berkembang menjadi alkoholisme.
Apa yang Membuat Seseorang Rentan Kecanduan Alkohol?
Gangguan penggunaan alkohol bisa terjadi pada siapa pun tanpa memandang status ekonomi, gender, jenis kelamin, maupun lingkungan. Meski begitu, faktor-faktor tersebut memang berperan dalam menentukan seberapa besar risiko seseorang mengalami alkoholisme.
Mayo Clinic dan NIAAA juga telah merumuskan faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami kecanduan.
Paparan alkohol sejak masa remaja dapat memprediksi risiko kecanduan di masa depan. Makin dini seseorang mulai minum alkohol, makin besar risiko kecanduannya. Jika konsumsinya bertahan dalam waktu lama, risiko alkoholisme bakal lebih tinggi.
Riwayat alkoholisme di keluarga juga ikut andil. Risikonya akan meningkat jika ada anggota keluarga yang memiliki masalah serupa, terutama orang tua. Belum lagi faktor sosial dan lingkungan yang pengaruhnya tak kalah besar terhadap kebiasaan seseorang mengonsumsi alkohol.
Risiko penyalahgunaan alkohol juga akan lebih tinggi apabila seseorang punya gangguan mental, seperti depresi, skizofrenia, dan kecemasan. Akan lebih parah risiko apabila seseorang punya trauma di masa lalu.
Pada intinya, tidak ada batasan yang benar-benar aman dalam konsumsi alkohol. Meskipun banyak orang dapat mengonsumsi alkohol tanpa kecanduan, risiko tetaplah ada, terutama bagi mereka yang memiliki faktor-faktor di atas. Bahkan dalam jumlah kecil, konsumsi alkohol bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kemungkinan berkembangnya pola konsumsi yang lebih berisiko.
 Ilustrasi Drunkorexia. foto/istockphoto
Ilustrasi Drunkorexia. foto/istockphoto
Stigma yang Membelenggu para Alkoholik
Meski AMA telah lama menyatakan alkoholisme sebagai penyakit, tidak bisa dimungkiri bahwa tidak semua orang setuju akan hal ini. Karena mekanismenya tidak seperti flu yang disebabkan oleh virus atau kanker yang berawal dari mutasi genetik, masalah alkoholisme masih kerap dianggap sebagai konsekuensi dari penggunaan alkohol yang tidak bertanggung jawab alih-alih masalah kesehatan.
Berbeda dengan narkotika yang penggunaannya berkonsekuensi hukum, alkohol adalah barang legal. Minuman ini dapat diakses dengan cukup mudah di warung-warung tertentu di pinggiran jalan, toko minuman beralkohol di mal-mal, hingga restoran mewah yang menyajikan koleksi wine dan liquor seharga jutaan rupiah.
Minuman beralkohol juga memiliki posisi tersendiri dalam kehidupan sosial. Minuman ini identik dengan relaksasi, kreativitas, serta menjadi simbol kesenangan dan perayaan, baik bagi anak-anak muda maupun orang tua. Bahkan, ada istilah social drinker, yaitu orang yang mengonsumsi alkohol hanya dalam situasi sosial, misalnya saat berkumpul dengan kawan-kawan atau merayakan pencapaian di tempat kerja.
Hal-hal tersebut membuat konsumsi alkohol tampak seperti pilihan pribadi semata, berbeda dengan saat kita terinfeksi virus penyebab flu. Tanpa kesadaran bahwa alkoholisme merupakan masalah kesehatan yang kompleks, ditambah berbagai stereotip tentang peminum alkohol, tak heran jika stigma terhadap orang yang mengalami alkoholisme masih begitu kuat.
Bagaimanapun bentuknya, stigma tetap berpotensi memperburuk kondisi penderita. Seturut laporan NIAAA, alasan banyak orang enggan mencari pengobatan juga berkaitan dengan stigma. Mereka terlalu malu menceritakannya kepada orang lain, merasa harus bisa berhenti sendiri, dan takut orang lain memberikan pendapat negatif.
Pasien kecanduan alkohol menganggap kondisi dan pengobatannya sebagai sesuatu yang memalukan atau sebuah kegagalan. Rasa takut akan dihakimi membuat mereka sangat khawatir akan penampilannya. Karena tidak ada jalan lain untuk mengatasi perasaan negatif ini, beberapa orang justru kembali mengonsumsi alkohol untuk mengalihkan diri.
Alkoholisme juga sering kali dianggap sebagai bagian dari identitas pasien. Kita bahkan punya istilah alkoholik untuk orang yang mengalami gangguan penggunaan alkohol. Jauh lebih mudah untuk menyebut bahwa Si X adalah alkoholik atau pecandu alkohol alih-alih orang yang menjalani pengobatan gangguan penggunaan alkohol.
Tak kalah penting, pengobatan untuk gangguan penggunaan alkohol melibatkan proses rehabilitasi yang panjang. Pasien perlu menjalani detoksifikasi dan menghadapi kemungkinan gejala putus alkohol, melewati beberapa kali sesi konseling yang melibatkan topik-topik yang membuatnya malu atau tidak nyaman, serta mengonsumsi obat-obatan dengan efek samping tertentu. Dukungan penuh dari keluarga, orang-orang terdekat, dan lingkungan, sangatlah penting untuk mendukung keberhasilannya.
Pengobatan dan Pemulihan dari Alkoholisme
Sembuh dari gangguan penggunaan alkohol memang tidak mudah, tetapi juga bukan hal mustahil. Pengobatannya mungkin berbeda-beda bergantung pada tingkat keparahan dan kebutuhan pasien. Prosesnya dapat melibatkan pendekatan medis, psikologis, sosial, hingga spiritual.
Tahap pertama rehabilitasi adalah detoksifikasi selama 2–7 hari yang bertujuan membersihkan tubuh dari sisa-sisa efek alkohol. Pada tahap ini, pasien mungkin akan mengalami berbagai gejala putus alkohol, seperti kegelisahan, gemetar, sakit kepala, berkeringat, hilangnya nafsu makan, bahkan mungkin depresi.
Setelah detoksifikasi rampung, pasien akan menjalani konseling dan terapi rehabilitasi untuk mempelajari keterampilan dan kontrol diri, mengatasi masalah emosional yang memicu kebiasaan minum alkohol, dan membentuk perilaku baru. Terapi dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun melibatkan keluarga.
Jika perlu, dokter juga bisa memberikan obat-obatan, seperti disulfiram, naltrexone, dan acamprosate. Disulfiram tidak secara langsung menghilangkan keinginan minum alkohol. Obat ini menimbulkan reaksi negatif seperti mual, muntah, dan sakit kepala, jika diminum bersama alkohol. Sementara itu, naltrexone dan acamprosate bekerja dengan mengurangi dorongan untuk minum alkohol.
Seperti halnya penyakit medis lainnya, peran keluarga, komunitas, dan lingkungan, sangat penting. Pasien dapat mengikuti program pemulihan seperti Alcoholics Anonymous (AA) atau komunitas serupa. Keluarga bisa ikut andil menyediakan lingkungan positif agar pasien mampu menghadapi tantangan setelah rehabilitasi. Jika diperlukan, pasien juga dapat mengikuti konseling berkelanjutan.
Alkoholisme bukanlah sekadar kebiasaan buruk atau cerminan dari kelemahan moral, melainkan gangguan kesehatan yang nyata. Sayangnya, stigma yang melekat pada kecanduan alkohol justru membuat banyak penderita enggan mencari bantuan karena takut dihakimi.
Membangun kesadaran bahwa alkoholisme adalah masalah kesehatan, bukan sekadar pilihan gaya hidup, menjadi langkah penting untuk menghapus stigma. Dengan begitu, akses bagi penderita untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan akan terbuka lebih luas.
tirto.id - Kesehatan
Kontributor: Diah Ayu Lestari
Penulis: Diah Ayu Lestari
Editor: Fadli Nasrudin

 2 months ago
79
2 months ago
79