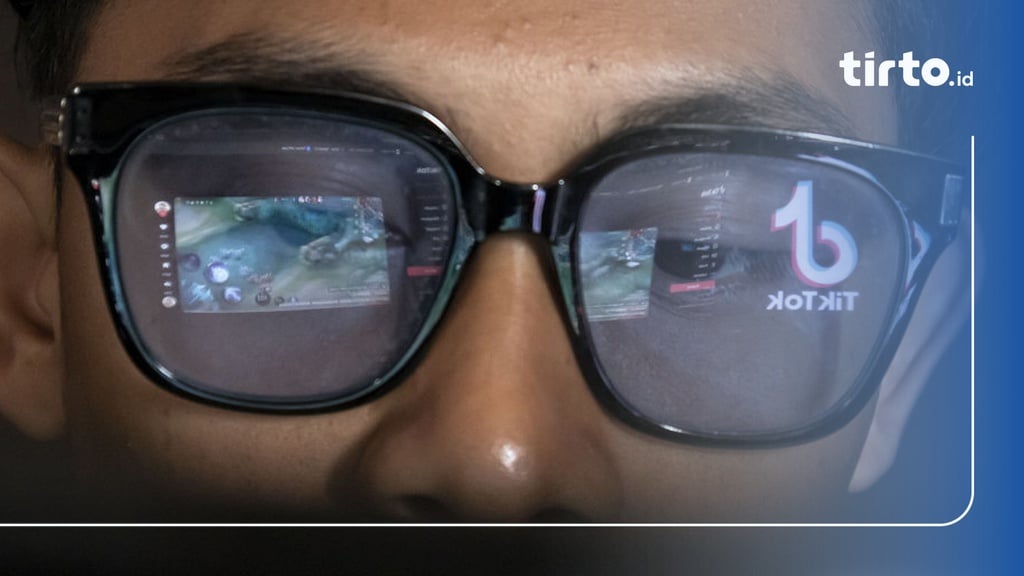tirto.id - Jika terdapat hamba sahaya, pembantu, atau siapa jua perempuan bersuami, tengah bepergian menggunakan perahu, lalu kedapatan bertindak asusila seksual, bahkan si penambang sekalipun akan dianggap bersalah dan wajib dihukum. Dia bisa dicap melakukan astacorah, delapan kejahatan yang berhubungan dengan pencurian.
Begitulah hukum yang berlaku di Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Mereka membikin aturan pergaulan ketat di hampir setiap lini, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual.
Akan halnya penambang perahu, tidak diperbolehkan menyentuh bahkan menegur penumpang perempuan, kecuali dalam kondisi tertentu dan terpaksa. Misalnya, dalam insiden perahu tenggelam, si penambang memang diharuskan membantu mengangkat serta membopong penumpangnya. Dalam hal itu, dia tidak dianggap berdosa. Namun, jika melanggar batas, mereka bisa dikenai sanksi melakukan strisanggrahana, tindak asusila melecehkan perempuan.
Hukum tersebut tertulis dalam Prasasti Canggu atau Trowulan I, berangka 1280 Saka atau 7 Juli 1358 M, yang dikeluarkan semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Ahli kesusastraan Jawa dari Belanda, Theodor Pigeaud, dalam Jawa in the Fourteenth Century (1960), menyebut bahwa prasasti ini memang berkenaan dengan aturan dalam aktivitas penambangan. Total terdapat 10 lempeng tembaga, dan yang mengatur strisanggrahana tertulis di lempeng IX.
Perkara Perempuan dalam Hubungan dan Seksualitas
Bukan hanya hal-hal umum yang diregulasikan untuk mencegah tindak asusila seksual. Majapahit sudah memproklamasikan hukum yang rinci, lugas, dan tandas.
Ada teks hukum yang mengatur ketentuan ini, disebut Kutaramanawa. Menurut Johann Christoph Gerhard Jonker dalam disertasinya, Een Oud-Javaansch Wetboek vergeleken met Indische Rechtsbronnen (1885), teks ini tergolong sebagai Manawadharmasastra atau Kitab Perundang-undangan Agama. Di dalamnya memuat pelbagai pasal yang diambil dari inti sari hukum Hindu.
Jumlahnya cukup banyak, sekira 275 pasal. Akan tetapi, menurut Slamet Mulyana lewat Perundang-undangan Majapahit (1967), terdapat penulisan pasal yang rangkap dan satu pasal dinyatakan sudah rusak, sehingga yang dipakai berjumlah 272 pasal.
Kitab itu memuat 19 bab. Tiga di antaranya berkaitan dengan peraturan mengenai perempuan: tukon, perkawinan, dan paradara.
Di masa modern, tukon bisa berarti pertunangan atau lamaran. Biasanya berupa sejumlah uang yang dibebankan kepada pihak jejaka sebagai tanda “pengikat” dan menjadi hak pihak gadis. Hukum ini berguna melindungi perempuan dari rangkaian hubungan yang memaksa dan tidak dikehendaki.
Jika perempuan penerima tukon enggan menggauli suaminya ketika sudah menikah—sebab tak menginginkannya—istri wajib mengembalikan besaran tukon sebanyak dua kali lipat. Namanya amadal sanggama.
Apabila si gadis kabur dan kawin dengan laki-laki lain lantaran menaruh cinta padanya, sedangkan bapaknya memilih diam dan bahkan mengawinkannya, semua tukon dari pihak pertama harus dikembalikan dua kali lipat. Tindak ini disebut amarang larangan. Adapun bapak gadis itu disanksi sebesar empat laksa* yang harus dibayarkan kepada raja. Namanya amadal tukon.
Dalam aturan Majapahit, perempuan juga mendapat perlindungan hukum. Apabila bakal suaminya (yang belum bersanggama dengan calon istri) terbukti menderita penyakit seksual yang melarang tidur bersama, seperti impoten atau buduk di perut, paha, bokong, termasuk hal yang tidak tampak dari luar macam ayan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Kepada perempuan, bakal suami wajib memberi tukon dengan besaran yang sama kembali.
Selain itu, apabila jejaka yang memberi tukon tepergok menggauli calon istrinya di luar janji waktu pernikahan, dia sama dengan merampas kehormatan. Hal itu termasuk perbuatan asusila. Pihak perempuan akan dilindungi dan dibebaskan dari beban pengembalian tukon. Sementara itu, pelaku asusila dikenai denda empat laksa. Demikianlah sesuai dengan ajaran Begawan Bharggawa.
Paradara, Larangan yang Diperbuat terhadap Istri Orang
Secara harfiah, paradara berarti istri orang lain. Dalam hal ini, seseorang dilarang main serong terhadapnya. Dalam Kitab Perundang-undangan Agama, besaran denda turut diatur bagi laki-laki yang terciduk mengganggu sampai memerkosa istri orang.
Ketentuan denda atas paradara dirangkum dengan cukup matang oleh Titi Surti Nastiti dalam Perempuan Jawa: Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII—XV (2016). Pelaku pemerkosa istri orang akan dikenakan denda sebesar dua laksa jika korbannya merupakan istri pertama. Apabila korban merupakan perempuan yang berasal dari kalangan menengah, dendanya salaksa. Sementara itu, denda lima tali dikenakan untuk perempuan kalangan bawah.
Denda tersebut dibayar oleh pelaku kepada raja, yang nantinya diberikan kepada suami korban, dengan catatan bahwa suami menghendaki penebusan berupa uang. Namun, bilamana pemerkosa tertangkap basah oleh suami, pelaku boleh dibunuh.
Siapa jua yang membuntuti istri orang lain sampai ke rumahnya, dengan maksud hendak meniduri, bisa dipidana mati oleh raja. Hukum tersebut jjuga berlaku bagi pelaku yang dengan sengaja “menyentuh” perempuan tersebut, lebih-lebih memaksa memeluknya. Bahkan, jika dia ketahuan “tidur” di ranjang istri orang lain, seseorang bisa dikenakan denda dua laksa.
Hukum yang sama juga diatur bagi pihak ketiga yang turut terlibat dalam persekongkolan asusila.
Menurut ketentuan Manawa, seseorang yang menyuruh orang lain untuk meniduri istri orang akan dihukum denda dua laksa. Merujuk pada aturan Kutara, orang yang disuruh bisa saja dihukum mati. Namun, ia juga berkesempatan menebusnya dengan denda empat laksa. Hukuman ini juga berlaku bagi penghasut dan pesuruh pelaku paradara.
Ketentuan yang sama pun berlaku jika pelaku pihak ketiga merupakan seorang perempuan. Apabila ia “menyediakan tempat” berbayar untuk sejoli yang belum menikah, raja menjatuhi denda sebesar 4.000 picis.
Pihak kerajaan juga menetapkan aturan mengenai kemungkinan tindak asusila yang tidak disengaja serta larangan yang diperbuat lantaran belum teredukasi.
Pertama, seseorang bisa dikenai hukuman dua laksa apabila ketahuan meminjam pakaian kepada istri orang lain di tempat sepi.
Kedua, larangan berbicara dengan istri orang lain di tempat sepi, kendati dengan alasan menagih utang atau obrolan lain yang diklaim mendesak dan perlu.
Biarpun begitu, dalam kasus lain, dua hal di atas bisa memiliki kesimpulan hukum yang berbeda. Misalnya, seseorang yang mengobrol bersama istri orang—dengan catatan bukan istri utama (tidak dipingit)—di tempat sepi, bahkan meskipun tidak menaruh maksud bejat untuk “melayani” dirinya, tetap dicap strisanggrahana. Orang tersebut hanya akan didenda lima tali. Jumlah yang cukup sedikit lantaran korban bukan merupakan istri utama dan tidak dipingit. Boleh jadi pula memang pelaku tidak mengetahui bahwa yang diajak berbicara sudah bersuami.
Larangan tersebut berfungsi sebagai upaya preventif, sebab bagaimanapun tindakan itu dapat mengundang nafsu berahi.
Aturan yang dibuat tidak hanya berlaku bagi rakyat biasa, tetapi juga pendeta. Mereka dilarang “menegur” istri orang lain di tempat sepi. Mengacuhkan larangan ini dianggap dapat menghilangkan kependetaannya, sesuai ajaran Sang Hyang Agama.
Laki-laki juga dilarang menghadiahi perempuan yang bersuami dalam bentuk apa pun, khususnya orang kaya atau hamba sahaya bangsawan kerajaan. Meskipun keduanya menyatakan sama-sama suka dan menerima, pemberi hadiah digolongkan sebagai strisanggrahana dan dapat dikenakan pidana mati. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang mengingkari aturan agama dan kesopanan, sehingga patut dihukum lewat undang-undang negara.
Di masa itu, para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Mereka yang terbukti memerkosa gadis, membawa lari korban, menyatakan bualan janji manis, atau memaksa perempuan pergi ke tempat sepi, akan dicap babi. Si babi juga didenda sebesar empat tali oleh raja.
Masyarakat bisa jadi saksi. Ketika korban perempuan melapor dengan cara berteriak dan menangis, yang didengar oleh banyak orang, pelakunya boleh dirajam ramai-ramai.
Selain dihukum mati, sebagai alternatif siksaan, pelaku kekerasan seksual bisa dibikin cacat. Tangan pelaku dipenggal oleh raja, sebagai sebuah pertanda bahwa dia pernah memerkosa istri orang. Masyarakat desanya juga berhak mengusir pelaku dari tempat tinggalnya.
tirto.id - News
Kontributor: Abi Mu'ammar Dzikri
Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri
Editor: Fadli Nasrudin

 1 month ago
54
1 month ago
54