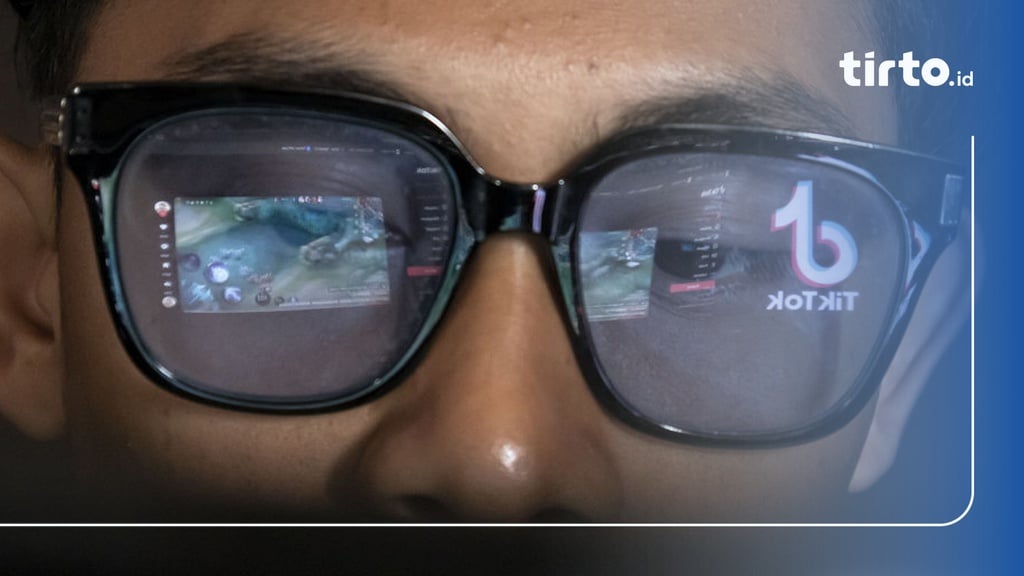tirto.id - Kasus kekerasan seksual di lingkup peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang mencuat belakangan ini menjadi tanda bahaya. Belum reda kasus pemerkosaan oleh Dokter Anestesi PPDS di Bandung, muncul lagi kasus pelecehan seksual dokter kandungan di Garut, Jawa Barat.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah dengan berencana mewajibkan tes kesehatan mental bagi dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Sebagai langkah dini hal ini perlu diapresiasi. Deteksi kondisi kesehatan mental dokter residen diharapkan mampu mencegah gangguan kejiwaan ataupun tindakan yang berpotensi merugikan pasien.
Namun, tes kesehatan mental ataupun deteksi dini gangguan kejiwaan bukan panaséa bagi persoalan PPDS di Indonesia. Terutama, moral dan etika dokter atau tenaga kesehatan kini tengah menjadi sorotan publik imbas kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Kultur dan sistem pendidikan kedokteran juga ikut menjadi topik perbincangan publik.
Diberitakan sebelumnya, seorang dokter anestesi PPDS di RSHS Bandung memerkosa tiga orang korban dengan menggunakan obat bius. Salah satunya keluarga pasien, sementara dua lainnya pasien. Modus pelaku dengan cara memeriksa darah, melakukan analisis untuk anestesi, dan dalih uji alergi terhadap obat bius. Pelaku, Priguna Anugerah Pratama, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dan terancam hukuman belasan tahun penjara dan dicabut izin praktiknya seumur hidup.
Pengamat kebijakan kesehatan sekaligus pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dicky Budiman, menilai tes kesehatan mental sebetulnya langkah awal yang baik tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen pencegahan kasus kekerasan seksual. Dicky menyebutkan, kesehatan mental yang terganggu memang dapat berkontribusi terhadap perilaku tidak etis.
“Namun tindakan amoral seperti kekerasan seksual lebih erat kaitannya dengan masalah integritas, penyimpangan etika, dan kegagalan sistem pengawasan yang profesional,” ucap Dikcy kepada wartawan Tirto, Selasa (15/4/2025).
Tes psikologis atau kondisi kejiwaan hanya mampu mengidentifikasi gejala atau risiko umum seperti depresi, burnout, dan kecenderungan perilaku agresif. Di sisi lain, ujar Dicky, perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual sering kali berkaitan erat dengan faktor kekuasaan, impunitas, dan budaya bungkam dalam suatu institusi.
Dicky merekomendasikan reformasi kurikulum etika kedokteran. Etika medis semestinya tak hanya menjadi teori di awal pendidikan dokter, tetapi mampu diinternalisasi secara konsisten selama masa pendidikan spesialis.
Karena itu, diskusi kasus, refleksi etik, hingga supervisi moral harus dilakukan secara rutin.
 Ilustrasi dokter. FOTO/iStockphoto
Ilustrasi dokter. FOTO/iStockphoto
Selain itu, setiap rumah sakit pendidikan perlu membentuk Komite Etik independen, yang menjamin pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual atau perundungan dapat diakses korban secara aman dan tanpa intimidasi. Budaya saling menutupi atau hierarki yang kaku dalam sistem pendidikan dokter harus diurai.
Ia menambah, evaluasi rekam jejak etik, rekam kelakuan, dan integritas calon peserta PPDS mestinya menjadi bagian dari sistem seleksi. Sebab, masyarakat tidak hanya mencari dokter yang pintar, tapi juga yang berintegritas dan berempati.
Kasus kekerasan seksual oleh peserta PPDS maupun dokter praktek adalah alarm serius yang menunjukkan bahwa selain kecakapan klinis, dimensi etik dan sistem pengawasan pendidikan kedokteran kita perlu lebih diperkuat.
“Jadi, tes kesehatan mental penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah kekerasan seksual jika tidak disertai sistem etik dan pengawasan yang ketat,” tegas Dicky.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan Kemenkes bakal mewajibkan tes kejiwaan bagi peserta PPDS lewat metode MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen, Priguna Anugerah Pratama, di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin, Bandung.
Dante menilai, pelaksanaan tes kejiwaan akan menilai peserta PPDS tak hanya pintar, tetapi juga tidak punya gangguan kejiwaan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Dante menegaskan, tugas mulia profesi dokter seharusnya dijalani sepenuh hati dan tak sesekali tergoda menyalahgunakan wewenang melanggar sumpah dokter.
“MMPI ini pemeriksaan untuk kesehatan jiwa terlebih lagi untuk yang berkaitan menggunakan obat-obat bius seperti program anestesi ini,” ujar Dante kepada wartawan di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (10/4/2025).
Tak Cukup Tes Kesehatan Mental
Kasus kekerasan seksual oleh dokter lain di Garut bisa menjadi penegas darurat masalah moral profesi dokter. Dokter itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Diduga, jumlah korban lebih dari satu karena beberapa di antara mereka sudah bersuara atau bercerita di media sosial.
Beredar pula rekaman CCTV yang diduga rekaman kejadian pemeriksaan di ruangan dokter kandungan tersebut di Garut, Jawa Barat. Terlihat di rekaman itu, tangan sang dokter tidak hanya memegang perut dan alat USG, namun juga masuk ke baju bagian dada korban.
Menanggapi kasus tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa Kemenkes telah berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dokter obgyn yang diduga melakukan kekerasan seksual tersebut. Penonaktifan sementara ini dilakukan sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Polisi juga turun tangan mengusut kasus ini.
“Kemenkes sudah koordinasi dengan KKI untuk menonaktifkan sementara STR-nya (Surat Tanda Registrasi) sambil menunggu investigasi lebih lanjut,” kata Aji lewat pesan singkat, Selasa (15/4/2025).
Associate Professor Public Health Monash University Indonesia, Grace Wangge, melihat bahwa gangguan kesehatan mental mungkin memicu/faktor risiko terjadinya tindakan di luar kenormalan oleh seseorang, bahkan seorang dokter. Faktor risiko ini menimbulkan masalah lebih besar jika pemicunya, salah satunya adalah faktor lingkungan kerja serta beban kerja.
 Header Indepth Kekurangan Dokter. tirto.id/Ecun
Header Indepth Kekurangan Dokter. tirto.id/Ecun
Grace menilai fenomena ini bukan hanya spesifik menimpa peserta PPDS, namun rata-rata semua profesi dengan tekanan kerja yang tinggi. Mencegah tindak amoral seperti kekerasan seksual, kata dia, seharusnya dilihat bukan sebatas level individu lewat masalah kesehatan mental saja.
“Tapi bagaimana lingkungan dan beban kerja memicu tindakan tersebut, dan bagaimana lingkungan gagal mencegah terjadinya kasus,” kata Grace kepada wartawan Tirto, Selasa (15/4/2025).
Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS di RSHS, Grace memandang fokus perhatian pemangku kebijakan hanya ditujukan bahwa kejadian terjadi sebab masalah individu dengan kesehatan mentalnya. Sayangnya, cara pandang itu luput melihat masalah lingkungan kerja dan kultur sistemik tempat kasus terjadi. Dalam hal ini, RS sebagai sebagai institusi gagal melindungi pasien dan keluarga pasien dari kejahatan di dalam rumah sakit.
Dalam pendidikan kedokteran, kata Grace, materi etika diberikan berulang-ulang semenjak tingkat pertama. Apabila kemudian masih terjadi pelanggaran etika, maka dapat ditinjau soal bagaimana etika tersebut diajarkan dan dipraktikan di lingkungan tenaga kesehatan.
Atas kejadian ini, Grace menekankan sistem perlindungan pasien dan keluarganya di rumah sakit. Bukan hanya keamanan terhadap obat dan tindakan medis, tetapi sampai keamanan mereka di lingkungan rumah sakit secara fisik dan bahkan keamanan data pasien.
“Jadi jelas menurut saya tes kesehatan mental tidak akan pernah menyelesaikan masalah (bukan tidak akan secara instan), karena tes ini sifatnya skrining, tidak menjamin,” ujar dia.
“Dan mengapa hanya PPDS, bagaimana dengan nakes yang sudah bertugas, mereka juga perlu di tes berkala dan kemudian dicari akar masalah dari problem yang timbul,” imbuh Grace.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mahesa Paranadipa Maikel, mengingatkan bahwa tes kesehatan mental membantu mengidentifikasi potensi masalah kesehatan kejiwaan peserta PPDS, namun tidak bisa langsung mencegah tindakan amoral atau kekerasan seksual.
Terlebih, ia memandang terdapat keterbatasan dalam tes kesehatan mental. Mahesa menilai tidak ada tes yang sempurna, alias tidak bisa memprediksi tindak kekerasan seksual dengan akurasi seratus persen.
Dalam tindakan kekerasan seksual, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku: seperti lingkungan, budaya, dan pengalaman.
 Ilustrasi Kekerasan Seksual. foto/Istockphoto
Ilustrasi Kekerasan Seksual. foto/Istockphoto
Ia memberikan rekomendasi pendekatan lebih komprehensif lewat pendidikan dan pelatihan tentang etika, moral, serta pencegahan kekerasan seksual yang lebih ketat agar membantu meningkatkan kesadaran.
Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring yang efektif pada perilaku individu tenaga kesehatan agar mencegah perilaku kekerasan seksual. Terpenting, dibuat sistem pelaporan yang efektif dengan sistem pelaporan kekerasan seksual yang dapat memastikan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani dengan cepat dan efektif.
“Serta memberikan sanksi yang tegas kepada dokter residen atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan amoral atau kekerasan seksual. Dengan demikian, pencegahan tindak amoral atau kekerasan seksual di rumah sakit atau faskes memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak,” terang Mahesa kepada wartawan Tirto, Selasa (15/4).
tirto.id - Kesehatan
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Alfons Yoshio Hartanto

 1 month ago
95
1 month ago
95