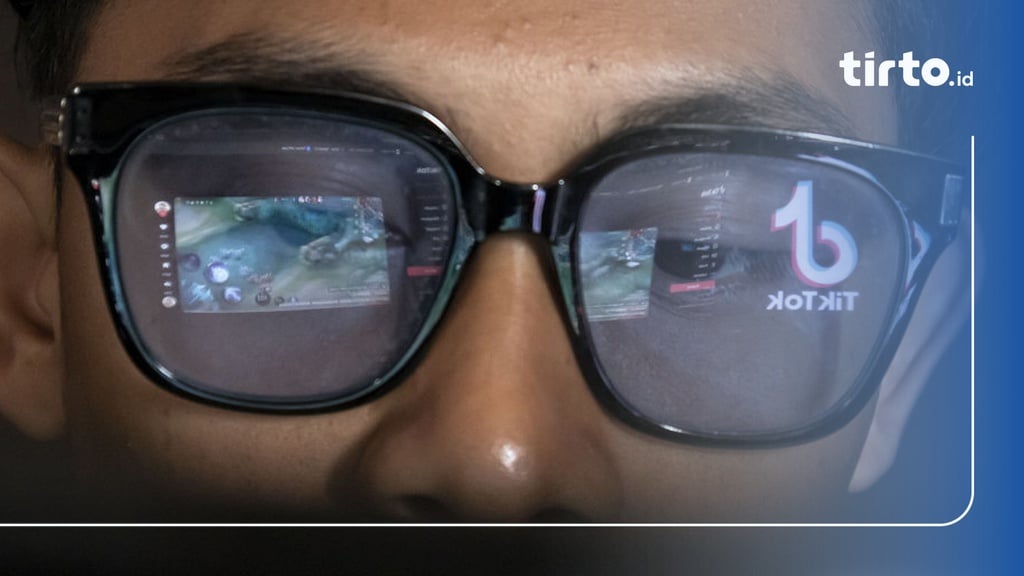tirto.id - World Bank atau Bank Dunia dalam laporan berjudul ‘Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia’ menyebut Indonesia telah kehilangan potensi penerimaan pajak hingga Rp944 triliun atau setara 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada rentang tahun 2016-2021.
Hal ini terjadi akibat lebarnya kesenjangan pembayaran pajak untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dibayarkan korporasi atau perusahaan.
Potensi penerimaan negara yang hilang dari PPN disebabkan oleh kebijakan pembebasan pajak untuk produk makanan mentah, pendidikan, layanan kesehatan, dan perhotelan. Sementara itu, dari PPh Badan, kerugian pendapatan pajak berasal dari pengecualian untuk perusahaan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar serta diskon tarif untuk perusahaan memiliki pendapatan di bawah Rp50 miliar.
“Kesenjangan kepatuhan PPh Badan dan PPN berkontribusi terhadap 58 persen dari total pendapatan nominal yang hilang,” bunyi laporan yang ditulis Rong Qian dan Grzegorz Poniatowski tersebut, dikutip Jumat (28/3/2025).
Dari perhitungan Bank Dunia, rata-rata kesenjangan antara PPN yang seharusnya dibayar dengan realisasi PPN yang diterima negara mencapai 43,9 persen atau senilai Rp386 triliun, setara 2,6 persen PDB tahun 2016-2021.
Sementara itu, rata-rata kesenjangan antara PPh Badan yang seharusnya dibayar perusahaan dengan PPh Badan yang diterima negara mencapai 33 persen, atau senilai Rp160 triliun, yang setara dengan 1,1 persen dari PDB pada periode 2016-2021.
“Karena kesenjangan kepatuhan yang besar dan rezim pajak alternatif untuk PPN dan PPh Badan, nilai kesenjangan kebijakan perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Perusahaan kecil dan banyak penyedia layanan saat ini dikenai pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah. Karena ketidakpatuhan di antara para wajib pajak ini kemungkinan sangat tinggi,” jelas laporan yang terbit 2 Maret 2025 itu.
Sebab, tingginya kesenjangan penerimaan dan ketidakpatuhan masyarakat maupun perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya membuat rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi salah satu yang terendah di dunia, yakni hanya mencapai 9,1 persen di 2021.
 Ilustrasi Bank Dunia. foto/istockphoto
Ilustrasi Bank Dunia. foto/istockphoto
Padahal, pada saat yang sama, rasio pajak Kamboja sebesar 18,0 persen, Malaysia 11,9 persen, Filipina 15,2 persen, Thailand 15,7 persen, dan Vietnam 14,7 persen. Sebaliknya, rasio ketidakpatuhan Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara berkembang di dunia.
“Indonesia telah mengalami tren negatif yang mengkhawatirkan dalam rasio penerimaan pajak terhadap PDB selama dekade terakhir. Dibandingkan dengan rasio pajak sepuluh tahun lalu, angka tahun 2021 mencerminkan penurunan sekitar 2,1 poin persen. Krisis Covid-19 memperparah masalah ini, mengakibatkan penurunan tajam menjadi 8,3 persen dari PDB pada tahun 2020,” sebut laporan itu.
Karena kondisi ini, Bank Dunia memandang Indonesia perlu segera menangani masalah kesenjangan kepatuhan secara paralel dengan perbaikan kebijakan perpajakan, terutama terkait pemungutan PPN dan PPn Badan. Sebab, jika kesenjangan terus terjadi karena ketidakpatuhan, setidaknya negara akan kehilangan potensi penerimaan hingga Rp546 triliun per tahun.
Bank Dunia menemukan tingginya tingkat ketidakpatuhan serta aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) yang mencapai 17,6-21,8 persen terhadap PDB. Hal tersebut dipicu oleh besarnya sektor usaha informal, semakin memperburuk kesenjangan dalam kepatuhan pembayaran pajak.
“Sayangnya, estimasi terbaru tentang kesenjangan kepatuhan dalam pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak tersedia. Bukti sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah pendapatan pajak yang hilang akibat ketidakpatuhan dapat melebihi perkiraan ekonomi bawah tanah,” tulis World Bank.
Peneliti Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menuturkan, masalah kepatuhan pajak yang dilaporkan oleh Bank Dunia bukanlah hal baru. Berbagai lembaga keuangan internasional juga telah lama menyoroti isu ini, yang menyebabkan rasio pajak Indonesia stagnan bahkan cenderung menurun dalam dekade terakhir.
Sebagai contoh, pada 2014 rasio pajak Indonesia tercatat hanya 10,85 persen terhadap PDB, dan turun sedikit menjadi 10,76 persen pada tahun berikutnya. Pada 2024, rasio pajak Indonesia kembali anjlok ke angka 10,07 persen, seiring dengan penerimaan pajak sepanjang 2024 yang hanya mencapai Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp1.988,9 triliun.
Kondisi ini lantas menjadi momok yang belum juga bisa diselesaikan. Apalagi, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia. Berdasar data Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), pada 2024 Indonesia menjadi negara terkaya ke-8 di dunia, dengan PDB per kapita sebesar 4,98 triliun dolar Amerika Serikat (AS).
“Tetapi kalau dilihat dari ukuran pajaknya itu kecil, itu isu pertama,” kata Yusuf, kepada Tirto, Jumat (27/3/2025).
Kondisi ini juga menggambarkan sektor usaha di Tanah Air masih didominasi oleh sektor informal yang sulit dipajaki karena skala dan omzet yang terlalu kecil. Hal ini pun sudah dirangkum pula oleh laporan bank dunia.
Dominasi sektor informal ini telah dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana per Agustus 2024 jumlah pekerja dari sektor ini mencapai 57,95 persen dari total penduduk atau setara 83,8 juta jiwa. Sedangkan jumlah pekerja formal masih tercatat sebanyak 60,82 juta jiwa atau sekitar 42,05 persen dari total penduduk.
“Jadi memang informalitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong pajak yang lebih tinggi, karena ketika usaha informal itu lebih besar jumlahnya, maka ada kriteria tertentu yang mengikuti di dalamnya. Sehingga, ketika pemerintah ataupun otoritas ingin memajaki, kriteria ini yang kemudian muncul, sehingga penarikan pajaknya tidak lebih besar,” jelas Yusuf.
 Petugas melayani wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (26/2/2025).ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.
Petugas melayani wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (26/2/2025).ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.
Penegakan hukum terhadap pengemplang pajak masih kurang tegas, sehingga tidak efektif memberikan efek jera. Nihilnya penegakan hukum terkait kasus pengemplangan pajak, seperti yang terungkap dalam Panama, Paradise, dan Pandora Papers, melibatkan nama-nama besar pejabat negara, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya otoritas pajak.
Kepercayaan masyarakat semakin tergerus setelah terungkapnya fakta sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha besar.
“Itu saya pikir juga mempengaruhi persepsi publik atau masyarakat secara umum dalam kepatuhan membayarkan ataupun kepatuhan melaporkan pajaknya,” terang Yusuf.
Padahal, melalui upaya pengurangan beban pajak -tax evasion ini, negara yang harusnya dapat mengantongi misalnya Rp100 miliar dari memajaki perusahaan-perusahaan besar tersebut, jadi hanya menerima Rp10 miliar pajak.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menuturkan, tax evasion, biasanya selalu melibatkan orang-orang yang berada di lingkungan otoritas perpajakan. Sementara itu, penerimaan yang kecil akibat tingginya tingkat ketidakpatuhan pembayaran pajak membuat fleksibilitas pemerintah dalam mendorong belanja negara menjadi terbatas. Sehingga, untuk merealisasikan belanja yang benar-benar dibutuhkan, tak jarang utang baik utang melalui penerbitan surat utang pemerintah maupun utang luar negeri menjadi jalan keluar.
“Paling besar itu salah satunya itu (tax evasion). Jadi, kita bisa melihat di sini terjadi kontradiksi bahwa ekonomi kita itu secara pertumbuhan dan PDB-nya besar, sementara tax yang ditarik pemerintah kecil,” kata Ronny, kepada Tirto, Jumat (28/3/2025).
Idealnya, sebagai negara dengan salah satu ekonomi terbesar di dunia, rasio pajak Indonesia berada di kisaran 11-12 persen. Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pengemplang pajak, baik itu yang melakukan dengan cara tax evasion maupun tax avoidance (penghindaran pajak), Ronny, menilai Indonesia dapat mencapai rasio pajak di angka 12 persen.
Tidak hanya itu, kebijakan perpajakan tampaknya perlu dirombak untuk menghilangkan peluang dan celah bagi mereka yang berniat melakukan penghindaran pajak.
“Karena seperti yang saya bilang tadi, orang harusnya dipajaki Rp100 miliar, dia cuma bayar Rp10 miliar. Itu kan besar banget (potensi penerimaan negara) yang hilang. Yang kaya cuma segelintir orang, yang korupsi, orang pajaknya, konsultan pajak, itu yang kaya, sama pengusahanya,” kata Ronny.
 Ilustrasi Pajak. foto/istockphoto
Ilustrasi Pajak. foto/istockphoto
Pada saat yang sama, peningkatan kerja sama internasional, seperti melalui ratifikasi Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) - salah satu instrumen penerapan pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat dianggap perlu untuk memitigasi terjadinya aktivitas penghindaran pajak.
“Termasuk di dalam penerapan pajak minimum global. Artinya, pemerintah juga harus melakukan penyesuaian dari pajak minimum global ini dengan ketentuan, misalnya di dalam negeri yang berkaitan, misalnya ketentuan seperti pemberian insentif pajak,” jelas Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.
Di sisi lain, untuk meningkatkan pajak pemerintah juga bisa meminimalkan aktivitas ekonomi bawah tanah dengan cara meningkatkan kelas usaha di sektor informal. Salah satu caranya yaitu menaikkan kapasitas produksi dan omzet usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah.
“Mungkin perlu diedukasi kepada para pelaku UMKM, agar mereka semangat ataupun bisa didorong naik kelas. Ini juga akan berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak dari sektor formal terutama,” ungkap Yusuf.
Menanggapi laporan Bank Dunia ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan, pihaknya akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Harapannya upaya ini dapat mendongkrak rasio pajak nasional.
“Dengan menempuh berbagai upaya, antara lain perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement, pengawasan wajib pajak, peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence,” jelas Dwi, melalui pesan singkatnya, kepada Tirto, dikutip Jumat (28/3/2025).
tirto.id - Ekonomi
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Intan Umbari Prihatin

 2 months ago
72
2 months ago
72