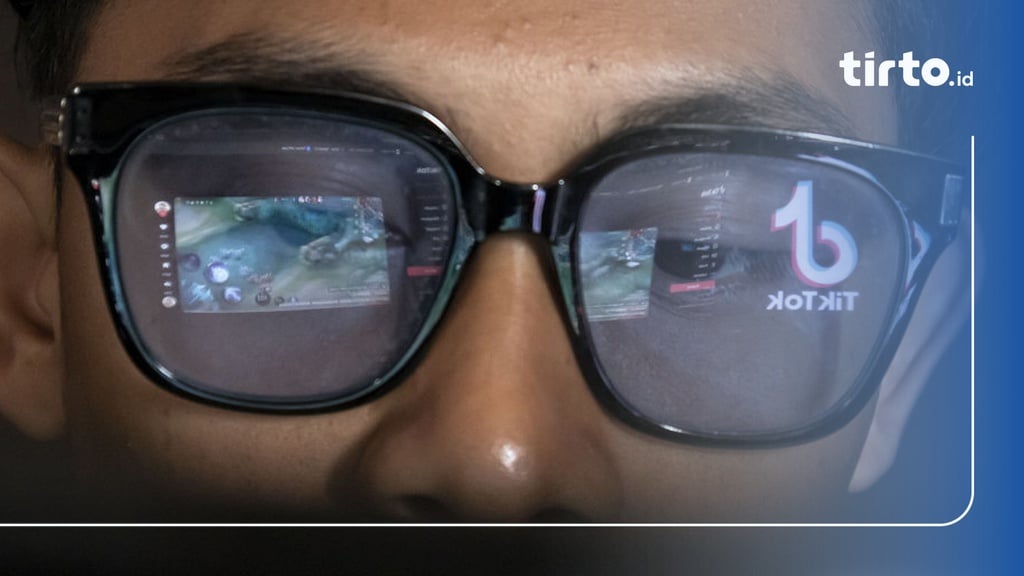tirto.id - Dalam dunia kerja, banyak karyawan yang merasa gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung. Selain itu, stagnasi jabatan yang membuat karier tak kunjung berkembang sering kali menjadi sumber kekecewaan.
Tidak jarang, kondisi ini disalahartikan sebagai akibat dari kurangnya usaha atau prestasi individu. Ini bermula dari konsep yang dikenal dengan meritokrasi, yang secara harfiah berarti sistem penghargaan berdasarkan prestasi, seolah-olah menawarkan kesetaraan kesempatan bagi semua orang untuk sukses asalkan mereka bekerja keras dan menunjukkan kemampuan yang memadai.
Namun, apakah benar gaji rendah atau kurangnya kesempatan hanya disebabkan oleh kurangnya usaha individu? Apakah meritokrasi benar-benar diterapkan secara adil, ataukah ia hanya mitos yang menutupi kompleksitas sosial dan ekonomi yang lebih luas?
Meritokrasi: Prinsip Dasar dan Harapan
Meritokrasi berakar pada prinsip bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan berdasarkan usaha, kecerdasan, dan prestasi. Dalam konteks dunia kerja, ini berarti gaji, promosi, dan pengakuan seharusnya diberikan berdasarkan kontribusi nyata seseorang terhadap organisasi atau perusahaan.
Meritokrasi merupakan sistem yang memprioritaskan kemampuan dan prestasi individu, namun penerapannya dapat memperparah ketimpangan jika tidak mempertimbangkan kondisi sosial yang kerap tidak setara.
Secara sederhana, meritokrasi menekankan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Dengan demikian, meritokrasi mendorong individu untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan memberikan kemampuan terbaik.
Prinsip ini juga bertujuan untuk menghilangkan bias-bias yang sering kali menghambat kemajuan seseorang di tempat kerja. Misalnya, dalam sistem yang tidak meritokratis, keputusan terkait promosi atau penghargaan pekerja mungkin dipengaruhi oleh suka tidak suka, nepotisme, atau diskriminasi.
Di Indonesia, meritokrasi diterapkan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014. Konsep tersebut tampak adil secara permukaan karena menawarkan penghargaan bagi mereka yang bekerja keras dan menunjukkan hasil yang baik. Namun, masalah muncul ketika kita menyadari bahwa kesempatan yang "sama" tidak selalu berarti adil.
Meski meritokrasi bertujuan untuk menghilangkan bias, sering kali bias tidak sadar tetap memengaruhi keputusan manajerial. Misalnya, penilaian terhadap seseorang dengan latar belakang tertentu atau stereotipe gender dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja seseorang.
Sayangnya, meritokrasi juga dapat menciptakan ilusi mobilitas sosial yang tinggi, seolah-olah setiap orang dapat "meraih mimpi" mereka asalkan mereka bekerja keras. Padahal faktor-faktor seperti latar belakang sosial, pendidikan, akses terhadap jaringan, dan bahkan keberuntungan sering kali berperan penting dalam menentukan kesuksesan seseorang.
Misalnya, seseorang yang lahir dalam keluarga dengan sumber daya ekonomi yang terbatas mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau jaringan profesional, yang akhirnya dapat membatasi peluang mereka di dunia kerja meskipun mereka bekerja keras sepanjang hayat.
Beberapa studi menunjukkan ada hambatan bagi perempuan dalam mencapai jabatan dan upah tinggi di birokrasi dan pendidikan, meskipun sistem meritokrasi diterapkan.
 Ilustrasi Buruh Karyawan. foto/istockphoto
Ilustrasi Buruh Karyawan. foto/istockphoto
Keterbatasan Meritokrasi dalam Menjelaskan Gaji Rendah
Meritokrasi sering kali mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi kesempatan seseorang untuk sukses. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi masalah yang mendasar.
Anak-anak dari keluarga kaya kerap memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, pelatihan ekstrakurikuler, dan koneksi profesional yang dapat membuka pintu bagi karier yang sukses.
Sebaliknya, mereka yang berasal dari keluarga dengan sumber daya terbatas harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk menginvestasikan waktu dan uang dalam pendidikan dan pengembangan diri.
Salah satu kendala struktural yang paling menonjol adalah diskriminasi dalam berbagai bentuk, baik berdasarkan gender, usia, suku, agama, atau latar belakang pendidikan. Misalnya, karyawan perempuan sering kali menerima gaji lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki beban kerja yang sama.
Selain itu, karyawan yang berasal dari kelompok minoritas atau latar belakang tertentu mungkin juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan promosi jabatan, meskipun mereka memiliki kompetensi yang memadai. Diskriminasi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat potensi perkembangan perusahaan secara keseluruhan.
Satu makalah akademis menganalisis dampak ketimpangan upah, perubahan teknologi yang bias keterampilan dan perubahan teknologi yang netral keterampilan pada pasar tenaga kerja di Jerman.
Studi yang diambil dari catatan administratif Jerman yang mencakup tahun 1975-2014 tersebut mengulas guncangan ketimpangan struktural yang berdampak negatif pada produktivitas, upah, dan jam kerja. Ketimpangan di bawah upah rata-rata memiliki dampak yang lebih merusak daripada ketimpangan di atas upah rata-rata.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa prestasi individu saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan jika sistemnya masih dipengaruhi oleh prasangka dan ketidakadilan struktural.
Seturut survei Cigna yang melibatkan 12.000 pekerja, umumnya generasi Z sangat khawatir tentang keuangan mereka, lebih dari generasi lainnya. 39 persen Gen Z menganggap ketidakamanan finansial sebagai penyebab stres utama mereka, lebih tinggi dibandingkan 34 persen milenial dan 29 persen pekerja berusia 50 hingga 64 tahun. Pekerja yang lebih muda ini khawatir tentang kenaikan biaya hidup dan dampaknya terhadap masa depan mereka.
Anggapan bahwa gaji rendah semata-mata disebabkan oleh kurangnya kerja keras atau usaha individu adalah kesimpulan yang berbahaya. Realitasnya, banyak faktor eksternal yang memengaruhi tingkat gaji seseorang, termasuk kebijakan perusahaan, kondisi pasar kerja, dan sistem ekonomi secara keseluruhan.
Misalnya, di sektor-sektor tertentu seperti buruh pabrik, gaji rendah mungkin lebih disebabkan oleh rendahnya nilai yang diberikan oleh masyarakat atau pemerintah terhadap jenis pekerjaan tersebut, bukan karena kurangnya usaha dari para pekerja.
Bahkan sekitar 60 persen pekerja di Indonesia berada di sektor informal dengan penghasilan rata-rata hanya Rp 1,7 juta per bulan.
Di sisi lain, beberapa posisi dengan tanggung jawab yang lebih ringan mungkin menerima gaji tinggi karena faktor seperti koneksi atau status sosial. Ini menunjukkan bahwa meritokrasi sering kali tidak berlaku dalam praktik, dan gaji tidak selalu mencerminkan usaha atau prestasi individu.
Selain diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja juga menjadi masalah yang sering diabaikan. Banyak perusahaan yang memanfaatkan ketidakberdayaan karyawan dengan memberikan upah yang jauh di bawah standar, padahal beban kerja yang ditanggung membutuhkan tenaga dan waktu yang besar.
 Ilustrasi Buruh Karyawan. foto/istockphoto
Ilustrasi Buruh Karyawan. foto/istockphoto
Selain itu, hubungan antara gaji dan produktivitas tidak selalu linear. Fenomena ini sering terjadi di sektor swasta, khususnya ritel, pertanian, dan jasa, terutama pada perusahaan yang tidak memiliki sistem penggajian yang transparan dan adil. Karyawan, terutama yang bekerja di level bawah, sering kali tidak memiliki kekuatan tawar untuk menuntut perbaikan gaji atau kondisi kerja yang lebih layak.
Dalam sistem ekonomi yang tidak merata, kesenjangan antara karyawan level bawah dan manajemen sering kali sangat lebar. Di banyak negara, kesenjangan antara gaji eksekutif dan pekerja level bawah sangat besar.
Studi Oxford Open Economics, menemukan ketimpangan gaji Chief Executive Officer (CEO) di Inggris. Ini terlihat dari paket kompensasi CEO untuk perusahaan FTSE 100 yang mencapai sekitar £5,1 juta dan £3,8 juta sejak awal 2010-an. Rasio gaji CEO terhadap rata-rata gaji karyawan mencapai 119:1 pada tahun 2019, melahirkan kesenjangan pendapatan yang ekstrem di dalam perusahaan.
Karyawan dengan jabatan rendah cenderung sulit untuk menikmati kenaikan gaji yang diinginkan, sementara posisi-posisi strategis mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar.
Ini juga membuktikan bahwa struktur ekonomi dan kebijakan perusahaan sering kali lebih berpengaruh daripada kerja keras individu.
Meritokrasi sebagai Mitos yang Menyesatkan
Dalam banyak kasus, meritokrasi sering digunakan untuk membenarkan kesenjangan sosial dan ekonomi dengan menyalahkan individu atas kegagalan mereka, sambil mengabaikan faktor-faktor sistemik yang membatasi kesempatan.
Misalnya, ketika seseorang tidak dapat mencapai kesuksesan secara finansial, sering kali mereka dianggap tidak cukup bekerja keras atau tidak memiliki kemampuan yang cukup, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka mungkin menghadapi rintangan struktural yang sulit diatasi.
Akibatnya, meskipun individu tersebut memiliki bakat dan kerja keras, mereka tetap terbatas oleh kondisi sistemik.
Mereka yang gagal sering dianggap kurang berusaha atau tidak memiliki kemampuan yang cukup. Pandangan seperti ini tidak hanya merendahkan individu yang berjuang dalam sistem yang tidak adil, tetapi juga mengalihkan perhatian dari akar masalah struktural yang sebenarnya.
Kritik lain terhadap meritokrasi adalah konsep ini sering digunakan untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan kelompok yang telah mapan. Dengan menekankan bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha individu, meritokrasi menutupi ketidakadilan sistemik yang menguntungkan kelompok tertentu sambil merugikan kelompok lain.
Misalnya, di banyak negara, praktik diskriminasi dalam perekrutan kerja atau pendidikan masih terjadi, namun hal ini sering diabaikan dengan alasan bahwa individu yang berprestasi akan selalu menemukan jalan mereka sendiri. Padahal, tanpa perubahan sistemik, kesempatan yang adil tidak akan pernah terwujud.
Yustiana Dwirainaningsih dalam jurnalnya menyebut penyerapan tenaga kerja di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini disebabkan oleh upah yang diterima pekerja lebih rendah dari kebutuhan hidup layak (KHL) dan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP).
Meskipun meritokrasi sering dianggap sebagai sistem yang ideal, kenyataannya konsep ini sering kali menjadi mitos yang menutupi ketidakadilan struktural.
Alih-alih menyalahkan individu karena "tidak bekerja keras", penting untuk melihat masalah gaji rendah dari perspektif sistemik. Perlu ada upaya kolektif untuk menciptakan sistem yang lebih adil, seperti meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi semua kalangan, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak buruh, mendorong transparansi dalam penetapan gaji, dan mengurangi bias dan diskriminasi struktural di tempat kerja.
Hanya dengan itu kita dapat menciptakan dunia kerja yang benar-benar menghargai usaha dan prestasi, tanpa mengabaikan kompleksitas realitas yang dihadapi oleh masing-masing individu dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan.
tirto.id - Mild report
Kontributor: Ali Zaenal
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi

 2 months ago
106
2 months ago
106