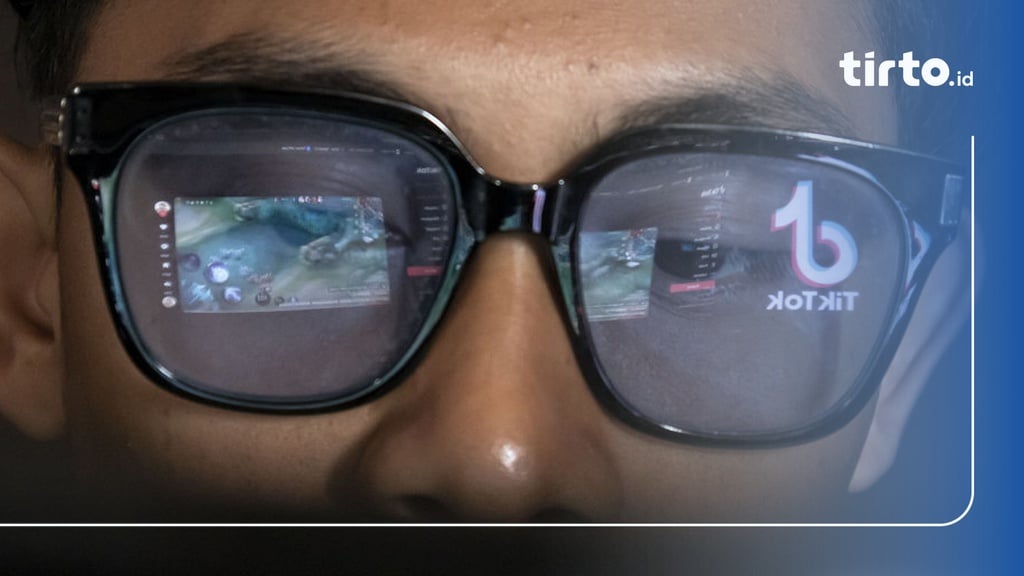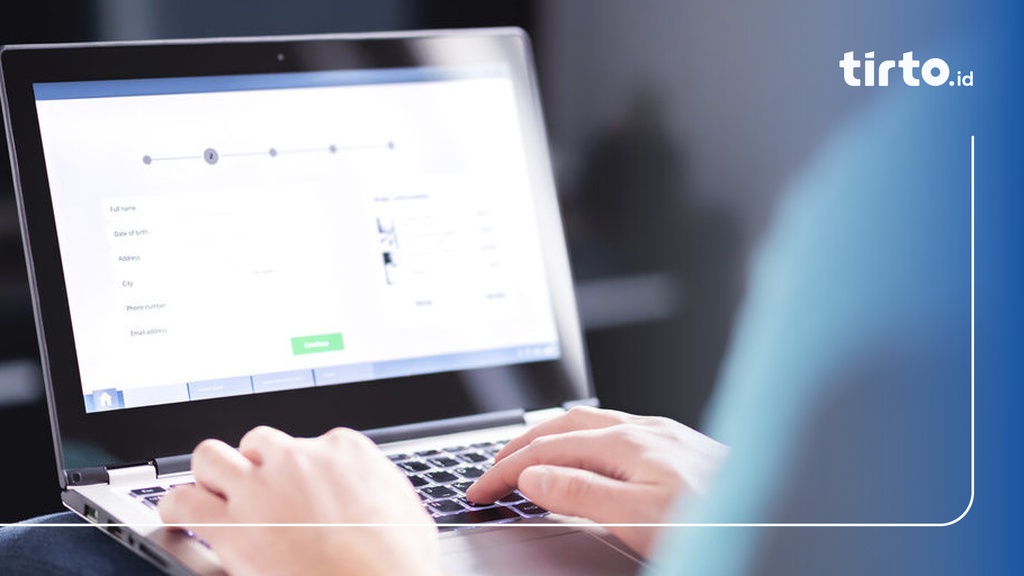tirto.id - Aksi eksibisionisme di layanan publik, salah satunya di KRL, masih terus berulang. Pelaku seakan tak punya kesadaran–atau bahkan pengetahuan, kalau aksinya termasuk pelecehan seksual yang mengancam ruang aman, terutama bagi perempuan dan minoritas gender lainnya.
Di saat setiap perempuan punya hak untuk merasa aman di ruang publik, termasuk di transportasi umum, survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) justru menunjukkan selama pandemi COVID-19, sebanyak 4 dari 5 Perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (79 persen dari 3.539 Perempuan).
Perempuan dan gender minoritas lainnya tercatat memiliki kecenderungan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik 6 kali lebih besar ketimbang laki-laki selama pandemi COVID-19.
Lima lokasi paling populer dengan kejadian pelecehan seksual secara offline paling banyak yakni ruang publik seperti jalanan umum atau taman, kawasan pemukiman, transportasi umum termasuk sarana dan prasarananya, toko, mal, dan pusat perbelanjaan, serta tempat kerja.
Baru-baru ini misalnya, aksi eksibisionisme terjadi di KRL dengan tujuan Parung Panjang – Tanah Abang. Pelaku diketahui melakukan masturbasi dan mengarahkan cairan spermanya ke bagian belakang tubuh korban, tepatnya di area pantat. Korban yang sempat merasa risih dan curiga, baru menyadari adanya cairan asing menempel setelah keluar dari stasiun Tanah Abang.
Setelahnya, korban lalu melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Merespons laporan itu, tim gabungan dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Gambir, dan petugas keamanan KAI, lantas menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan tim gabungan terhadap pelaku mengungkap bahwa pelaku melakukan perbuatannya secara sadar tanpa pengaruh gangguan jiwa.
Meski penyidik kepolisian sempat menjerat pelaku dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 juta, kasus ini berujung damai.
Pihak KAI sendiri memberikan sanksi kepada pelaku berupa blacklist. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menegaskan pihaknya akan memasukkan pelaku ke daftar hitam sehingga pelaku tak bisa lagi memanfaatkan layanan KRL.
"Dengan langkah ini, pelaku tak bisa lagi menggunakan Commuter Line untuk mencegah terulang kejadian serupa ke depannya," katanya, Rabu (16/4/2025). Langkah yang sama juga diambil KAI saat aksi eksibionis terjadi 2024 lalu.
Masalahnya, sanksi semacam itu tidak menyentuh akar masalah. Peneliti Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Wawan Kurniawan, menyatakan blacklist pelaku eksibisionisme di KRL hanya memberi efek jera sesaat. Namun, pelaku bisa saja pindah ke ruang publik lain dan mengulang aksinya.
“Solusi jangka panjang butuh pendekatan yang lebih menyeluruh—bukan hanya hukuman, tapi juga terapi psikologis, penegakan hukum yang konsisten, serta pembentukan norma sosial yang tegas terhadap pelecehan. Kita juga butuh ruang publik yang lebih aman dan masyarakat yang berani bersuara, agar pelaku tahu perilaku seperti ini tak akan pernah ditoleransi di mana pun,” ucap Wawan kepada Tirto, Kamis (17/4/2025).
Eksibisionisme sendiri tergolong dalam kelainan seksual. Menukil artikel Alodokter yang sudah ditinjau secara medis, disebutkan bahwa penderita kondisi ini mendapatkan kepuasan seksual dari memperlihatkan alat vitalnya kepada orang yang tidak dikenal. Selain benar-benar memperlihatkan alat vital, ada juga penderita eksibisionis yang bisa mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan membayangkan dirinya memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
Menurut Wawan, eksibisionisme bukan cuma soal hasrat seksual, melainkan juga soal kekuasaan. Pelaku sering kali ingin menunjukkan dominasi dan mencari kepuasan dari rasa takut atau terkejut korban.
“Ini bukan tindakan spontan semata, tapi tumbuh dari budaya yang masih memandang perempuan sebagai objek dan kurang memberikan tekanan sosial terhadap pelaku pelecehan. Ketika ruang publik dibiarkan tanpa pengawasan sosial yang kuat, pelaku merasa bebas dan aman melakukan aksinya. Artinya, ini bukan hanya soal individu yang menyimpang, tapi juga soal norma sosial yang membiarkannya tumbuh,” ujar Wawan.
Urgensi Mengubah Mindset
Kekerasan seksual sebenarnya didorong oleh cara pandang masyarakat yang melihat perempuan sebagai objek. Program Director Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist) yang juga menjadi bagian dari KRPA, Anindya Nastiti Restuviani, menegaskan bahwa pelecehan seksual yang terjadi dalam konteks laki-laki kepada perempuan merupakan konteks di mana seksisme sejenis itu terjadi, ditambah pula pembiasaan-pembiasaan dari hal tersebut.
“Nah, cuman kan kalau misalkan dalam konteks satu kasus, misalkan kita ngomongin eksibisionis yang ini, ya kita nggak tahu layer-nya apa aja. Bisa jadi ya tadi, dia punya kelainan, dan lain-lain, yang memang harus didiagnosa secara profesional,” ucap Vivi lewat sambungan telepon, Kamis (17/4/2025).
Tapi kembali lagi, kata Vivi, karena adanya normalisasi, orang tidak pernah melihat ini sebagai sesuatu yang krusial untuk diselesaikan. Dengan demikian pelaku bisa terus melakukan kekerasan selama tidak pernah ada yang menegur.
“Selama ini nggak pernah ada yang memberikan sanksi, atau bahkan selama ini nggak ada yang pernah kasih tahu, bahwa perilaku-perilaku seperti itu sebetulnya nggak benar gitu kan ya. Akhirnya mereka menganggap ini adalah hal yang biasa, dan akhirnya terus dilakukan. Dan memang nggak mudah untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Vivi.
Vivi pun menyampaikan pendapat yang senada dengan Wawan soal sanksi blacklist terhadap pelaku aksi eksibisionisme. Menurutnya, meski pelaku sudah tidak bisa menaiki KRL, tapi misal dia tidak didampingi dan diberitahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, dia bisa melakukannya di tempat lain.
Adanya gerbong KRL khusus perempuan yang sebenarnya sudah difungsikan sejak 2010 pun dinilai Vivi kurang efektif. Sebab, dengan adanya gerbong perempuan, kekerasan seksual masih marak terjadi.
“Tapi memang bentuk-bentuk pengadaan gerbong perempuan, karena di Transjakarta kan juga ada bagian yang khusus untuk perempuan, itu kan bentuk-bentuk affirmative action. Tapi kalau kita ngomongin tentang equality, ini enggak substantif gitu. Karena ini modalnya protektif jadinya, jadi menganggap bahwa ya sudah kita kurung aja perempuannya, sedangkan laki-lakinya yang akar masalahnya, yaitu mereka yang melakukan pelecehan, itu mereka malah dibebaskan,” kata Vivi.
 Ilustrasi Kekerasan Seksual. FOTO/iStockphoto
Ilustrasi Kekerasan Seksual. FOTO/iStockphoto
Pada akhirnya, ada segelintir orang yang meyakini bahwa jika perempuan tidak ingin mendapat pelecehan, maka mereka mesti masuk dalam gerbong perempuan. Pola pikir seperti itu harus dibenahi. Karena, perlu digarisbawahi, baik di gerbong perempuan maupun tidak, mereka berhak atas rasa aman. Pelaku juga tidak boleh melakukan pelecehan terlepas dari tempat gerbong korban, lantaran ruang publik adalah milik bersama.
“Kedua, sebetulnya yang paling penting adalah, melatih first responder yang ada di situ juga. Jadi apakah misalkan kayak petugas keamanan, penjaga tiket, dan lain-lain itu paham enggak bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa. Bagaimana mereka bisa merespon dengan perspektif korban, misalkan seperti itu,” lanjut Vivi.
Lebih jauh Vivi bilang, dalam konteks UU TPKS tidak mengenal damai dengan pelaku. Ketika bicara tentang UU TPKS, fokusnya yakni bagaimana kita bisa mengembalikan mental dari korban itu sendiri, di mana ada poin-poin dalam UU TPKS yang memuat soal kewajiban negara dan pelaku untuk rehabilitasi. Jika berujung damai, maka pelaku tidak bisa diberi rehabilitasi alias pembetulan cara pikir.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, juga menyoroti soal penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Katanya, kasus kekerasan seksual di Indonesia harus diselesaikan secara tegas, transparan, dan komprehensif dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begitu pula dengan UU TPKS yang perlu diperkuat kembali pada seluruh instansi, terutama pada fasilitas yang menyangkut hak pelayanan publik, seperti pada instansi pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga transportasi umum. Hal itu harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang aman, bukan justru terancam hak asasi manusianya akibat instansi yang tidak berkomitmen dalam penanganan kekerasan seksual.
“Paradigma yang berorientasi korban perlu kita perjuangkan dengan memberikan pendampingan secara menyeluruh, dan kepastian hukum oleh pemerintah kepada korban agar mereka mendapatkan fasilitas yang memadai dan ruang aman dalam proses rehabilitasi secara mental dan sosial,” ungkap Natasya, lewat keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).
Masih banyaknya kasus kekerasan seksual dinilai Natasya mencerminkan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga para pelaku masih melenggang bebas untuk menjalankan aksinya.
Segala macam bentuk kekerasan seksual harus ditindaklanjuti secara menyeluruh agar tidak semakin banyak korban yang terdampak. Pembentukan satgas di fasilitas publik juga perlu disertai dengan sumber daya pendukung dan pelaksanaan rencana aksi nyata, bukan hanya sekadar formalitas untuk kepentingan citra instansi belaka.
Pemberdayaan satgas yang memadai diharapkan dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk mengadukan kekerasan yang mereka alami dan menindaklanjuti berbagai kasus secara segera tanpa harus menunggu penambahan jumlah korban.
Metode Intervensi “BANTU”
Masyarakat perlu bekerja sama untuk bisa menciptakan ruang publik yang aman bagi semua. Selain itu, penting untuk menjadi active by stander, pendek kata, tidak hanya menjadi saksi yang diam saat menyaksikan kekerasan.
Vivi dari Jakarta Feminist memaparkan tips yang bisa digunakan sebagai metode intervensi. Upaya itu disingkat sebagai “BANTU” yang didesain agar masyarakat bisa melakukan intervensi senyamannya mereka.
“Karena kembali lagi, nggak semua orang nyaman untuk intervensi secara langsung, dan orang suka berpikiran yang namanya intervensi itu, intervensinya cuma secara langsung menegur pelaku, padahal yang namanya intervensi itu kan macam-macam ya,” ucap Vivi.
Pertama, huruf B berarti berani untuk menegur pelaku. Teguran itu tak harus selamanya keras meski di transportasi umum memang harus keras karena situasinya yang urgent. Hal yang bisa dilakukan misalnya mengatakan ke pelaku “gue lihat apa yang lo lakuin, stop it” atau “gue laporin lo ke petugas”.
Selanjutnya A yaitu alihkan perhatian. Alihkan perhatian ini sesederhana pura-pura memberi tempat duduk atau pura-pura menjatuhkan barang. Langkah seperti ini berguna untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pelaku dan pelaku bisa menyadari bahwa tindakannya diawasi.
“Nah N-nya ini emang agak maksa, disingkatnya yaitu ngajak orang lain, untuk membantu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak yakin, kalau itu kekerasan atau bukan, kita bisa ngajak orang di sebelah kita. Misalkan 'kak itu kayaknya, lagi melakukan sesuatu deh, yang membuat kita semua disini nggak nyaman', atau membuat korban itu nggak nyaman, jadi akhirnya kita bisa ada backup,” ujar Vivi.
 Ilustrasi Pelecehan Seksual. FOTO/IstockPhoto
Ilustrasi Pelecehan Seksual. FOTO/IstockPhoto
Itu mengapa pentingnya petugas-petugas di ruang publik memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual dan bagaimana mereka bisa menangani dengan perspektif korban.
Lalu satu poin yang sering dilupakan dalam konteks intervensi adalah bagian “T”, yaitu tanyakan keinginan korban. Hal ini berfungsi untuk mengafirmasi bahwa apa yang terjadi dengan mereka adalah kekerasan.
“Dan kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan, buat mereka untuk membantu. Jadi sesimpel kayak, tadi aku melihat kamu mengalami kekerasan, kira-kira apa yang bisa, saya lakukan untuk membantu kamu, apakah mau ditemenin sampai kamu berhenti di tujuan kamu, mau ditemenin duduk? Itu disini fungsi afirmasi itu tadi,” ungkap Vivi.
Terakhir, U adalah upayakan untuk merekam. Bukan untuk diviralkan tanpa persetujuan korban, rekaman ini berguna untuk bukti saat ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami.
“Karena sekarang kan banyak korban, terus itu diviralin, tanpa persetujuan dari korban itu sendiri. Padahal sebetulnya yang penting adalah, ini direkam. Diberikan kepada korban, untuk akhirnya bisa dibuktikan, bukti, memproses, untuk melaporkan ini kepada pihak yang berwajib,” tutup Vivi.
tirto.id - News
Reporter: Fina Nailur Rohmah
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Anggun P Situmorang

 2 months ago
86
2 months ago
86